Text
Gandum dan Mi Instan: Peluang dalam IA-CEPA
Politik Perdagangan Internasional | 8 Desember 2022
Penandatanganan IA-CEPA menjadi langkah awal bagi Indonesia dan Australia untuk mempererat kerja sama keduanya dalam bidang ekonomi. IA-CEPA memiliki peran penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia sebab meskipun memiliki lokasi geografis yang berdekatan, kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang termasuk rendah. Terlebih lagi, perjanjian ini juga mencakup persoalan-persoalan lain di luar perdagangan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan, seperti pendidikan, keuangan, perdagangan elektronik, dan telekomunikasi. Sebagai sebuah perjanjian yang komprehensif, IA-CEPA diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendorong Indonesia dan Australia dalam memaksimalkan pemanfaatan keunggulan masing-masing untuk kemajuan ekonomi. Hal ini diproyeksikan dapat tercapai melalui pembentukan kolaborasi economic powerhouse antara kedua negara dalam kerangka perdagangan internasional dan ekonomi global. Kolaborasi ini dilakukan dengan memperkuat produktivitas manufaktur dan agrikultur serta meningkatkan ekspor produk tersebut kepada negara atau pihak ketiga (Winanti & Kyle, 2019). Esai ini akan membahas peluang dari ekspor gandum Australia untuk Indonesia dalam membentuk economic powerhouse untuk komoditas mi instan dari Indonesia serta potensi kebermanfaatannya bagi masing-masing negara.
Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan bilateral sejak lama, sekitar paruh kedua tahun 1940-an (Kusumohamidjojo, 1986). Meski demikian, hubungan ini kerap kali diwarnai berbagai perselisihan dan ketegangan politik-keamanan (Kusumohamidjojo, 1986). Pemerintah dari masing-masing negara pun menjadi terlalu berfokus pada perselisihan politik-keamanan dan cenderung mengabaikan aspek-aspek lain dari hubungan mereka, termasuk potensi kerja sama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini ironis sebab baik Indonesia dan Australia mampu menjalin hubungan ekonomi yang baik dan erat dengan negara-negara lain yang tidak berdekatan secara geografis. Selain itu, hal ini juga disayangkan sebab begitu lamanya hubungan bilateral kedua negara telah dibangun namun tidak ada kerja sama yang berjalan ditujukan untuk memaksimalkan perkembangan dan pembangunan ekonomi masing-masing. Menurut Karunaratne (1982), kerja sama ini dapat membantu pembangunan ekonomi di Indonesia yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan, sebuah ancaman bagi keamanan di Australia. Kehadiran IA-CEPA penting untuk mengembangkan kerja sama ekonomi ini. Akan tetapi, perjalanan hubungan ekonomi Indonesia-Australia tidak berhenti pada penandatanganan IA-CEPA saja. Kerangka perjanjian dan proyeksi pencapaian yang telah dirancang tidak dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa analisis kritis mengenai kondisi yang telah ada dalam kaitannya dengan perjanjian tersebut.
Antara kedua negara, Indonesia memiliki spesialisasi dalam produksi komoditas yang berbasis tenaga kerja dan sumber daya (Karunaratne, 1982). Dari sisi Indonesia, optimalisasi produksi komoditas yang seperti ini penting untuk dilakukan agar dapat membantu perkembangan ekonominya. Dalam kaitannya dengan IA-CEPA, optimalisasi ini dapat dilakukan untuk produk yang bahan dasarnya merupakan komoditas ekspor terbesar Australia untuk Indonesia. Dilansir dari data Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, per tahun 2021, komoditas ekspor terbesar Australia untuk Indonesia adalah gandum, yaitu senilai 1.8 milyar Dollar Australia. Terlebih lagi, Indonesia merupakan tujuan pasar gandum Australia terbesar (AEGIC, t.t.). Sebagian besar komoditas gandum ini dijadikan bahan baku untuk produksi mi instan (Sapiie dalam Patunru et al., 2021). Menariknya, mi instan merupakan salah satu komoditas ekspor substantif Indonesia (Sapiie dalam Patunru et al., 2021). Di masa yang akan datang, dengan pengawasan implementasi kebijakan yang baik, gandum dan mi instan berpeluang menjadi komoditas yang mendorong kolaborasi economic powerhouse antara Indonesia dan Australia di bawah kerangka IA-CEPA. IA-CEPA diharapkan mampu meminimalisir berbagai hambatan terhadap komoditas agrikultur Australia yang dieskpor untuk Indonesia, terlebih dengan adanya stagnansi perdagangan barang Australia-Indonesia sejak 2013 (Busch, 2018).
Pada tingkat global, gandum merupakan salah satu bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh banyak orang di berbagai negara. Berdasarkan data pada tahun 2017-2018, gandum dikonsumsi oleh 2.5 milyar penduduk di 89 negara (Culas, 2022). Australia merupakan salah satu eksportir gandum terbesar di dunia dengan jumlah ekspor sebesar 11.4% dari total ekspor gandum global (Culas, 2022). Lebih lanjut lagi, dilansir dari situs Australian Export Grain Innovation Centre, produksi gandum di Australia berorientasi ekspor, dengan mengekspor 65%-75% produksi gandum nasional. Bagi Australia, merawat dan mengoptimalkan ekspor gandum merupakan salah satu langkah yang penting untuk dilakukan. Sebagaimana dinyatakan dalam Cetak Biru untuk Perdagangan dan Investasi dengan Indonesia, Australia tengah menargetkan peluang-peluang untuk pemulihan ekonomi dan keamanan ekonomi. Ekspor gandum dapat membantu Australia dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitan dengan hubungan dagang dengan Indonesia, ekspor gandum memegang peran yang cukup penting. Indonesia menempati posisi kedua di dunia dalam konsumsi mi instan (Kurniawan, 2021). Dengan posisi ini, gandum menjadi komoditas impor yang penting bagi Indonesia.
Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu importir gandum terbesar di dunia (Culas, 2022). Pada kurun waktu 2013-2017, Indonesia menempati peringkat satu sebagai importir gandum dunia (Culas, 2022). Australia pun merupakan mitra dagang gandum Indonesia yang signifikan (Culas, 2022). Agar tercipta keseimbangan, Indonesia dapat memanfaatkan gandum tersebut untuk keperluan ekspor Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar impor gandum Indonesia diolah menjadi mi instan. Kolaborasi economic powerhouse dapat dilakukan dengan menguatkan dan menjaga ekspor mi instan Indonesia. Saat ini, mi instan menempati proporsi 88.49% dari keseluruhan komoditas ekspor produk pasta Indonesia (Kurniawan, 2021). Kemudian, pada tingkat global, Indonesia juga merupakan eksportir mi instan terbesar ketiga setelah Korea Selatan dan Vietnam (Volza, 2022). Meskipun mengalami penurunan pada 2021, nilai ekspor mi instan Indonesia pada 2020 mengalami peningkatan sebesar 22.96% dari nilai ekspor pada tahun 2019 (Kurniawan, 2021). Pasar mi instan terbesar Indonesia adalah Malaysia, dengan peningkatan permintaan dari beberapa negara lain seperti Timor Leste, Kamboja, dan Taiwan (Kurniawan, 2021). Sebagai negara yang masih memiliki kendala dalam hal perkembangan ekonomi, optimalisasi ekspor mi instan dapat menjadi salah satu upaya bagi Indonesia dalam memajukan perekonomiannya. Selain itu, keuntungan yang diperoleh Indonesia dari ekspor mi instan juga dapat membantu Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Kehadiran IA-CEPA patut diapresiasi sebagai upaya untuk membantu perkembangan ekonomi, baik bagi Indonesia maupun bagi Australia. Apresiasi ini tidak cukup dilakukan dengan mengimplementasi isi perjanjian dan pengawasan terhadap implementasi tersebut. Untuk benar-benar mendapat manfaat optimal dari IA-CEPA, perlu dilakukan analisis dan evaluasi rutin, terutama mengenai komoditas tertentu yang berpeluang menguatkan hubungan ekonomi Indonesia-Australia. Ekspor gandum Australia merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia, yakni dalam hal kebutuhan pangan dan untuk keperluan ekspor mi instan. Baik Indonesia maupun Australia perlu merawat perdagangan gandum ini untuk memastikan keuntungan optimal bagi masing-masing negara. Produksi dan ekspor mi instan yang optimal oleh Indonesia pun juga penting untuk mendorong Indonesia sebagai eksportir pangan global dengan komoditas unggulannya. Dengan mengawasi dan menjaga rantai suplai ini, Indonesia dan Australia dapat mencapai tujuan dari IA-CEPA untuk membentuk economic powerhouse.
Referensi
Busch, M. (2018). Economic Policy in the Australia-Indonesia Relationship: Unbound Potential, Everlasting Climax. Dalam T. Lindsey & D. McRae (eds.), Strangers Next Door?: Indonesia and Australia in the Asian Century (pp. 471-498). Hart Publishing.
Culas, R. (2022). Prospects for Australian Wheat Exports Amid the Ukraine-Russia Conflict. Australian Institute of International Affairs. https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/prospects-australian-wheat-exports-amid-ukraine-russia-conflict/
DFAT. (2021). A Blueprint for Trade and Investment with Indonesia. The Commonwealth of Australia. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/blueprint-trade-investment-indonesia.pdf
DFAT. (tidak tertanggal). Indonesia Economic and Trade Data. Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/indo-cef.pdf
Global Instant noodle export import trade data, buyers, & suppliers. (2022, 2 September). Volza. https://www.volza.com/p/instant-noodles/
Karunaratne, N. D. (1982). Prospects for Stronger Australia-Indonesia Economic Ties. Asian Survey, 22(3), pp. 292-303. https://www.jstor.org/stable/2644031
Kurniawan, D. (2021). Indonesian Instant Noodle Exports Enter Non-Traditional Markets, IEB Institute: The Trend Is Increasing. VOI. https://voi.id/en/economy/112182/indonesian-instant-noodle-exports-enter-non-traditional-markets-ieb-institute-the-trend-is-increasing
Kusumohamidjojo, B. (1986). The Indonesia‐Australia relationship: Problems between unfamiliar neighbours. Australian Outlook, 40(3), pp. 143-147. DOI: 10.1080/10357718608444917
Patunru, A., Surianta, A., & Audrine, P. (2021). Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Building the Powerhouse. Center for Indonesian Policy Studies. https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d_469623da8d5444c09d68dfca96ec42ae.pdf
Wheat. (tidak tertanggal). Australian Export Grains Innovative Centre. https://www.aegic.org.au/australian-grains/wheat/
0 notes
Text
Emansipasi Ekologis dalam Pariwisata di Bali
Politik Perubahan Lingkungan Hidup Global | 14 Juni 2022
Sejarah ditulis oleh pemenang, begitu pula dengan pengetahuan. Pengetahuan mengenai sesuatu, dalam hal ini problematika lingkungan, tidak pernah hadir dengan begitu saja. Segala macam pengetahuan bisa hadir setelah melalui serangkaian proses produksi pengetahuan dengan cara yang beragam. Keberadaan dari suatu pengetahuan di tengah masyarakat pun memiliki sifat yang kontekstual. Mengenai apa suatu pengetahuan lingkungan akan diproduksi, bergantung pada kondisi dan tatanan sosial di mana pengetahuan tersebut lahir. Pernyataan ini didasarkan pada pernyataan dari Timothy Luke (1995) bahwa banyak istilah terkait dengan lingkungan memiliki ketidakjelasan makna sampai kita menempatkannya dalam lensa genealogi tertentu. Sebagai contoh, pengetahuan mengenai kontaminasi limbah medis terhadap tanah dan air (Manzoor & Sharma, 2019) lahir dalam suatu tatanan sosial yang secara geografis berlokasi dekat dengan fasilitas kesehatan. Sebelum kita menempatkan kontaminasi limbah medis dalam sebuah payung konteks yaitu persoalan lingkungan, apa yang kita pahami hanyalah sebagai fenomena pembuangan limbah medis sebagai proses alami dari praktik operasional rumah sakit. Kontaminasi tersebut, lebih lanjut, berkembang menjadi pengetahuan mengenai kerusakan lingkungan ketika masyarakat yang memanfaatkan tanah dan air tercemar tersebut untuk kehidupannya. Dalam kata lain, suatu fenomena dapat dipahami sebagai sebuah problematika lingkungan karena adanya subjek politik tertentu yang terdampak fenomena tersebut.
Lantas, bagaimana bisa suatu fenomena atau informasi dipahami sebagai bagian dari problematika atau fenomena yang lebih besar? Dalam ilustrasi di atas, bagaimana fenomena kontaminasi limbah medis bisa dibenarkan sebagai bagian dari persoalan lingkungan? Luke (1995) mendefinisikan kata environment atau lingkungan sebagai sebuah keadaan yang lahir dari tindakan to environ yang berarti mencakup, mengelilingi, menyampul, atau melingkupi. Dari pemaknaan tersebut, dapat dilihat bahwa kita memahami suatu fenomena sebagai persoalan lingkungan ketika fenomena tersebut berkaitan erat dengan kehidupan kita dan dinamika satu sama lain saling mempengaruhi. Meski demikian, penting untuk diketahui bahwa pemaknaan mengenai isu lingkungan bersifat tetap. Terdapat perubahan dari masa ke masa mengenai klasifikasi dan titik utama permasalahan. Mol (2001) membagi kronologi perubahan tersebut menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama gerakan lingkungan (sejak 1900) mengupayakan perlindungan sumber daya alam dan spesies dengan cara konservasi alam di negara-negara yang mengalami perkembangan industrialisasi. Gelombang kedua (sejak 1970) mengupayakan minimalisir pertambahan beban lingkungan dan kemunduran kualitas lingkungan dengan reogranisasi tatanan sosial yang bersifat destruktif terhadap lingkungan di negara-negara industri. Terakhir, gerakan ketiga (sejak 1980) mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan pada tingkat global dengan reformasi institusi-institusi yang relevan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perubahan diskursus, narasi, dan pengetahuan yang berkuasa mengenai apa yang disebut sebagai persoalan lingkungan dan cara-cara mengatasinya. Lebih spesifik lagi, perubahan diskursus tersebut juga tercermin dari cara pandang spasial mengenai lingkungan hidup, yakni skala persoalan dan skala penyelesaiannya.
Pada dasarnya, terdapat lebih dari satu pemahaman dan interpretasi mengenai fenomena lingkungan tertentu. Sebagai konsekuensinya, segala analisis materil mengenai fenomena lingkungan dalam satu periode waktu yang sama merupakan diskursus alih-alih kebenaran mutlak (Escobar, 1996). Artinya, kebenaran mengenai fenomena lingkungan tertentu bersifat jamak namun bukan berarti kebenaran yang satu menegasi kebenaran yang lain. Akan tetapi, pada akhirnya hanya terdapat satu narasi yang secara kolektif diyakini sebagai kebenaran. Narasi tersebut merupakan pengetahuan yang berkuasa dan posisinya ‘yang berkuasa’ diperoleh karena konteks politik di mana narasi tersebut berada.
Konsep yang dapat menjelaskan hegemoni suatu pengetahuan mengenai lingkungan adalah konsep environmentality, yang merupakan aplikasi dan penerapan dari konsep governmentality milik Foucault dalam narasi mengenai lingkungan. Secara sederhana, konsep environmentality menyatakan bahwa dinamika politik lingkungan terjadi melalui pengaruh kekuasaan dan pengetahuan. Luke (1995) menyebutkan bahwa the environment merupakan basis bagi pembentukan pengetahuan dan siasat pengendalian oleh penguasa. Meski demikian, tidak semua diskursus yang diterapkan oleh penguasa mempertimbangkan lingkungan. Lingkungan pun menjadi sebuah diskursus yang termarjinalkan dalam kontestasi pengetahuan. Dalam kata lain, pengetahuan yang berkuasa tidak melihat problematika lingkungan sebagai suatu kebenaran. Pembangunan emansipasi ekologis pun dilakukan untuk memberikan suara dan tempat bagi problematika lingkungan dalam tatanan sosial politik sebagai pengetahuan yang berkuasa, sebagai diskursus kebenaran oleh pemegang kekuasaan.
Salah satu kasus yang dapat menggambarkan upaya emansipasi ekologis dalam kontestasi pengetahuan mengenai lingkungan adalah politik lingkungan dalam pariwisata di Bali. Pada akhir 1980-an, Bali menjadi objek kontestasi pengetahuan dan diskursus lingkungan. Kebijakan investasi yang disahkan oleh pemerintah pusat pada 1987 menyebabkan masifnya investasi untuk pembangunan pariwisata dan infrastrukturnya di Bali (Warren, 1998). Master Plan Pariwisata 1971 yang dicanangkan pemerintah juga menjadi perwujudan upaya pemerintah dalam membangun hegemoni pengetahuan mengenai utilisasi lingkungan untuk kegiatan ekonomi, yaitu pariwisata. Master Plan tersebut secara legal mengidentifikasi satu per empat daratan di Bali dan satu dari lima desa di Bali sebagai zona wisata (Warren, 1998). Dalam kasus ini, kontestasi pengetahuan mengenai lingkungan ‘dimenangkan’ oleh pemerintah yang didukung oleh relasi kuasanya dengan penduduk di Bali sebagai subjek politik lingkungan. Ekologi pun tidak memperoleh suaranya—tidak teremansipasi—dalam tatanan sosial ini.
Sebagaimana tatanan sosial merupakan arena kontestasi diskursus, masyarakat Bali pun memiliki diskursusnya sendiri berupa nilai-nilai yang mereka yakini merupakan sebuah kebenaran. Bagi masyarakat Bali, tanah dan air memegang signifikansi kultural dan kepentingan praktis (Warren, 1998) sehingga mereka menentang pengetahuan yang diberlakukan pemilik kekuasaan berupa eksploitasi komersial lingkungan untuk pariwisata. Terlebih lagi, industri pariwisata yang dibangun tersebut secara nyata menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Beberapa di antaranya yaitu erosi pantai, peningkatan sampah plastik, pencemaran selokan dan udara, salinasi air tanah, konversi lahan produktif, dan pengalihan guna lahan pertanian untuk hotel dan lapangan golf (Warren, 1998). Terlebih lagi, pemeliharaan lapangan golf membutuhkan pemberian zat kimia sebanyak 7-10 kali lebih banyak dari yang digunakan dalam pertanian dan penggunaan air sebanyak hingga 40.000 liter per hari padahal kurangnya ketersediaan air pun sudah terjadi di pertanian hilir Bali (Warren, 1998). Bagi masyarakat Bali, pengetahuan yang berkuasa saat itu terbukti bertentangan dengan kebenaran yang mereka yakini sehingga menjadi penting bagi mereka untuk melakukan emansipasi ekologis. Menjadi penting bagi mereka untuk menyuarakan lingkungan dalam kontestasi diskursus dan dalam tatanan sosial. Keluhan-keluhan mereka diartikulasikan melalui berbagai jalur, salah satunya tertuang dalam surat kabar lokal Bali Post (Warren, 1998).
Kontestasi pengetahuan antara pemerintah dan masyarakat Bali mengenai lingkungan sejatinya merupakan bentuk dari asumsi bahwa realitas sosial dapat diatur. Escobar (1996) menyebutkan bahwa konsep perencanaan dan manajemen merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa perubahan sosial dapat direkayasa, diarahkan, dan diproduksi sesuai keinginan. Dengan merujuk pada tulisan Escobar, praktik perencanaan pembangunan pariwisata di Bali merupakan tindakan yang dianggap sebagai tindakan rasional dan objektif—bagi para pengembang (Escobar, 1996). Jika kita melihat melalui konteks yang lebih luas, fenomena pembangunan pariwisata di Bali merupakan bagian dari praktik ekonomi kapitalis, di mana sumber daya alam dan wilayah diutilisasi sedemikian rupa melalui perencanaan pembangunan untuk menghasilkan keuntungan. Kasus di Bali ini pun sesuai dengan penjelasan Escobar mengenai implikasi dari ekonomi kapitalis terhadap lokasi yang terisolasi. Menurutnya, dalam ekonomi kapitalis dunia, komunitas yang paling terisolasi di Negara Dunia Ketiga menjadi tercerabut dari konteks lokal mereka dan didefinisikan kembali sebagai sumber daya untuk dirancang dan diatur (Escobar, 1996). Pembangunan pariwisata di Bali telah menyebabkan kerusakan lingkungan—yang tidak hanya berfungsi dalam kehidupan praktis masyarakat—yang memegang peran dalam identitas lokal dan kultural masyarakat Bali sehingga membuat mereka tercerabut dari kelokalannya.
Menurut pendekatan pasca struktural, perkembangan pengetahuan mengenai problematika lingkungan bersifat kontekstual, yakni ditentukan oleh konteks sosial politik di mana pengetahuan tersebut berada. Suatu pengetahuan mengenai problematika lingkungan pun akan hadir jika pengetahuan tersebut memiliki signifikansi bagi subjek politik tertentu. Artinya, problematika lingkungan akan menjadi problematika hanya bagi aktor-aktor tertentu yang—tentunya secara subjektif—terdampak oleh problematika tersebut. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa, dalam suatu tatanan sosial, problematika lingkungan merupakan kontestasi diskursus yang hegemoninya dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain.
Konsekuensi dari kontestasi tersebut adalah bahwa terdapat lebih dari satu pengetahuan mengenai lingkungan yang diyakini sebagai kebenaran—yang kebenaran satunya tidak serta merta menegasi kebenaran lain. Hanya diskursus yang diyakini oleh penguasa sebagai kebenaran-lah yang dapat memegang posisi sebagai pengetahuan yang berkuasa. Seringkali, pengetahuan tersebut memarjinalkan kebenaran mengenai lingkungan sehingga diperlukan emansipasi ekologis untuk memberikan suara bagi subjek-subjek lingkungan dalam tatanan sosial politik. Upaya masyarakat Bali untuk melawan pariwisata yang merusak lingkungan merupakan bentuk artikulasi subjek politik dalam upaya emansipasi ekologis. Tidak hanya karena lingkungan memberikan mereka manfaat praktis, lingkungan juga merupakan bagian dari identitas lokal dan kultural mereka—sehingga kerusakannya menyebabkan ketercerabutan mereka dari kelokalan kultural.
Referensi
Escobar, A. (1996). Construction nature: Elements for a post-structuralist political ecology. Futures, 28(4), pp. 325-343.
Luke, T. W. (1995). On Environmentality: Geo-Power and Eco-Knowledge in the Discourses of Contemporary Environmentalism. Cultural Critique, 31, pp. 57-81. https://doi.org/10.2307/1354445
Manzoor, J. & Sharma, M. (2019). Impact of Biomedical Waste on Environment and Human Health. Environmental Claims Journal, 31(4), pp. 311-334. DOI: 10.1080/10406026.2019.1619265
Mol, A. P. J. (2001). Globalization and Environmental Reform: The Ecological Modernization of the Global Economy. The MIT Press.
Warren, C. (1998). Tanah Lot: the cultural and environmental politics of resort development in Bali. Dalam P. Hirsch & C. Warren (eds.), The Politics of Environment in Southeast Asia (pp. 229-261). Routledge.
0 notes
Text
Analisis International Force East Timor sebagai Militerisasi Politik Dunia oleh Australia
Militer dan Politik | 18 Juni 2022
Latar Belakang
International Force East Timor atau INTERFET merupakan operasi militer yang dikirim oleh Australia sebagai misi perdamaian di Timor Timur pada September 1999. Misi tersebut tergolong sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Australia dalam beberapa dekade terakhir (White, 2008). Operasi tersebut diotorisasi oleh UNSC melalui Resolusi 1264, bertugas untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur, melindungi United Nations Mission in East Timor (UNAMET), dan memfasilitasi operasi bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, UNAMET telah melakukan referendum bagi masyarakat Timor Timur pada 30 Agustus 1999 untuk menentukan status Timor Timur yang saat itu berstatus sebagai provinsi di Indonesia (Smith, 1999). Hasil referendum yang menyatakan bahwa 78% pemilih menginginkan kemerekaan Timor Timur dari Indonesia memantik serangan bersenjata, kekerasan, dan intimidasi oleh pendukung status otonomi di bawah Indonesia (Smith, 1999). Atas dasar terjadinya gejolak inilah, Australia membentuk dan mengirimkan INTERFET sebagai operasi perdamaian multinasional yang terdiri atas beberapa negara lainnya.
Intervensi militer melampaui batas wilayah negara umumnya diinisiasi dan dipimpin oleh negara-negara adidaya atau oleh organisasi internasional. INTERFET menjadi menarik untuk dianalisis sebab menunjukkan representasi middle power dalam militerisasi politik dunia. Lebih lanjut lagi, kasus ini menunjukkan bahwa logika empire dalam politik dunia tidak hanya dapat dibangun oleh negara adidaya melainkan dapat pula dibentuk oleh negara middle power.
Argumentasi utama
Tulisan ini menganalisis motif yang mendorong Australia untuk membentuk dan mengirimkan INTERFET. Secara garis besar, argumen utama yang disampaikan dalam tulisan ini adalah bahwa INTERFET merupakan perwujudan upaya Australia dalam menciptakan keamanan di Timor Timur sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya.
Analisis
INTERFET sebagai fitur tatanan keamanan dunia liberal yang diyakini Australia
Dalam menjalankan politik luar negerinya, Australia memiliki norma internasionalisme liberal. Menurut Wilkins & Bromfield (2019), internasionalisme liberal didefinisikan sebagai aktivisme politik luar negeri Australia yang secara aktif mempromosikan nilai-nilai liberal. Pengiriman operasi militer INTERFET merupakan perwujudan dari norma ini. Secara tersirat, Australia memiliki ketidakpercayaan terhadap TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai pasukan keamanan di Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Leste. Berbagai kekerasan bersenjata dan represi oleh TNI terhadap masyarakat Timor Timur menunjukkan adanya persoalan dalam relasi sipil-militer di Indonesia. Ketidakpercayaan ini disebabkan oleh adanya rekam jejak TNI dalam mengintervensi berbagai pemilu di Indonesia dan tindakan TNI yang kerap mendukung milisi anti kemerdekaan Timor Timur (Fernandes, 2008; Henry, 2013; White, 2008).
Tidak hanya sebatas persepsi, penilaian Australia terhadap TNI pun dibuktikan dengan terjadinya berbagai kekerasan bersenjata di Timor Timur. Terdapat peristiwa pembantaian Santa Cruz pada 1991 dengan represi TNI terdokumentasi dalam rekaman video jurnalis (Fernandes, 2008). Temuan intelijen pertahanan Australia yang bocor juga menyatakan bahwa TNI menembakan gas air mata dan tidak mengintervensi ketika kelompok pro-kemerdekaan diserang dalam pembantaian Liquica (Fernandes, 2008). Persepsi ketidakpercayaan Australia terhadap TNI semakin dibuktikan oleh serangan bersenjata pada 2 & 3 September 1999 terhadap orang-orang Timor Timur yang bekerja dengan UNAMET serta serangan terhadap UNAMET pasca diumumkannya hasil referendum pada 4 September 1999 (Henry, 2013). Dua serangan terakhir inilah yang menjadi pemicu spesifik pengiriman INTERFET oleh Australia. Kondisi ini dibingkai secara politis oleh Australia sebagai penyimpangan dari visi dunia liberal yang dimilikinya. Oleh karena itu, Australia merasa bahwa menjaga keamanan di Timor Timur secara langsung merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk mewujudkan tatanan keamanan dunia liberal.
Keterikatan Australia dan Asia dalam kompleksitas geopolitik
Sebagai negara Barat yang ‘terkurung’ di antara negara-negara Asia dan Oseania, Australlia harus memiliki cara khusus agar bisa menjaga kesintasan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan dengan menerapkan logika keamanan regionalisme (McDougall, 2011). Dalam kaitannya dengan kasus Timor Timur, Australia memandang bahwa pemeliharaan tatanan dan stabilitas kawasan Asia merupakan pendekatan yang harus diambil Australia sebagai negara Barat yang bertetangga dengan Asia (Lyon, 2011) agar kepentingan Barat tidak terancam. Untuk menunjukkan komitmen Australia terhadap Asia, Perdana Menteri Paul Keating pun menerapkan norma kebijakan Asian engagement yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Asia adalah rumah alami Australia (Wilkins & Bromfield, 2019). Pernyataan Paul Keating menjadi penting sebab visi Australia terhadap intensinya untuk aktif berinteraksi dan terlibat dengan Asia dapat dikatakan secara resmi adalah bagian dari politik luar negerinya.
Gejolak di Timor Timur sejak awal integrasinya ke Indonesia pun sudah memperoleh perhatian khusus Australia, terutama dengan beredarnya bukti peristiwa pembantaian Santa Cruz. Instabilitas berkepanjangan di Timor Timur, khususnya pasca referendum, dibingkai secara politik oleh Australia sebagai ancaman bagi keamanan dan kepentingan nasionalnya. Nyatanya, Timor Timur secara spesifik memang menjadi salah satu titik kunci bagi keamanan dan kepentingan nasional Australia. Menteri Pertahanan John Moore dan Perdana Menteri John Howard mengungkapkan, dalam kesempatan yang berbeda, bahwa stabilitas di Timor Timur merupakan hal esensial bagi kepentingan nasional dan strategis Australia (Majumdar, 2001; McDougall, 2011). Meskipun Australia berusaha untuk menjaga hubungan bilateral baik dengan Indonesia dengan menghargai apapun kebijakan Indonesia mengenai Timor Timur (White, 2008), hasil referendum menjadi basis bagi Australia untuk mengintervensi represi kemerdekaan Timor Timur.
Kesimpulan
Kasus INTERFET dan Timor Timur memberi kita pandangan bahwa militerisasi dalam politik dunia masih berlangsung meskipun masa kolonialisme dan Perang Dunia telah berakhir. Selama negara merasa bahwa militerisasi diperlukan untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasionalnya, militerisasi akan tetap hadir sebagai bagian dari fitur politik dunia. Militerisasi politik dunia juga tidak selalu terwujud dalam bentuk kerja sama pertahanan dan pembangunan basis militer. Lebih menarik lagi, kasus ini menunjukkan bahwa militerisasi politik dunia dapat pula dilakukan oleh negara middle power. Australia dapat dikatakan cukup berhasil dalam melakukan misi perdamaiannya yang ditunjukkan dengan terwujudnya transisi dan kemerdekaan Timor Timur. Tidak hanya itu, kasus ini juga menjadi salah satu contoh keberhasilan Australia dalam mengeksekusi dan mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui politik luar negerinya. Internasionalisme liberal sebagai politik luar negeri Australia tergolong berhasil dalam menjadi cara Australia untuk mewujudkan tatanan dunia liberal yang divisikannya di Timor Timur. Di saat yang bersamaan, Australia memandang bahwa militerisasi masih menjadi opsi yang terbaik untuk menyikapi kompleksitas geopolitik melalui keamanan regionalisme.
Referensi
Fernandes, C. (2008). The Road to INTERFET: Bringing the Politics Back In. Security Challenges, 4(3), pp. 83-98. https://www.jstor.org/stable/26459192
Henry, I. (2013). Playing Second Fiddle on the Road to INTERFET: Australia’s East Timor Policy Throughout 1999. Security Challenges, 9(1), 87–112. http://www.jstor.org/stable/26461970
Lyon, R. (2011). AUSTRALIA AND ASIA. In Forks in the river: Australia’s strategic options in a transformational Asia (pp. 34–37). Australian Strategic Policy Institute. http://www.jstor.org/stable/resrep04187.11
Majumdar, M. (2001). AUSTRALIAN POLICY IN EAST TIMOR. India Quarterly, 57(4), pp. 161-172. http://www.jstor.com/stable/45073280
McDougall, D. (2011). Australia and Asia-Pacific Security Regionalism: From Hawke and Keating to Howard. Contemporary Southeast Asia, 23(1), pp. 81-100. https://www.jstor.org/stable/25798529
Smith, A. (1999). EAST TIMOR: opting for independence. New Zealand International Review, 24(6), pp. 6-9. https://www.jstor.org/stable/45234876
White, H. (2008). The Road to INTERFET: Reflections on Australian Strategic Decisions Concerning East Timor, December 1998-September 1999. Security Challenges, 4(1), pp. 69-87. https://www.jstor.org/stable/26458869
Wilkins T. S. & Bromfield, N. (2019). Foreign and defence policy. Dalam P. J. Chen et al. (eds.), Australian Politics Policy (pp. 580-602). Sydney University Press.
0 notes
Text
Dinamika Pembentukan Negara di Sudan Selatan: Penculikan Perempuan sebagai Implikasi Kekacauan Negara
State Formation di Afrika | 7 November 2021
Praktik mahar dalam pernikahan tidak asing lagi ditemukan dalam kehidupan manusia. Pemberian mahar umumnya dilakukan oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Bentuk mahar pun bermacam-macam, sesuai dengan tradisi, kesepakatan, atau kemampuan ekonomi. Praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Sudan Selatan nyatanya unik, sebab tradisi yang berkembang saat ini berada di atas fondasi kekerasan terhadap perempuan dan tidak jarang anak-anak. Lizzie Lacey dalam artikel jurnalnya berjudul Women for cows: An analysis of abduction of women in South Sudan yang terbit pada 2013 memaparkan masalah penculikan perempuan-perempuan sebagai senjata dalam konflik antar-etnis. Sebagian dari pemaparannya didasarkan atas wawancara langsung terhadap para perempuan penyintas aksi kekerasan yang kejam tersebut.
Lacey mengungkapkan bahwa sejak 2009—meskipun Sudan Selatan belum berdiri sebagai negara—ribuan perempuan menjadi korban penculikan di negara bagian Jonglei dalam berbagai serangan balasan dalam konflik antara etnis Lou Nuer dan Murle. Konflik yang dimaksud secara spesifik termanifestasi dalam bentuk perampokan ternak. Lacey mengklaim bahwa perampokan ternak merupakan tradisi yang sudah lama sering terjadi antaretnis. Meski demikian, tradisi tersebut semakin lama semakin meningkat, sengit, dan tajam akibat kurangnya infrastruktur sosial dan fisik serta alternatif ekonomi yang layak (pp. 91-2). Di Sudan Selatan pun perempuan dianggap senilai dengan hewan ternak dalam sebuah pernikahan. Lacey (p. 94) menerangkan bahwa hewan ternak yang diperoleh dari perampokan digunakan untuk membayar mahalnya ‘harga mempelai wanita.’ Di saat yang bersamaan, perempuan dihargai atas kemampuan fertilitas dan tenaga kerjanya sehingga marak terjadi penculikan perempuan karena manfaat yang dibawanya untuk keluarga penculik tanpa harus melalui praktik mahar (p. 94).
Sepintas, fenomena di atas tampak sebagai fenomena kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, sebagai fenomena kekerasan terhadap perempuan yang terisolasi. Nyatanya, fenomena tersebut menggambarkan fakta yang lebih luas mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Sudan Selatan. Lacey, dengan mengutip Stern, mengungkapkan bahwa praktik mahar merupakan fitur yang menonjol dalam kehidupan perekonomian masyarakat Sudan Selatan (p. 95). Artinya, praktik mahar tidak dapat dimaknai semata sebagai tradisi tetapi pada kenyataannya turut berperan dalam membentuk dinamika relasi dan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat Sudan Selatan. Di saat yang bersamaan pula, pengkultusan hewan ternak oleh masyarakat Sudan Selatan—termanifestasi dalam perampokan dan dalam praktik mahar—tidak terlepas dari fakta bahwa mereka hidup dalam model penggembalaan sehingga sangat bergantung pada hewan ternak (p. 94). Lacey (p. 94) lebih lanjut lagi, dengan mengutip IOM, bahwa Sudan Selatan merupakan salah satu negara dengan populasi penggembala terbesar di dunia dan banyak penduduk Sudan Selatan menganggap kepemilikan hewan ternak sebagai perwujudan akumulasi kekayaan.
Lebih lanjut lagi, dari tulisan Lacey, setidaknya terdapat 3 faktor intrinsik yang tercermin dan tertanam secara laten dalam kasus konflik dan kekerasan tersebut. Pertama, perpecahan etnis. Seperti yang telah disebutkan di awal, kasus penculikan perempuan dan perampokan ternak merupakan konflik dan kekerasan yang terjadi antaretnis. Etnis-etnis yang terlibat kerap terlibat dalam konflik ini di antaranya adalah Lou Nuer, Murle, dan Dinka di negara bagian Jonglei dengan memanfaatkan pertarungan politik untuk melakukan perampokan (Lacey, 2013, p. 92). Merujuk pada pemaparan Thomson (2016, p. 62), konflik antaretnis tersebut dapat dilihat dari perspektif primordialis yang memandang bahwa etnis merupakan bentuk identitas yang telah ada dan melekat pada individu atau kelompok sejak lama sebagai warisan dari masa pra-kolonial. Perspektif ini juga melihat bahwa kesetiaan sejarah dalam suatu identitas etnis telah terbawa pada perpolitikan hari ini (Thomson, 2016, p. 62).
Kedua, ketimpangan ekonomi. Masih merujuk pada ringkasan di awal, penculikan perempuan terjadi akibat sulitnya mengakumulasi kekayaan dalam bentuk kepemilikan hewan ternak. Di saat yang bersamaan, perempuan dalam masyarakat Sudan Selatan dipandang memiliki nilai berharga karena kemampuan fertilitas dan tenaga kerjanya. Sementara itu, untuk dapat menikahi seorang perempuan, masyarakat Sudan Selatan meyakini praktik mahar menggunakan hewan ternak. Kesulitan untuk memiliki hewan ternak—yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu keluarga—menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi. Dari sini menarik untuk dikaji lebih dalam penyebab ketimpangan ekonomi di Sudan Selatan mengingat negara ini termasuk negara dengan sumber daya alam yang cukup melimpah. Ellsberg et al. (2021, p. 3034) mengklaim bahwa jatuhnya ekonomi di Sudan Selatan disebabkan oleh konflik yang terjadi secara luas dan berkepanjangan sehingga menyebabkan kesengsaraan dan kelaparan bagi penduduk negara ini.
Ketiga, ketimpangan gender. Faktor ini sangat jelas tampak dalam kasus konflik dan kekerasan yang diteliti dan didiskusikan oleh Lacey. Penculikan perempuan sendiri telah menunjukkan kekerasan berbasis gender. Lacey (p. 97) kemudian mengutip Weber dengan menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan refleksi dari dominasi seksual laki-laki sebagai cara untuk memproyeksikan kekuasaan dan untuk memutuskan hubungan antara komunitas masyarakat dengan ranah feminin yaitu rumah tangga. Lacey juga mengungkapkan hasil wawancaranya dengan perempuan di Sudan Selatan bahwa “perampok memahami tidak ada yang lebih menyakitkan seorang laki-laki ketika anak perempuan, saudara perempuan, istri, atau ibunya diculik” (p. 99). Upaya tersebut menunjukkan adanya objektifikasi perempuan sebagai alat untuk memperoleh kekayaan dan mendukung kelangsungan hidup keluarga si penculik karena kemampuan fertilitas perempuan tersebut. Sistem hukum di Sudan Selatan pun masih minim perlindungan terhadap perempuan. Hak perempuan dalam sistem hukum Sudan Selatan tergolong sebagai ranah privat dan hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat (p. 96). Sayangnya, hukum adat yang ada masih meletakkan perempuan secara sub-ordinat di hadapan laki-laki (p. 96). Meski demikian, kita harus berhati-hati dalam mencoba membantu penyelesaian isu tersebut. Mohanty (1991) menekankan bahwa gagasan bahwa perempuan di negara Dunia Ketiga secara inheren teropresi oleh kultur dan tradisinya memiliki logika bahwa perempuan tidak memiliki agensi. Sebagai alternatifnya, upaya membantu perempuan negara Dunia Ketiga dalam struktur opresif harus memperhatikan dan menekankan politik kelokasian alih-alih memaksakan nilai eksternal yang dianggap berlaku universal (Mohanty, 1991).
Ketiga faktor yang telah disebutkan di atas sejatinya memiliki benang merah, yakni lahir akibat konflik bersenjata dan perang sipil berkepanjangan yang terjadi di Sudan Selatan. Konflik dan perang berkepanjangan menyebabkan kurang bahkan absennya perhatian terhadap kehidupan rakyat Sudan Selatan. Sudan Selatan lahir sebagai negara merdeka pada 2011 akibat perang sipil dengan negara tetangganya, Sudan, sejak tahun 1960-an. Akan tetapi, setelah berdiri sebagai negara merdeka pun, Sudan Selatan masih mengalami perang sipil bahkan hingga dua kali. Kekacauan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memakan waktu sangat lama menunjukkan belum kuatnya pembangunan kekuasaan pemerintah negara ini. Sebagai konsekuensinya, konflik dan kekerasan lain, yang justru terpinggirkan dari perhatian, pun terjadi. Konflik dan kekeraasan berupa penculikan perempuan untuk mahar merupakan salah satu refleksi dari kondisi tersebut.
Referensi
Ellsberg, M., Murphy, M., Blackwell, A., Macrae, M., Reddy, D., Hollowell, C., Hess, T., & Contreras-Urbina, M. (2021). “If You Are Born a Girl in This Crisis, You Are Born a Problem”: Patterns and Drivers of Violence Against Women and Girls in Conflict-Affected South Sudan. Violence Against Women, 27(15-16), 3030-3055. DOI: 10.1177/1077801221996463
Lacey, L. (2013). Women for cows: An analysis of abduction of women in South Sudan. Agenda: Empowering Women for Gender Equity, 27(4), 91-108. https://www.jstor.org/stable/43825103
Mohanty, C. T. (1991). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. In C. T. Mohanty, A. Russo, & L. Torres (Eds.), Third World Women and the Politics of Feminism (pp. 51-80). Indiana University Press.
Thomson, A. (2016). An introduction to African politics (3rd ed). Routledge.
0 notes
Text
Membongkar Diskursus Politik dalam Pembantaian Santa Cruz
Kekerasan dalam Politik Dunia | 21 Desember 2021
Latar Belakang
Pada 12 November 1991 terjadi insiden penembakan membabi buta oleh TNI terhadap warga Timor Timur di pemakaman Santa Cruz. Sebelum insiden, mereka yang ditembaki tengah berkumpul di pemakaman tersebut dalam aksi protes menuntut kemerdekaan. Tragisnya peristiwa tersebut yang terekam dalam video hasil rekaman jurnalis Australia menuai protes dari berbagai kalangan. Di sisi lain pun, tidak ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengusut persoalan tersebut dan justru malah menolak kecaman dari masyarakat internasional seperti dari presiden Amerika Serikat. Justifikasi penggunaan kekerasan oleh negara dalam kasus tersebut menarik untuk dibahas karena peristiwa tersebut bertentangan dengan norma demokrasi dan hak asasi manusia yang tengah berkembang secara global saat itu. Pun kecaman dari ‘sekutu-sekutu’ Indonesia saat itu tidak memberi signifikansi keadilan bagi warga Timor Timur. Tulisanini membahas diskursus seperti apa yang mendorong legitimasi kekerasan oleh militer Indonesia terhadap warga Timor Timur.
Pertanyaan Penelitian
Bagaimana pemerintah dan militer Indonesia saat itu memaknai dan memandang Timor Timur sehingga represi atas tuntutan kemerdekaan, salah satunya yang terwujud dalam pembantaian masal Santa Cruz, menjadi terjustifikasi? Bagaimana posisi mereka sebagai bagian dari Indonesia dimaknai oleh warga Timor Timur, khususnya para aktivis pro-kemerdekaan, sehingga menuntut kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia?
Pendekatan
Pembahasan dalam esai ini menggunakan pendekatan analisis diskursus kritis yang disampaikan oleh Fairclough (Jorgensen & Phillips, 2002), spesifiknya adalah konsep yang merujuk diskursus pada penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Diskursus diyakini membentuk dan dibentuk oleh struktur dan praktik sosial yang ada dalam kurun waktu yang spesifik. Diskursus dipandang sebagai bentuk dari praktik sosial yang memproduksi ulang dan mengubah pengetahuan, identitas, dan relasi sosial serta di saat yang bersamaan juga dibentuk oleh praktik sosial dan struktur sosial lainnya. Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan berfokus pada diskursus spesifik yang mendefinisikan kondisi sosial politik di Timor Timur dan di Indonesia serta bagaimana keduanya membentuk dan dibentuk.
Pembahasan
Pandangan pemerintah dan militer Indonesia saat itu terhadap Timor Timur berkaitan erat dengan keputusan rezim baru di Portugis pada 1974 untuk melepaskan kekuasaan atas wilayah-wilayahnya di luar negeri, termasuk Timor Timur. Berkembang setidaknya dua kondisi yang membawa pada antagonisasi Timor Timur oleh pemerintah Indonesia. Pertama, salah satu dari tiga partai politik dominan di Timor Timur beraliran politik kiri, yaitu Fretilin (Philpott, 2006). Pasalnya, Fretilin menginginkan kemerdekaan yang kemudian dideklarasikan sebagai Republik Demokratik Timor Leste (Lawless, 1976). Antagonisasi berbasis komunisme terhadap Timor Timur tampak ketika Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Indonesia untuk Australia pada Februari 1975 dan Partai Golkar—sebagai partai penguasa Indonesia—pada Maret 1975 menyatakan bahwa Indonesia mengkhawatirkan dan tidak akan mentoleransi kehadiran komunisme di Timor Timur (Lawless, 1976). Faktor ini dapat dibaca dari siapa rezim yang berkuasa di Indonesia saat itu, yaitu pemerintah Soeharto yang sangat memusuhi komunisme, dan dari konteks global berupa Perang Dingin. Kedua, Philpott (2006) menyatakan bahwa kemunculan negara baru yang berbatasan langsung dengan Indonesia dapat memicu kelompok-kelompok lain di Indonesia untuk memisahkan diri. Kuatnya narasi identitas ke-Indonesia-an yang dipegang rezim Orde Baru membuat disintegrasi menjadi sangat dihindari. Terlebih lagi, terdapat pembenaran invasi Indonesia atas dasar persamaan klan seperti yang disampaikan oleh Ali Murtopo (Lawless, 1976).
Meskipun masih dapat diperdebatkan, kedua faktor di atas setidaknya menjadi diskursus yang mendefinisikan struktur dan praktik sosial sehingga membuat pemerintah dan militer Indonesia memandang Timor Timur sebagai negara merdeka adalah musuh dengan parameter nasionalisme—yang anti terhadap komunis—dan integrasi bangsa. Kehadiran negara baru yang berbatasan langsung dengan kemungkinan di bawah kuasa partai berideologi kiri menjadi definisi musuh terhadap inti dari berjalannya kekuasaan rezim Orde Baru. Penggunaan kekerasan pun lantas menjadi terjustifikasi demi menjaga nasionalisme dan integrasi bangsa—yang dimulai saat invasi Indonesia pada 7 Desember 1975 (Lawless, 1976).
Di sisi lain, integrasi paksa ke Indonesia dimaknai oleh penduduk Timor Timur sebagai bentuk penindasan yang harus dilawan. Pasalnya, penggunaan kekerasan oleh TNI terus berlangsung terus berlangsung setelah peresmian integrasi pada 15 Desember 1975, untuk merepresi resistensi tuntutan kemerdekaan terutama yang dilakukan Fretilin, Falantil, CRRN, dan CNRM (Lawless, 1976; Philpott, 2016). Pembenaran atas makna penindasan diperkuat dengan sifat rezim Orde Baru yang diktator dan menutup Timor Timur dari dunia. Penindasan menjadi diskursus yang mendefinisikan posisi penduduk Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, momen ‘dibukanya’ Timor Timur secara parsial bagi pihak internasional oleh Seoharto pada 1989 menjadi kesempatan bagi kelompok-kelompok resistensi untuk memperoleh dukungan internasional melalui kunjungan pers dan kelompok HAM (Philpott, 2006). Ironisnya, represi dan logika yang diterapkan Orde Baru terhadap Timor Timur tidak berubah sedikit pun.
Revolusi-revolusi di Eropa Tengah dan Timur pada 1989 mengindikasikan akhir dari kekuasaan komunisme secara global (Porter, 2016). Komunisme tidak lagi dipandang sebagai musuh oleh negara-negara liberal seperti Amerika Serikat namun kondisi ini tidak terjadi pada lanskap struktur politik di Indonesia. Rezim Orde Baru ‘terlepas’ dari norma pasca Perang Dingin yang tidak lagi menjustifikasi kekerasan oleh negara untuk melawan komunisme (Philpott, 2016). Dengan demikian, tidak mengherankan jika peristiwa Santa Cruz 1991 sebagai manifestasi kekerasan negara dapat terjadi dan berbagai sangkalan dari kritik internasional pun muncul (Philpott, 2016). Lebih spesifik lagi, peristiwa Santa Cruz merupakan salah satu upaya rezim Orde Baru untuk mempertahankan hegemoninya di tengah banyaknya resistensi seperti peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 dan peristiwa Tanjung Priok 1984. Terjadinya peristiwa Santa Cruz menunjukkan bahwa kekuatan komunisme dan ancaman disintegrasi bangsa masih mendefinisikan struktur politik Indonesia saat itu—dengan terdapatnya kedua elemen tersebut dalam kemerdekaan Timor Timur. Dengan demikian, diskursus yang mendefinisikan justifikasi kekerasan negara dalam peristiwa Santa Cruz kurang lebih masih sama dengan diskursus yang menjustifikasi invasi dan integrasi paksa Timor Timur ke Indonesia.
Kesimpulan
Pendefinisian kemerdekaan Timor Timur sebagai musuh oleh Indonesia merupakan hasil dari produksi pengetahuan, identitas, dan relasi sosial yang disebabkan oleh kekhawatiran terhadap komunisme dan ancaman disintegrasi bangsa. Di saat yang bersamaan, kedua faktor tersebut merupakan diskursus yang dibentuk oleh krisis rezim Orde Baru akibat berbagai resistensi yang melanda. Atas nama nasionalisme dan integrasi bangsa, penggunaan kekerasan dalam peristiwa Santa Cruz menjadi terjustifikasi sebagai instrumen politik rezim Orde Baru untuk membentuk dan membentuk ulang konfigurasi politik Indonesia dan Timor Timur. Konteks domestik berupa resistensi-lah yang membuat berakhirnya Perang Dingin tidak mempengaruhi lanskap politik di Indonesia. Di sisi lain, pengalaman integrasi paksa penduduk Timor Timur menjadi diskursus yang memaknai posisi mereka sebagai pihak yang tertindas sehingga menuntut kemerdekaan. Kontak dengan pihak internasional merupakan kesempatan bagi mereka untuk memperkuat tuntutan kemerdekaan. Pertemuan kepentingan politik berbeda antara rezim Orde Baru dan penduduk Timor Timur menjadi inti dari terjadinya pembantaian massal Santa Cruz.
Referensi
Jorgensen, M. & Phillips, L. J. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. SAGE Publications.
Lawless, R. (1976). The Indonesian Takeover of East Timor. Asian Survey, 16(10). 948-964. https://www.jstor.org/stable/2643535
Philpott, S. (2006). East Timor's Double Life: Smells like Westphalian Spirit. Third World Quarterly, 27(1). 135-159. https://www.jstor.org/stable/4017664
Porter, A. L. (2016). The Post–Cold War Years, 1989–99. Windows of Opportunity: East Timor and Australian Strategic Decision Making (1975-1999). Air University Press. http://www.jstor.com/stable/resrep13828.10
0 notes
Text
Konsekuensi Kemanusiaan dari Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya
Hukum Humaniter Internasional | 11 Desember 2021
Pada Februari 2011, pecah perang sipil di Libya sebagai kelanjutan dari protes terhadap pemimpin Libya saat itu, Muammar Qaddafi, yang represif dan korup. Tanggapan dari Qaddafi terhadap protes yang tidak baik membuat protes berujung pada konflik bersenjata dan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran (Libya profile - Timeline, 2021). DK PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 1973 pada Maret 2011 dengan mandat untuk melindungi penduduk sipil di Libya setelah Resolusi 1970 yang dikeluarkan pada Februari dinilai tidak memberi dampak apapun (Terry, 2015). Kekuatan militer yang mulanya terdiri atas Prancis, Inggris, dan AS bertambah hingga terdiri atas 14 negara anggota NATO yang membuat NATO memegang kendali atas Libya per 31 Maret 2011 (Terry, 2015). Intervensi ini kemudian dilabeli oleh beberapa ahli sebagai keberhasilan implementasi praktik Responsibility to Protect atau R2P yang bertujuan melindungi kemanusiaan (Kuperman, 2013).
Perintah dari Resolusi 1973 secara formal memang sejalan dengan hukum humaniter internasional. Akan tetapi, terdapat beberapa kritik terhadap intervensi NATO yang salah satunya menyebutkan bahwa NATO menggunakan banyak serangan udara dan pengeboman masif sehingga menimbulkan kematian warga sipil (Terry, 2015). Esai ini membahas kondisi Libya saat intervensi dan dampaknya dari aspek kemanusiaan. Problematika ini menarik untuk dibahas karena terdapat pelabelan intervensi ini sebagai keberhasilan R2P yang justru bertentangan dengan realitas yang terjadi. Untuk mendukung analisis, esai ini menggunakan dua landasan konseptual. Yang pertama adalah konsep mengenai R2P. Dilansir dari halaman situs PBB, R2P merupakan norma bersama untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan yang disepakati dalam KTT Dunia 2005 (Šimonović, t.t.). Norma ini memiliki tiga pilar tanggung jawab yaitu bagi negara untuk melindungi populasinya, bagi komunitas internasional untuk membantu negara dalam melindungi populasinya, dan bagi komunitas internasional untuk melindungi ketika negara gagal melindungi populasinya (Šimonović, t.t.). Yang kedua adalah prinsip hukum humaniter internasional, spesifiknya adalah pembedaan dan kebutuhan militer. Crowe & Weston-Scheuber (2013) menjelaskan bahwa prinsip pembedaan adalah prinsip di mana kombatan harus membedakan antara target militer dan target sipil. Sementara itu, kebutuhan militer dijelaskan sebagai prinsip di mana kombatan hanya diizinkan menggunakan kekuatan yang derajatnya cukup untuk menyasar target militer dan dengan kerugian yang sangat minimum (Crowe & Weston-Scheuber, 2013).
Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh NATO
Bagian ini akan membahas intervensi NATO di Libya melalui kacamata hukum humaniter internasional. Terdapat dua alasan mengapa intervensi tersebut relevan untuk dianalisis melalui hukum humaniter internasional. Pertama, intervensi yang dilakukan NATO menggunakan kekuatan militer sehingga dapat dikatakan bahwa NATO termasuk dalam pihak yang terlibat dalam pertempuran konflik bersenjata. Hal ini sesuai dengan cakupan hukum humaniter internasional yang berlaku dalam suatu konflik bersenjata. Kedua, intervensi NATO memiliki justifikasi kemanusiaan. Di saat yang bersamaan, hukum humaniter internasional pun bertujuan untuk menjaga kemanusiaan dalam konflik bersenjata sehingga hasil intervensi NATO perlu dilihat dari hukum ini.
Dalam intervensinya, cara berperang yang dilakukan NATO di antaranya adalah serangan udara dan pengeboman udara. Dengan melihat pada korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan dari dua cara tersebut, dapat dikatakan bahwa NATO melanggar prinsip pembedaan. Menurut laporan dari Human Rights Watch (2012), terdapat 72 korban jiwa dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dari penduduk sipil Libya akibat serangan udara NATO. Aiwars pun menyebutkan bahwa kenyataan yang ada bisa jadi lebih tinggi dari angka tersebut dan menyebutkan bahwa serangan NATO menyebabkan setidaknya 223 hingga 403 kematian dari penduduk sipil (Dyke, 2021). Mungkin argumentasi penyangkalan akan mengatakan bahwa bisa saja korban-korban tersebut merupakan penduduk yang kebetulan berada di dekat sasaran militer NATO. Akan tetapi, investigasi Human Rights Watch dan reportase Dyke (2021) menyebutkan bahwa setidaknya delapan serangan udara NATO justru menyasar lokasi-lokasi tanpa kehadiran militer yang dihuni penduduk sipil. Attia al-Juwaili, mengungkapkan bahwa keluarganya yang saat itu sedang mengungsi di Desa Majer untuk menyelamatkan diri dari zona konflik justru menjadi korban dari serangan NATO termasuk tewasnya anak perempuan beliau (Dyke, 2021). NATO mengklaim bahwa lokasi tersebut merupakan titik komando dan kendali pasukan Qaddafi namun klaim tersebut disangkal oleh penduduk setempat (Dyke, 2021). Tidak hanya tempat tinggal, serangan NATO juga menyasar objek non-militer lainnya di Libya. Sebuah stasiun televisi dan tiga penghubung televisi serta pabrik pipa Brega yang menyediakan pipa untuk persediaan air dari sungai menjadi sasaran pengeboman yang dilakukan NATO (Terry, 2015). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa NATO melanggar prinsip pembedaan yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I (Crowe & Weston-Scheuber, 2013).
Di saat yang bersamaan, pelanggaran prinsip pembedaan dalam kasus ini berkaitan dengan pelanggaran prinsip kebutuhan militer. Merujuk pada amanat dari Resolusi 1973 dan R2P, NATO diberikan izin untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi penduduk sipil. Namun kenyataannya, serangan militer NATO yang seharusnya hanya menyasar sesama kombatan perang justru turut menyasar warga sipil. Artinya, pelanggaran terjadi karena NATO telah melakukan serangan yang berlebihan melebihi tujuan untuk mencapai tujuan militer dari kehadirannya di Libya yaitu untuk melindungi penduduk sipil. Terry (2015) bahkan menyebutkan bahwa tidak ditemukan bukti-bukti yang mengindikasikan upaya NATO untuk melindungi penduduk sipil yang mendukung Qaddafi. Jatuhnya korban jiwa dari penduduk sipil juga menujukkan pelanggaran terhadap prinsip kebutuhan militer yang tercantum dalam Pasal 54 Protokol Tambahan I (Crowe & Weston-Scheuber, 2013).
Kegagalan Tercapainya Tujuan Resolusi 1973 DK PBB dan R2P
Baik Resolusi 1973 maupun R2P memiliki benang merah yang sama yaitu perlindungan populasi. R2P menegaskan tanggung jawab untuk melindungi populasi dari genosida kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Lebih spesifik lagi, Resolusi 1973 memandatkan perlindungan terhadap penduduk sipil dan kawasan populasi sipil yang berada dalam ancaman Jamahiriya Arab Libya melalui berbagai tindakan yang diperlukan (Terry, 2015). Sejatinya pun, resolusi tersebut dikeluarkan dengan landasan Bab 7 Piagam PBB (Terry, 2015) yang mengatur tindakan yang berkaitan dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Resolusi 1973 dan R2P sama-sama memiliki semangat kemanusiaan dan bertujuan untuk menjaga hal tersebut. Artinya, NATO harus menjaga dan mengedepankan kemanusiaan di Libya dengan melindungi penduduk sipil dari berbagai kekerasan dan konflik yang mungkin terjadi, baik itu dari pemerintahan Qaddafi, kelompok pemberontak, maupun NATO. Baik sebagai prinsip dalam melakukan intervensi maupun sebagai tujuan dari intervensi.
Lantas bagaimana penerapan semangat kemanusiaan tersebut dalam praktiknya? Dalam pemaparan bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan prinsip kebutuhan militer dari tindakan militer NATO. Penduduk sipil turut menjadi korban dan kawasan tempat tinggalnya turut luluh lantah. Kehadiran NATO di Libya seakan-akan menyimpang dari tujuan awalnya untuk melindungi penduduk sipil menjadi tindakan politis yang mengincar Qaddafi sebagai musuh. Hal ini tampak dari bom NATO yang meledakkan sebuah gedung di Tripoli hingga menewaskan salah satu anak laki-laki Qaddafi dan tiga orang cucu Qaddafi (Terry, 2015). Terdapat upaya dari NATO yang memperlakukan Qaddafi sebagai musuh. NATO seakan-akan terlibat dalam peperangan melawan pemerintahan Qaddafi. Hal ini tentu menyimpang, tidak hanya karena adanya pergeseran dari tujuan untuk melindungi penduduk sipil, tapi juga karena Resolusi 1973 tidak memberikan izin NATO untuk mengambil keberpihakan dalam suatu perang internal apapun ancaman serangan terhadap penduduk sipil (Terry, 2015). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa NATO telah gagal dalam mencapai tujuannya sesuai yang dimandatkan oleh Resolusi 1973 dan R2P.
Kesimpulan
Intervensi NATO secara yuridis terikat pada hukum humaniter internasional, Resolusi 1973, dan R2P. Meskipun ketiga hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya mengikat tetapi fakta bahwa NATO terikat pada ketiga instrumen tersebut tidak dapat dipungkiri karena ketiganya disusun berdasarkan hukum kebiasaan dalam skala internasional. Dari pemaparan dan argumentasi esai ini, dapat disimpulkan bahwa NATO telah melanggar ketiganya. Pelanggaran hukum humaniter internasional menjadi titik mula gugurnya kemanusiaan dalam praktik intervensi NATO di Libya. Penggunaan kekuatan militer NATO telah menciptakan penderitaan yang tidak perlu dan kerusakan yang berlebihan. Lebih lanjut lagi, NATO telah melanggar instrumen-instrumen yang menjadi justifikasi intervensinya di Libya yaitu Resolusi 1973 DK PBB dan R2P. NATO yang seharusnya hadir untuk melindungi penduduk sipil di Libya malah cenderung mengabaikannya. Pada praktiknya, kekuatan militer digunakan oleh NATO secara politis untuk menjatuhkan Qaddafi dari kursi kepemimpinan di Libya. Meskipun tidak disebutkan dalam Resolusi 1973 dan R2P, kata intervensi tidaklah salah untuk menyebutkan tindakan NATO di Libya. NATO tidak hadir untuk melindungi kemanusiaan tapi hadir untuk mengintervensi konflik domestik suatu negara.
REFERENSI
Crowe, J. & Weston-Scheuber, K. (2013). Principles of International Humanitarian Law. Edward Elgar.
Dyke, J. (2021, 20 Maret). NATO Killed Civilians in Libya. It’s Time to Admit It. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2021/03/20/nato-killed-civilians-in-libya-its-time-to-admit-it/
Kuperman, A. J. (2013). A Model Humanitarian Intervention? Reassessing NATO's Libya Campaign. International Security, 38(1), 105-136. https://www.jstor.org/stable/24480571
Libya profile - Timeline. (2021, 15 Maret). BBC News. https://www.bbc.com/news/world-africa-13755445
Terry, P. (2015). The Libya intervention (2011): neither lawful, nor successful. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 48(2), 162-182. https://www.jstor.org/stable/24585876
Unacknowledged Deaths: Civilian Casualties in NATO’s Air Campaign in Libya. (2012, 14 Mei). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/report/2012/05/13/unacknowledged-deaths/civilian-casualties-natos-air-campaign-libya
0 notes
Text
Kapitalisme dalam Konstruksi Identitas Gender
Gender dan Politik | 23 Desember 2021
Suatu konstruksi kekuasaan dapat terjadi dalam sebuah sistem yang bersifat hierarkis. Ada elemen yang menempati posisi di atas, ada yang di bawahnya, di bawahnya lagi, di bawah bawahnya lagi, dan seterusnya. Sebuah faktor dapat disebut sebagai faktor kuasa ketika kehadiran dan dinamika operasionalnya berpengaruh secara signifikan terhadap hal lain. Kondisi ini tidak terkecuali terjadi dalam pembentukan identitas gender. Ketika membicarakan identitas gender, sering kali kita menunjuk pada pengaruh kultur, pengaruh patriarki, pengaruh norma, dan pengaruh biologis. Akan tetapi, pengaruh-pengaruh tersebut hanya menjelaskan alasan yang mendasari konstruksi identitas gender bukan menjelaskan terjadinya proses konstruksi. Lantas, pengaruh apa yang dapat menjelaskan jalan terjadinya proses pembentukan identitas gender? Jawabannya adalah sistem kapitalisme. Pasalnya, kapitalisme sebagai sistem yang secara inheren eksploitatif berjalan berkelindan dengan sistem patriarki yang opresif (Eisenstein, 1979). Sistem ekonomi yang kapitalis menjadi landasan konstruksi sosial dan kuasa dalam mendefinisikan unsur femininitas dan maskulinitas, baik itu dalam melabeli identitas seseorang maupun dalam mengasosiasikan pekerjaan dan peran tertentu. Lebih spesifik lagi, sistem kapitalisme merupakan suatu sistem yang hierarkis sehingga menjadi ruang operasional yang tepat bagi patriarki dalam melakukan opresi dengan meletakkan identitas feminin dan maskulin dalam suatu strata.
Kapitalisme merupakan sistem yang meletakkan pencapaian material sebagai parameter keberhasilan. Sebagai konsekuensinya, produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah material menjadi aspek penting dalam relasi sosial dan politik. Produktivitas menjadi aspek yang dinomorsatukan, dianggap superior. Implikasi dari logika tersebut adalah mereka yang tidak mampu menghasilkan nilai tambah material dianggap sebagai kelas dua, dipandang rendah, dan dipandang sebagai sub-ordinat. Pandangan Marx mengenai relasi material tersebut nyatanya dapat diekstrak dan diaplikasikan dalam memahami opresi gender (Eisenstein, 1979). Hal inilah yang diyakini oleh perspektif feminisme marxis. Lebih lanjut lagi, perspektif tersebut tidak hanya melihat opresi terhadap pekerja dengan gender tertentu namun mencakup kacamata di luar sistem produksi secara langsung.
Perspektif feminisme marxis menyebut sistem yang opresif sebagai sistem kapitalis patriarki. Sama halnya dengan perspektif marxis, dalam sistem ini seseorang harus menghasilkan nilai tambah melalui proses produksi untuk dianggap berharga. Konstruksi gender kemudian terbentuk dengan mengasosiasikan gender tertentu dengan fungsi reproduksi dan aspek biologisnya (Eisenstein, 1979b). Seseorang dengan unsur biologis rahim, vagina, dan hormon progesteron serta dengan fungsi reproduksi berupa mengandung anak, melahirkan, menyusui, dan menstruasi secara deterministik dikonstruksikan sebagai gender feminin. Lebih jauh lagi, unsur patriarki dapat dijumpai dengan asosiasi bahwa identitas gender feminin memiliki peran sentral yang berkaitan dengan keberlangsungan utilisasi fungsi reproduksi dan aspek biologisnya yaitu dengan melakukan pekerjaan domestik. Pengabaian pekerjaan domestik sebagai suatu ‘usaha’ yang dilakukan oleh seseorang dengan gender feminin—dengan hormon progesteron—disebabkan oleh tidak adanya akumulasi kapital dan pertambahan nilai material yang dihasilkan. Sebaliknya, sistem kapitalis patriarki mengkonstruksikan identitas seseorang yang memiliki hormon testoteron sebagai gender maskulin. Perannya pun diesensialkan dengan peran bekerja di luar rumah—sebagai pekerja, sebagai buruh, sebagai pencari nafkah, yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah material. Konstruksi sedemikian rupa inilah yang membuat identitas gender maskulin dilihat sebagai gender yang lebih tinggi dibanding gender feminin.
Unsur opresif terhadap gender feminin lainnya dapat dilihat dari berlangsungnya proses alienasi. Marx mendefinisikan manusia sebagai makhluk spesies (species beings), artinya makhluk yang berkembang mencapai kapasitas potensialnya untuk kerja kreatif, kesadaran sosial, dan kehidupan sosial melalui perjuangan melawan masyarakat kapitalis (Eisenstein, 1979a). Mereka yang tidak bisa berkembang untuk mencapai kapasitas potensialnya pun mengalami proses alienasi. Dalam perspektif marxis, kelompok yang mengalami alienasi adalah kelompok pekerja. Jika digunakan dalam memandang relasi gender, proses alienasi terjadi terhadap identitas gender feminin. Terdapat empat cara berlangsungnya alienasi terhadap tubuh yang feminin. Pertama, tubuh teralienasi dari produk yang mereka hasilkan. Kedua, tubuh teralienasi dari tubuhnya sendiri saat bekerja—mengalami dehumanisasi. Ketiga tubuh teralienasi dari tubuh lain sehingga menciptakan iklim yang kompetitif. Keempat, tubuh teralienasi dengan alam karena kehadiran alam dipandang menghambat kelangsungan hidup. Implikasi dari proses alienasi membuat tubuh kesulitan untuk membangun makna tanpa ilusi mengenai diri mereka, secara spesifik yaitu ilusi yang diciptakan oleh sistem kapitalis patriarki. Kebebasan tubuh feminin pun berdampingan dengan kehadiran eksploitasi dan opresi—sebab makna tubuh feminin sejatinya selalu lebih dari eksistensinya secara fisik (Eisenstein, 1979a).
Apakah peran dari sistem kapitalisme berlaku dalam pengalaman saya melihat masyarakat? It used to, meskipun pada saat itu saya belum memiliki pemahaman yang cukup tapi di sinilah unsur kekuasaan bekerja dengan baik. Sejak kecil dan masuk sekolah, setidaknya saya, selalu disosialisasikan dengan norma bahwa seseorang dengan fungsi reproduksi melahirkan dan sebagainya—perempuan—memiliki identitas gender yang feminin dan sebaliknya. Norma tersebut melihat bahwa pembagian identitas gender bersifat biner, either it’s feminine or masculine. Seakan-akan tidak ada tubuh dengan fungsi reproduksi melahirkan yang memiliki identitas gender di luar identitas feminin. Seakan-akan tidak ada tubuh lain yang tidak memiliki fungsi reproduksi melahirkan namun mengidentifikasi dirinya sebagai gender feminin. Norma yang sama juga menekankan bahwa perempuan, tubuh yang secara inheren beridentitas feminin, memiliki peran sentral yang hanya sebatas dalam melakukan reproduksi dan mengurus persoalan domestik. Nilai dan kontribusi perempuan terhadap masyarakat hanya dilihat dari kemampuan reproduktif yang ditujukan untuk mencetak buruh pekerja bagi sistem kapitalisme. Pun ketika seorang perempuan memasuki ranah pekerja kapitalisme, apresiasi terhadapnya nyaris nihil dan pencapaiannya tidak dianggap signifikan—semua karena identitas gender dan organ biologisnya. Semua karena konstruksi identitas gender yang esensialis. She belongs in the kitchen. “Kasur, sumur, dapur,” ujar mereka.
Mirisnya, opresi dari sistem kapitalis patriarki di Indonesia pernah dengan nyata diaplikasikan secara institusional pada tingkat negara. Rezim Orde Baru, melalui ideologi Ibuisme Negara, mendefinisikan perempuan sebagai pendamping suami, sebagai pembuat bangsa, sebagai ibu dan pendidik untuk anak-anak, sebagai pengurus rumah (Suryakusuma, 1999) Makna kata “ibu” yang luas dipersempit oleh negara terbatas pada makna biologis (Suryakusuma, 1999). Konstruksi identitas tersebut terujud dalam beberapa institusi nasional seperti Dharma Wanita, Kongres Wanita Indonesia, Kementerian Urusan Peranan Wanita, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang menjadi kanal kendali negara terhadap identitas gender (Suryakusuma, 1999). Esensialisme identitas gender juga dilakukan rezim Orde Baru dengan mereduksi makna Hari Ibu yang sejatinya merayakan pemberdayaan dan pergerakan perempuan menjadi peran perempuan yang terdomestikasi serta makna Hari Kartini yang merayakan emansipasi perempuan menjadi ajang kontestasi pakaian daerah. Semua demi menyokong kapitalisme.
Konstruksi demikian berimplikasi pada logika bahwa kodrat perempuan harus di rumah, untuk mengurus anak, yang nantinya menghasilkan buruh baru untuk menyokong berjalannya kapitalisme. Logika ini berjalan berkelindan dengan logika bahwa perempuan tidak perlu sekolah karena takdirnya hanyalah di rumah. Implikasinya, ketika terjadi satu dan lain hal di luar rencana sehingga memaksa perempuan untuk bekerja di luar rumah, mereka justru menghadapi diskriminasi. Tidak ada riwayat pendidikan, stereotip bahwa mereka hanya di rumah, membuat mereka rentan mendapat upah rendah (Wolf, 1999). Wolf (1999) pun menemukan adanya anak-anak perempuan yang dipaksa oleh ayahnya untuk bekerja sebagai buruh pabrik di Jawa meskipun mereka masih di bawah kriteria usia minimum. Para buruh perempuan—dewasa maupun anak-anak—dipandang tidak memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni sehingga mereka memperoleh timbal balik berupa upah yang sangat kecil, dibandingkan dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan dan upah buruh laki-laki. Opresi terhadap perempuan di dunia kerja juga terjadi melalui perampasan hak cuti haid ataupun pemotongan gaji ketika mengambil cuti tersebut (Istakhori, 2018).
Nyatanya, konstruksi identitas juga menyebabkan opresi terhadap mereka yang memiliki identitas bukan cisgender—tidak sama dengan jenis kelamin saat dilahirkan—dan mereka dengan identitas gender non-biner—di luar dikotomi feminin dan maskulin. Contoh sederhana dapat dilihat dari realitas yang dihadapi seorang transpuan. Terlahir dengan jenis kelamin laki-laki membuat mereka dilabeli dengan identitas gender maskulin. Ketika mereka menyadari bahwa menjadi seorang maskulin bukanlah identitasnya, ketika mereka memutuskan untuk merealisasikan identitas ekspresi gender yang sebenarnya mereka rasakan, diskriminasi, stigma, dan kebencian datang terhadap mereka (Menjadi Manusia, 2020). Dari perspektif feminisme marxis, opresi terhadap transpuan dapat dipahami terjadi karena mereka mendobrak konstruksi identitas gender yang dibentuk oleh sistem kapitalis patriarki. Mereka tidak menjadi tubuh yang maskulin dan tidak menjadi tubuh yang berperan sebagai buruh. Mereka menjadi ancaman bagi berlangsungnya sistem kapitalisme.
Dalam sistem kapitalis patriarki, tubuh dijadikan objek untuk mendukung berlangsungnya hierarki kekuasaan. Sistem kapitalisme menjadi faktor yang berperan kuat dalam mengkonstruksi identitas gender seseorang. Identitas gender dikonstruksi sedemikian rupa oleh sistem, oleh kekuasaan, alih-alih diekspresikan oleh tubuh itu sendiri. Tubuh menjadi objek untuk memenuhi kepentingan kekuasaan tertentu, menjadi bagian dari sistem pertukaran. Identitas gender dibangun dengan mengesensialisasikan organ dan fungsi biologis. Lebih lanjut lagi, tubuh yang dikonstruksikan dengan gender feminin dimarjinalisasi dan dipandang sebagai sub-ordinat dalam sistem kapitalis patriarki sehingga perannya dalam masyarakat pun dimaknai sebagai peran sekunder. Alih-alih dipandang sebagai tubuh yang utuh, tubuh yang selalu berkembang untuk mencapai kapasitas potensialnya, nilai dan fungsi tubuh feminin ditentukan oleh kemampuan mereka dalam aspek reproduksi, seksualitas, produksi, dan sosialisasi anak-anak. Berhasilnya pengaruh faktor kuasa dalam membentuk identitas gender pun turut berperan dalam cara saya memahami apa yang terjadi di masyarakat. Saya pernah berada pada titik di mana saya memandang identitas gender sebagai sesuatu yang terikat dengan organ biologis tubuh dan memandang identitas feminin secara mutlak memiliki peran dalam masyarakat yang berkaitan dengan urusan domestik. Tubuh feminin boleh mengejar dan mendapat berbagai pencapaian di luar rumah asalkan kondisi domestik tetap terkendali karena kodrat tubuhnya adalah di rumah. Kemerdekaan tubuh menjadi terbelenggu karena fungsinya ditentukan untuk menjamin pencetakkan buruh tetap berjalan dengan mulus.
Referensi
Eisenstein, Z. R. (1979a). Developing a Theory of Capitalist Patriarchy and Socialist Feminism. Dalam Z. R. Eisenstein (eds.), Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism (pp. 5-40). Monthly Review Press.
Eisenstein, Z. R. (1979b). Some Notes on the Relations of Capitalist Patriarchy. Dalam Z. R. Eisenstein (eds.), Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism (pp. 41-55). Monthly Review Press.
Istakhori, K. (2018, 8 Maret). Eksploitasi Buruh Perempuan Melalui Perampasan Cuti Haid. Majalah Sedane. https://majalahsedane.org/eksploitasi-buruh-perempuan-melalui-perampasan-cuti-haid/
Menjadi Manusia. (2020, 20 Mei). 177. #CeritaMereka Tentang Menjadi Seorang Transpuan [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6NKW7Ln-K30
Suryakusuma, J. I. (1999). The State and Sexuality in New Order in Indonesia. Dalam L. J. Sears (eds.), Fantasizing the Feminine in Indonesia (pp. 92-119). Duke University Press.
Wolf, D. L. (1999). Javanese Factory Daughters: Gender, the State, and Industrial Capitalism. Dalam L. J. Sears (eds.), Fantasizing the Feminine in Indonesia (pp. 140-162). Duke University Press.
0 notes
Text
Perkebunan Kelapa Sawit di Papua: Mimikri dalam Pembangunan Pasca-Kolonial
Ekonomi Politik Pembangunan | 3 November 2021
Mimikri merupakan sebuah konsep dalam tradisi pemikiran Pasca-kolonial yang dikenalkan oleh Homi Bhabha. Menurutnya, mimikri adalah sebuah praktik di mana kelompok sub-altern berusaha untuk mengikuti, menerapkan, dan mengimplementasikan nilai, norma, dan praktik yang dibawa oleh pengkoloni (Bhabha, 1994, p. 86). Meski terkesan bahwa kelompok sub-altern berusaha untuk menyamakan diri dengan pengkoloni, nyatanya tidak demikian. Bhabha (1994, p. 89) menyebut praktik mimikri melahirkan hasil yang “almost the same but not quite.” Penyebabnya adalah bahwa sejatinya antara kelompok sub-altern dengan pengkoloni memiliki kebiasaan hidup, nilai, dan norma yang berbeda sehingga pada dasarnya mustahil bagi kelompok sub-altern menjadi sepenuhnya sama dengan pengkoloni. Akan tetapi, antara keduanya terdapat relasi kuasa yang timpang. Di sinilah tampak aspek opresif dalam sebuah proyek ekonomi politik. Pengkoloni memaksakan proyek pembangunan ekonomi dengan cara dan nilainya sendiri terhadap kelompok sub-altern. Apabila relasi kuasa antara keduanya setara, kelompok sub-altern pasti bisa menolak pemaksaan tersebut. Akan tetapi, sebab relasi kuasa yang timpang, kelompok sub-altern terpaksa untuk menerima dan mengikuti pemaksaan dari pengkoloni. Mereka tidak memiliki pilihan selain menerima dan mengikuti pengkoloni agar bisa bertahan hidup.
Kasus menarik yang menggambarkan kondisi ini adalah kasus mengenai industri perkebunan kelapa sawit di Papua. Acosta & Curt (2019, p. 200) menjelaskan bahwa penanaman kelapa sawit di Papua menghancurkan ekosistem alam, menghilangkan kawasan hutan, dan mengganggu kelangsungan hidup penduduk lokal yang berkonsentrasi di hutan. Pembangunan industri kelapa sawit di Papua sendiri didorong oleh dampak positif perekonomian Indonesia dan peningkatan PDB Indonesia karena industri kelapa sawit (Acosta & Curt, 2019, p. 199). Kabar baik tersebut membuat pemerintah pusat Indonesia berusaha untuk terus menambah jumlah komoditas minyak kelapa sawit, atau setidaknya mempertahankan jumlah yang sudah ada, untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Aspek opresif dari pembangunan ekonomi dalam kasus ini tampak dari kebijakan-kebijakan yang mendorong industri kelapa sawit di lahan yang jelas-jelas sudah memiliki fungsi dan nilainya tersendiri bagi penduduk lokal yaitu hutan Papua. Kebijakan yang demikian secara nyata mengorbankan praktik kehidupan asli penduduk Papua dengan mengatasnamakan pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut juga terbukti mendorong praktik-praktik deforestasi yang mengorbankan hutan adat masyarakat Papua (Aditya, 2020a; Greenpeace Indonesia, 2021). Greenpeace Indonesia (2021) juga menemukan bahwa hingga 2019, hutan adat di Papua seluas 168.471 hektar telah berubah menjadi lahan perkebunan sawit. Sayangnya, antara penduduk bahkan pemerintah daerah Papua sendiri memiliki relasi kuasa yang lebih rendah dibandingkan pemerintah pusat Indonesia. Pada akhirnya pun, mau tidak mau, penduduk Papua harus menerima implementasi kebijakan tersebut.
Lantas, di mana aspek mimikrinya? Mimikri terjadi di kala penduduk Papua harus melakukan praktik yang sejatinya tidak sejalan dengan praktik kehidupan mereka. Lebih lanjut lagi, dampak dari pembangunan industri kelapa sawit terhadap kehidupan penduduk Papua sangat besar. Terlepas dari aspek kerusakan yang disebabkan, tidak sedikit penduduk Papua yang pada akhirnya menjadi buruh perkebunan kelapa sawit di tanah mereka sendiri. Dilansir dari berita Antara News, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Merauke mengungkapkan bahwa industri kelapa sawit di kabupaten tersebut berhasil menyerap 2.474 orang asli Papua sebagai tenaga kerja. Mimikri dalam kasus ini semakin jelas dengan adanya justifikasi dari tokoh adat masyarakat Papua, Pdt Albert Yoku, yang menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit mampu “mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan masyarakat dari berbagai suku” (Subagyo, 2021).
Hal yang menarik pun tampak dari pembingkaian yang dilakukan oleh berbagai media Indonesia dan pemerintah pusat Indonesia mengenai betapa positifnya kontribusi yang diberikan industri tersebut terhadap kehidupan di Papua. Gambar di bawah merupakan tangkapan layar dari hasil pencarian ketika saya mengetikan kata kunci “industri sawit papua” di Google. Pembingkaian tersebut menunjukkan adanya logika dasar kolonialis, di mana perlu adanya pembuktian bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pengkoloni terhadap penduduk sub-altern membawa dampak positif, bahwa pengkoloni merupakan penyelamat bagi penduduk sub-altern yang kehidupannya mengalami ketertinggalan namun dengan cara yang tidak kontekstual dan mengabaikan politik kelokasian.
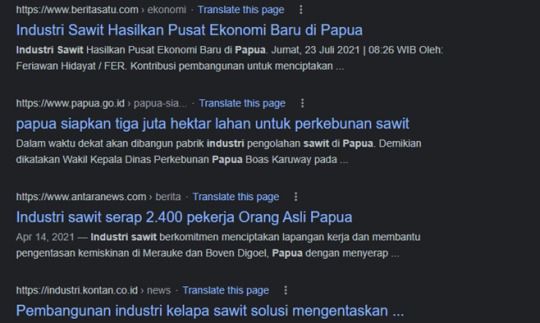
Pemerintah pusat Indonesia di sini dapat dikatakan sebagai pengkoloni karena merupakan pihak yang memaksakan penerapan kebijakan nilainya yang berbeda dengan nilai lokal di Papua. Kebijakan tersebut sejatinya ditujukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuantitatif, yang disinyalir kemudian hasilnya mampu meningkatkan dan memeratakan pembangunan di Indonesia khususnya di Papua. Dikutip dari berita Jawa Pos, Staf Khusus Wapres RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah menyatakan bahwa industri kelapa sawit merupakan “industri prioritas dalam pengentasan kemiskinan” sehingga harus turut “dilakukan di Indonesia bagian Timur.” Tidak hanya pemerintah pusat, pengkoloni dalam kasus ini juga terdiri dari aktor-aktor privat, salah satunya adalah PASPI atau Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. Direktur Eksekutif PASPI menyatakan bahwa perkebunan sawit berkontribusi dalam “membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua.”
Nyatanya pun, berhasilnya pengkoloni menjalankan kebijakannya terhadap kelompok sub-altern beserta hasil positifnya tidak dapat dijadikan indikator berhasilnya suatu proyek ekonomi pembangunan. Kesuksesan suatu proyek pembangunan seharusnya lebih berorientasi pada kelompok sub-altern. Artinya, penilaian kesuksesan tersebut harus menekankan pada etnografi maupun politik kelokasian dari kondisi kehidupan masyarakat sub-altern. Jika tidak demikian, kesimpulan bahwa proyek pembangunan sukses dilakukan meskipun faktanya kelompok sub-altern tidak mendapat keuntungan apapun atau bahkan teropresi, merupakan kesimpulan yang memiliki logika kolonialis atau logika penjajah.
Logika yang demikian menurut saya lahir dari apa yang disebut oleh Arturo Escobar sebagai diskursus pembangunan. Menurutnya, negara-negara Barat membentuk pemahaman mengenai apa yang tergolong modern dan maju melalui setidaknya tiga hal yaitu tipe rasionalitas yang berkaitan dengan mereka, bentuk kekuasaan dan pengetahuan yang mencirikan mereka, dan cara mereka mengasumsikan tanggung jawab atas kondisi kehidupan (Escobar, 1984, p. 395). Escobar menguatkan argumentasinya dengan menggarisbawahi adanya pengabaian oleh para ahli terhadap dampak dari proyek pembangunan ala Barat yang menyebabkan tidak membaik bahkan semakin memburuknya kondisi kehidupan dari banyak orang (Escobar, 1995, p. 5). Dari pemikiran Escobar tersebut, penting untuk memproblematisasi, “pembangunan untuk siapa? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pembangunan ini? Apakah pembangunan tersebut benar-benar ‘membangun’ masyarakat sub-altern?”
Oleh karena pemahaman mengenai pembangunan dan modernitas terbentuk melalui suatu diskursus, pemahaman yang diproduksi oleh negara-negara Barat pun dapat dilawan oleh masyarakat sub-altern. Praktik mimikri yang dilakukan oleh masyarakat sub-altern adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk narasi baru mengenai pembangunan. Bhabha (1994, p. 88) menyebutkan bahwa praktik mimikri menghasilkan visi ganda akibat adanya representasi parsial atas masyarakat sub-altern dalam suatu proyek pembangunan. Visi ganda tersebut juga melahirkan ambivalensi (Bhabha, 1994, p. 88) karena masyarakat sub-altern seakan-akan dijejali dengan norma dan nilai yang tidak selaras dengan norma dan nilai asli mereka. Di sinilah mimikri dapat menjadi ancaman bagi pengkoloni (Bhabha, 1994, p. 88) karena posisi pengkoloni seakan-akan berupaya ditentang oleh masyarakat sub-altern.
Praktik mimikri yang ada dimanfaatkan oleh kelompok sub-altern untuk masuk dalam praktik diskursus pembangunan sebagai subjek pembangunan, alih-alih tetap sebagai objek pembangunan. Masuknya kelompok sub-altern dalam diskursus membuka ruang bagi mereka untuk mengartikulasikan kepentingan mereka juga sehingga representasi mereka menjadi tidak begitu parsial, jika tidak bisa penuh, dalam proyek pembangunan yang berjalan. Dalam kata lain, upaya artikulasi tersebut merupakan bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat sub-altern terhadap pengkoloni. Upaya masyarakat sub-altern dalam membentuk diskursus pembangunan menunjukkan agensi masyarakat sub-altern. Hal ini bertentangan dengan logika dasar pemikiran pembangunan Barat yang melihat masyarakat Dunia Ketiga sebagai masyarakat yang lemah dan tidak berdaya hanya atas dasar tidak adanya kepemilikan mereka atas gaya hidup dan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara Barat. Dari upaya artikulasi masyarakat sub-altern, lahirlah sebuah sistem hibrida yang secara sederhana dapat dikatakan merupakan penggabungan kepentingan, nilai, dan norma masyarakat sub-altern dengan proyek pembangunan. Meski demikian, sistem hibrida ini tidak secara otomatis mengartikan hilangnya representasi parsial atas masyarakat sub-altern.
Praktik mimikri yang dilakukan oleh penduduk Papua terhadap kebijakan pengalihfungsian lahan untuk perkebunan sawit memiliki celah yang dapat mereka manfaatkan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Tatkala masyarakat Papua ‘mengizinkan’ penggunaan lahannya untuk perkebunan sawit, terjadi permasalahan praktik yang tidak sesuai dengan prosedur dan izin yang ditetapkan. Korindo, perusahaan kelapa sawit asal Korea Selatan yang melakukan operasional perkebunan di Papua, ditemukan melanggar ketentuan di Indonesia melalui investigasi yang dilakukan oleh BBC (Aditya, 2020b). Perusahaan tersebut melakukan pembakaran hutan adat besar-besaran dan sengaja untuk memperluas lahan perkebunan sawit di Boven Digoel, Papua (Aditya, 2020b). Artikulasi kepentingan masyarakat sub-altern tampak dari pernyataan Manajer Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Boy Even Sembiring, yang membela posisi hutan adat Papua sebagai wilayah otonomi khusus sehingga lahan tersebut tidak dapat diperlakukan sama dengan tanah milik negara. Selain itu, Boy juga mengungkapkan bahwa ganti rugi Rp100.000 per hektar dari hutan adat yang diberikan perusahaan Korindo pun tidak masuk akal (Aditya, 2020b). Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa WALHI merupakan aktor yang menjembatani pengartikulasian kepentingan masyarakat Papua di hadapan korporat atau pengkoloni.
Sementara itu, temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas saratnya masalah perizinan perusahaan sawit di Provinsi Papua Barat mendorong pihak yang berwenang di Provinsi Papua untuk mengambil langkah terkait perizinan operasional perusahaan sawit di Provinsi Papua (Fadli, 2021). Dalam kasus ini, aktor yang berperan dalam menjembatani pengartikulasian kepentingan masyarakat Papua adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua di hadapan pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI. Kepala Kantor BPN Provinsi Papua, John Wicklif Aufa, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi dan evaluasi atas Hak Guna Lahan (HGU) di seluruh wilayah Papua melalui koordinasi dengan kantor-kantor pertanahan setempat (Fadli, 2021).
Secara implementasinya, mungkin masih patut dipertanyakan dan perlu menunggu perkembangan selanjutnya. It remains to be seen. Meski demikian, jika dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran pembangunan pasca-kolonial dan pembangunan sebagai diskursus, upaya artikulasi kepentingan masyarakat Papua yang dijembatani oleh WALHI dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua di atas menunjukkan adanya agensi masyarakat sub-altern dalam proyek pembangunan ekonomi yang opresif. Menyesuaikan dengan sistem hibrida yang dipaparkan oleh Bhabha, maka yang harus kita tunggu dari perkembangan kasus ini adalah sistem hibrida seperti apa yang akan terbentuk.
Referensi
Acosta, P. & Curt, M. D. (2019). Understanding the expansion of oil palm cultivation: A case-study in Papua. Journal of Clear Production, 219, 199-216. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.02.029
Aditya, N. R. (2020b, 13 November). Kisah Pilu Habisnya Hutan Adat di Papua demi Perluasan Lahan Kelapa Sawit. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/05170081/kisah-pilu-habisnya-hutan-adat-di-papua-demi-perluasan-lahan-kelapa-sawit
Aditya, N. R. (2020b, 13 November). Walhi: Ganti Rugi Rp 100.000 Per Hektar untuk Tanah Adat Papua Tak Masuk Akal. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/16130451/walhi-ganti-rugi-rp-100000-per-hektar-untuk-tanah-adat-papua-tak-masuk-akal?page=all
Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. Routledge.
Binekasri, R. (2021, 13 April). Industri Kelapa Sawit di Tanah Papua Dapat Serap Tenaga Kerja. Jawa Pos. https://www.jawapos.com/ekonomi/13/04/2021/industri-kelapa-sawit-di-tanah-papua-dapat-serap-tenaga-kerja/
Escobar, A. (1984). Discourse and Power in Development: Michel Foucault and the Relevance of His Work to the Third World. Alternatives: Global, Local, Political, 10(377), 377-400. DOI: 10.1177/030437548401000304
Escobar, A. (1995). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton University Press.
Fadli, A. (2021, 15 Agustus). Sarat Masalah, Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Papua dan Papua Barat Dievaluasi. Kompas. https://www.kompas.com/properti/read/2021/08/15/120000521/sarat-masalah-perizinan-perkebunan-kelapa-sawit-di-papua-dan-papua?page=all
Greenpeace Indonesia. (2021, 6 April). Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua. Greenpeace. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44826/deforestasi-terencana-mengancam-tanah-adat-dan-lanskap-hutan-di-tanah-papua/
Subagyo. (2021, 14 April). Industri sawit serap 2.400 pekerja Orang Asli Papua. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/2099766/industri-sawit-serap-2400-pekerja-orang-asli-papua
0 notes
Text
Ringkasan Kebijakan (Policy Brief): Mengatasi Pernikahan Anak di Indonesia sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Penduduk Indonesia
Strategi | 2 Juli 2021
A. Ikhtisar
Pernikahan anak telah terbukti menimbulkan dampak multidimensional terhadap kualitas hidup penduduk di Indonesia. Meski demikian, pada faktanya Indonesia menempati peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia dengan kasus pernikahan anak terbanyak.[1] Dokumen ini mencantumkan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menekan angka kasus pernikahan anak di Indonesia.
B. Rekomendasi Kebijakan
v Menghapus Pemberian Dispensasi Pernikahan Anak
Pemerintah pusat harus menghapus pemberian dispensasi pernikahan usia di bawah ketentuan UU untuk mengantisipasi dan membatasi adanya praktik pernikahan anak.
v Mengawasi Pernikahan di Berbagai Daerah
Pemerintah pusat harus menggandeng pemerintah daerah serta badan-badan relevan dan KUA setempat untuk mengawasi data usia pernikahan guna mengantisipasiadanya praktik pernikahan anak.
v Mendirikan LSM dan Memberdayakan Gerakan Masyarakat Sipil untuk Mengkampanyekan Dampak Negatif Pernikahan Anak
LSM dan gerakan masyarakat sipil dapat menjadi opsi untuk mengkampanyekan dampak negatif dari pernikahan anak agar norma sosial di masyarakat tersebut dapat mengalami pergeseran menjadi anti pernikahan anak.
v Menggandeng Pemuka Agama Setempat untuk Menyebarkan Pemahaman mengenai Pernikahan Anak
Pemuka agama setempat memiliki peran penting karena posisinya yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam kehidupan masyarakat tertentu. Pemuka agama dapat memberi pengaruh sosial sehingga membentuk preferensi masyarakat untuk tidak melakukan praktik pernikahan anak.
v Melakukan Edukasi secara Rutin dan Masif mengenai Dampak Negatif Pernikahan Anak
Edukasi yang dilakukan secara rutin dan masif mengenai dampak negatif dari pernikahan anak dapat mempengaruhi dan merekayasa emosi dari masyarakat bahwa pernikahan anak merupakan praktik yang tidak selayaknya dilakukan.
v Meningkatkan Akses Penduduk di Daerah Pedesaan terhadap Pendidikan Berkualitas
Pemerintah harus menambah jumlah sekolah terutama di daerah-daerah terpencil, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menggratiskan biaya pendidikan agar memperluas akses penduduk terhadap pendidikan berkualitas. Dengan terbukanya akses tersebut, masyarakat pun memiliki pilihan dan preferensiuntuk mengenyam pendidikan.
C. Urgensi Penanganan Isu
Fakta di lapangan dan riset ilmiah menunjukkan bahwa pernikahan anak memiliki banyak dampak negatif dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, penting untuk menekan angka pernikahan anak di Indonesia. Dampak-dampak negatif dari pernikahan anak adalah sebagai berikut:
Ø Berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental, baik bagi anak yang dinikahkan maupun bagi bayi yang dilahirkan dari pernikahan anak.[2]
Terdapat sejumlah kondisi yang membahayakan remaja jika hamil di usia muda seperti tekanan darah tinggi, anemia, dan risiko mengalami kematian. Bayi yang dilahirkan juga memiliki kemungkinan untuk lahir secara prematur. Di sisi lain, remaja belum memiliki kesiapan mental dan kedewasaan yang cukup untuk mengurus kehidupan rumah tangga dan mengurus anak.
Ø Penelantaran anak hasil dari pernikahan anak.[3]
Anak dari hasil pernikahan di bawah umur rentan untuk mengalami penelantaran nasib karena ketidakmampuan orangtuanya dalam mengurus dan adanya ketidakstabilan rumah tangga.
Ø Melanggengkan kekerasan terhadap perempuan.[4]
Anak perempuan diekspektasikan untuk mengurus rumah tangga padahal usianya yang masih sangat belia membuatnya tidak memiliki kemampuan yang cukup. Akibatnya, mereka kerap mendapat perlakuan kekerasan dari suami.
Ø Menghilangkan kesempatan anak untuk mengenyam pendidikan.[5]
Menikahnya anak di bawah umur membuat mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan dan mengenyam pendidikan. Hilangnya kesempatan tersebut menjadi batu sandungan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
D. Permasalahan Saat Ini
§ Peraturan Legal di Indonesia yang Memungkinkan Pernikahan Anak
Saat ini pernikahan di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. UU tersebut menyebutkan bahwa minimal usia untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Meski demikian, UU tersebut memberi kelonggaran berupa dispensasi untuk pernikahan di bawah ketentuan usia tersebut dengan alasan mendesak.[6] Dispensasi ini menjadi celah bagi masyarakat untuk melakukan praktik pernikahan anak.
§ Manipulasi Data Usia
Masih terdapat kasus-kasus di mana orangtua memanipulasi data usia anaknya yang akan dinikahkan dengan cara membuat KTP palsu. Pembuatan KTP palsu ini di antaranya melibatkan RT dan RW setempat.[7] Adanya manipulasi data ini membuat praktik pernikahan anak menjadi tidak terdeteksi.
§ Kemiskinan
Beberapa kasus pernikahan anak terjadi karena ketidakmampuan orangtua untuk membiayai hidup dan pendidikan anaknya lebih lanjut. Kondisi ekonomi yang terhimpit tersebut akhirnya mendorong orangtua untuk menikahkan anaknya. Tidak sedikit pula anak yang akhirnya berinisiatif untuk menikah meski masih di bawah umur dengan alasan himpitan ekonomi orangtua.[8]
§ Budaya yang Menormalisasi Pernikahan Anak
Masih terdapat budaya setempat di sejumlah daerah di Indonesia yang meyakini bahwa anak, terutama anak perempuan, merupakan sebuah objek yang dimiliki orangtua. Dalam kondisi yang sudah ekstrim, keyakinan tersebut mencakup keyakinan bahwa orangtua yang menentukan kapan dan dengan siapa anaknya menikah.[9]Terdapat pula budaya di mana orangtua langsung menerima lamaran terhadap anaknya, meskipun anaknya masih di bawah umur, dengan alasan mengkhawatirkan akan masa depan anaknya yang tidak mendapat pasangan.[10]
§ Misinformasi Mengenai Indikator Kedewasaan Anak
Terdapat orangtua di Indonesia yang hanya menjadikan ajaran agama sebagai acuan untuk mengukur kedewasaan anak, terutama anak perempuan. Sering kali orangtua menganggap bahwa anaknya sudah dewasa dengan alasan sudah mengalami pubertas dan menstruasi.[11]Dari sudut pandang agama hal tersebut memang benar. Akan tetapi, indikator yang sama tidak dapat dijadikan acuan untuk menikahkan anak. Secara biologis dan mental, manusia yang masih berusia di bawah 19 tahun belum memiliki kesiapan untuk menjalankan pernikahan.
§ Pernikahan Bawah Tangan
Adanya ketentuan dalam UU bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun kerap mendorong terjadinya praktik pernikahan anak yang bersifat bawah tangan atau tidak tercatat secara hukum negara.[12]Kasus-kasus seperti ini membuat sulitnya mendeteksi praktik pernikahan anak.
[1] Ellyvon Pranita, “Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia,” Kompas, terakhir dimodifikasi 20 Mei 2021, https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all
[2] dr. Verury Verona Handayani, “Dampak Kesehatan Fisik dan Mental Pernikahan Dini bagi Remaja,” Halodoc, terakhir dimodifikasi 26 Juni 2020, https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja
[3] VOA Indonesia, “Pernikahan Anak di Seluruh Dunia: Indonesia – Rasminah,” Video YouTube, 4:52, 13 Desember 2019, https://www.youtube.com/watch?v=N6LZMAHuHeM&t=190s
[4] Narasi Newsroom, “Pernikahan Anak: “Kalau Tak Diubah, Tujur Turunan Begini Terus | Narasi Newsroom,” Video YouTube, 5:54, 20 April 2021, https://www.youtube.com/watch?v=7qJXC7tiJAc
[5] BBC News Indonesia, “Pernikahan anak di Sulawesi: "Berikan ijazah, jangan buku nikah" - BBC News Indonesia,” Video YouTube, 6:27, 25 Juli 2019, https://www.youtube.com/watch?v=kPobMk4_RjA
[6] Pemerintah Republik Indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI), https://jdihn.go.id/files/4/2019uu016.pdf
[7] Endro Priherdityo, “Pernikahan Bawah Tangan dan Manipulasi Data Usia,” CNN Indonesia, terakhir dimodifikasi 23 Juli 2016, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723080852-277-146518/pernikahan-bawah-tangan-dan-manipulasi-data-usia
[8] Narasi Newsroom, “Pernikahan Anak: “Kalau Tak Diubah, Tujur Turunan Begini Terus | Narasi Newsroom.”
[9] Ibid.
[10] BBC News Indonesia, “Pernikahan anak di Sulawesi: "Berikan ijazah, jangan buku nikah" - BBC News Indonesia.”
[11] Priherdityo, “Pernikahan Bawah Tangan dan Manipulasi Data Usia.”
[12] Ibid.
0 notes
Text
Peran Agama Mayoritas dalam Penetapan Kebijakan di Asia Selatan: Studi Kasus di Bhutan, India, dan Sri Lanka
Agama dan Politik di Asia Selatan | 26 Juni 2021
Tidak dapat dipungkiri bahwa kuatnya identitas keagamaan dapat dijadikan sebagai justifikasi pemerintah negara dalam membangun identitas nasional. Hal tersebut yang setidaknya dapat dilihat di tiga negara di Asia Selatan, yaitu Bhutan, India, dan Sri Lanka. Peran agama mayoritas dalam dinamika politik di ketiga negara tersebut sangat kuat bahkan tidak jarang mengorbankan eksistensi dan hak-hak penganut agama minoritas. Esai ini akan membahas dan membandingkan kebijakan GNH di Bhutan, UU Pencegahan atas Penyembelihan dan Pelestarian Hewan Ternak di India, dan UU Pelarangan Pemaksaan Konversi Agama yang diusung oleh JHU di Sri Lanka. Komparasi dalam esai ini berputar pada upaya mencari persamaan dan perbedaan dalam ketiga kasus tersebut.
Gross National Happiness di Bhutan
GNH atau Gross National Happiness merupakan kebijakan pemerintah di Bhutan yang digunakan sebagai parameter dalam pembangunan di Bhutan. Dalam dokumen Anggaran Nasional Bhutan untuk 1996-97, Menteri Keuangan Bhutan menyatakan bahwa “GNH telah dan akan menjadi prinsip acuan untuk strategi pembangunan berkelanjutan Bhutan” (Munro, 2016, p. 71). Kebijakan yang menganggap bahwa kebahagiaan adalah “keinginan bersama dari seluruh umat manusia dan sebaiknya menjadi fokus utama dari seluruh umat manusia” ini memiliki filosofi yang diambil dari ajaran Buddha (Givel, 2015, p. 109). Implementasi GNH dilakukan dengan menyeimbangkan kesejahteraan materiil dengan pencapaian spiritual melalui empat pillar yaitu pembangunan ekonomi yang adil, pelestarian agama dan budaya, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan pemerintahan yang baik (Givel, 2015, p. 109). Bhutan merupakan negara yang menjadikan ajaran Buddha Mahayana sebagai agama negara (Givel, 2015, p. 103) sehingga tidak menherankan apabila prinsip dan pedoman pembangunan negara dilandaskan pada ajaran agama Buddha.
Meski demikian, kebijakan GNH tidak semata-mata dibuat karena Bhutan merupakan negara agama Buddha. Adanya modernisasi dan kapitalisme global membuat Raja Jigme Singye Wangchuk berupaya untuk menyeimbangkan perubahan yang ada dengan eksistensi budaya dan pemerintahan tradisional Bhutan (Givel, 2015, p. 108). Salah satu perubahan yang dimaksud adalah meningkatnya jumlah kelompok etnoreligius Lhotshampa yang mayoritas menganut agama Hindu (Evans, 2010, p. 27). Secara etnis dan bahasa, mereka juga berbeda dengan mayoritas penduduk Bhutan. Kebijakan GNH, yang salah satunya adalah pelestarian agama dan budaya, memberikan implikasi tidak menyenangkan terhadap kelompok Lhotshampa. Hal ini juga semakin diperparah dengan pengadopsian kebijakan ‘One nation, One people’ pada 1989. Kebijakan tersebut bertujan untuk mempertahankan budaya nasional Bhutan melalui penegakan Driglam Namzha yang merupakan hukum tradisional Buddha mengenai pakaian dan etiket (Evans, 2010, p. 29). Terdapat laporan bahwa beberapa orang Lhotshampa yang tidak berpakaian sesuai pakaian nasional tidak mendapat pelayanan di rumah sakit dan terdapat penghalangan bagi orang-orang untuk menikah menggunakan pakaian tradisional Hindu (Evans, 2010, p. 29).
Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill di India
Di salah satu negara bagian di India, yaitu Karnataka, terdapat UU yang melarang secara total penyembelihan sapi. UU yang secara resmi bernama UU Pencegahan atas Penyembelihan dan Pelestarian Hewan Ternak ini disahkan pada 9 Desember 2020 silam (Arakal, 2020). Definisi dari hewan ternak dalam UU ini adalah “sapi, anak sapi dan banteng, lembu jantan, dan banteng yang berumur di bawah 13 tahun” (Ajay, 2021; Arakal, 2020). Hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelanggar UU ini adalah hukuman pidana selama 3 hingga 7 tahun dan denda sebesar 50.000 hingga 500.000 Rupee (Ajay, 2021). UU ini dirumuskan dan disahkan oleh Pemerintah Negara Bagian Karnataka yang dipimpin oleh Partai BJP (Ajay, 2021).
Di India, yang berpenduduk mayoritas beragama Hindu, kerap terjadi kasus cow vigilantes. Dalam kasus tersebut, terdapat perlakuan main hakim sendiri dengan menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang diduga menyembunyikan, mengonsumsi, dan mengangkut sapi (Harris & Thornell, 2019). Dalam salah satu video unggahan Vox bertajuk ‘India’s cow vigilantes are targeting Muslims,’ terdapat dua contoh kasus cow vigilantes yang menewaskan tiga orang. Seorang Muslim berusia 56 tahun dipukuli hingga tewas karena diduga membawa daging sapi. Dua orang pedagang hewan ternak yang membawa sapi dalam truk untuk dijual juga dipukuli bahkan digantung di pohon sehingga membuat mereka tewas. Video tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa penyembelihan sapi dilarang di sebagian besar negara-negara bagian India. Kasus cow vigilantes pun banyak terjadi di India, termasuk di negara bagian Karnataka. Dengan berlakunya UU Pencegahan atas Penyembelihan dan Pelestarian Hewan Ternak 2020 di Karnataka, pemerintah negara bagian setempat mengungkapkan bahwa kasus-kasus tuntutan terhadap cow vigilantes akan ditarik (Ani, 2021).
The Prohibition of Forcible Conversion of Religion Bill di Sri Lanka
Pada Mei 2004, sebuah partai politik baru bernama JHU di Sri Lanka mengusulkan UU baru di Parlemen Sri Lanka yang bernama UU Pelarangan Pemaksaan Konversi Agama (Hertzberg, 2016, p. 193). UU tersebut diusung dengan tujuan untuk menjawab keresahan kelompok Sinhala-Buddha atas adanya unethical conversion “oleh kelompok Kristiani evangelikal terhadap komunitas miskin Buddha dan Hindu” (Deegalle, 2004, p. 98). Unethical conversion adalah persyaratan untuk melakukan perpindahan ke agama tertentu sebagai timbal balik atas bantuan yang telah diberikan. Meskipun UU tersebut sejatinya memiliki tujuan yang baik, kontroversi dan penolakan terhadap UU yang diusulkan oleh JHU tersebut tetap tidak terhindarkan.
Kontroversi dari UU tersebut berpusat pada dua hal. Pertama, UU tersebut memiliki bahasa yang ambigu sehingga dapat membahayakan aktivitas umat Kristiani (Hertzberg, 2016, p. 194). Kedua, pernyataan dalam preambule UU tersebut tidaklah sesuai dengan pernyataan dalam Konstitusi Sri Lanka. Preambule UU menyatakan bahwa “Whereas, Buddhism being the foremost religion professed and practiced by the majority people of Sri Lanka…” sementara Pasal 9 Konstitusi Sri Lanka menyebutkan bahwa Buddhisme memiliki foremost place di Sri Lanka (Hertzberg, 2016, p. 194). Para oposisi dari UU ini berargumentasi bahwa Buddhisme sebagai dengan “foremost place” tidaklah sama dengan Buddhisme sebagai “foremost religion” (Hertzberg, 2016, p. 194). Di sisi lain, Mahkamah Agung Sri Lanka menyatakan bahwa tujuan dari UU tersebut sesuai dengan Konstitusi Sri Lanka (Hertzberg, 2016, p. 195). Meski demikian, terdapat ketidaksesuaian dari ayat-ayat dalam UU yang membuat UU ini masih belum bisa diberlakukan. Ayat 3 dan Ayat 4(b) dinyatakan melanggar Pasal 10 Konstitusi Sri Lanka oleh Mahkamah Agung sehingga bagian tersebut harus direvisi atau setidaknya dibutuhkan persetujuan dari 2/3 anggota parlemen untuk mengesahkan UU tersebut (Hertzberg, 2016, p. 195).
Analisis Komparasi Kasus
a. Persamaan antara Ketiga Kasus
Dari penjelasan singkat mengenai ketiga kasus di atas, terdapat tiga hal yang dapat dilihat dalam ketiga kasus tersebut. Pertama, terdapat identitas keagamaan tertentu yang berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas tertentu tersebut mempengaruhi kebijakan yang dirumuskan, disahkan, dan diambil dalam masing-masing negara. Dalam hal ini, terdapat agama tertentu sebagai agama mayoritas yang dianggap mencerminkan identitas nasional. Segala kebijakan negara sering kali bahkan harus dilandaskan pada ajaran agama tersebut. Di Bhutan dan Sri Lanka, identitas agama Buddha berperan dalam terbentuknya kebijakan GNH dan pengusulan UU Pelarangan Pemaksaan Konversi Agama oleh JHU. Di India, identitas agama Hindu berperan dalam perumusan dan pengesahan UU Pencegahan atas Penyembelihan dan Pelestarian Hewan Ternak di Karnataka oleh Partai BJP. Identitas agama tersebut berupaya untuk dipertahankan dan diwujudkan sedemikian rupa agar dapat menunjukkan agama tersebut sebagai identitas nasional.
Kedua, terdapat penggunaan agama sebagai alat politik. Tidak hanya identitas agama yang memiliki signifikansi, ajaran agama tersebut juga membentuk kebijakan yang diambil oleh negara. Fox (2018, pp. 53-4) mengungkapkan terdapat dua manifestasi politik dari ajaran agama. Pertama, adanya keinginan pemerintah untuk menggunakan aturan agama sebagai hukum atau kebijakan (Fox, 2018, p. 53). Hal ini dapat dilihat dalam kasus GNH di Bhutan dan UU di Karnataka, India. Kedua kebijakan tersebut secara berturut-turut didasarkan oleh ajaran agama Buddha dan keyakinan dalam agama Hindu. Kedua, adanya keinginan untuk menciptakan eksklusivitas agama dengan memberikan privilese bagi agama tertentu (Fox, 2018, p. 54). Hal ini dapat dilihat dalam kasus usulan UU oleh JHU di Sri Lanka. Buddhisme sendiri sejatinya telah memiliki posisi yang istimewa di Sri Lanka seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Konstitusi Sri Lanka. Akan tetapi, JHU berupaya untuk memperkuat privilese tersebut dan justru dapat menciptakan eksklusivitas agama dengan usulan UU Pencegahan atas Pemaksaan Konversi Agama. Upaya tersebut tampak dari preambule UU yang menyatakan bahwa Buddhisme merupakan “the foremost religion” di Sri Lanka.
Terakhir, konteks dari masing-masing kasus tersebut cenderung terjadi karena adanya sentimen terhadap kelompok agama tertentu. Di Bhutan, meskipun bukan terhadap kelompok agama tertentu secara keseluruhan, terdapat sentimen terhadap kelompok etnoreligius Lhotshampa yang mayoritas menganut agama Hindu. Kelompok Lhotshampa tentunya memiliki tradisi dan cara hidup yang berbeda dengan yang diyakini sebagai nilai utama oleh Pemerintah Bhutan. Di India, sejak lama saat masa state formation, telah terdapat sentimen dari kelompok Hindu terhadap kelompok Muslim. Sentimen tersebut masih berlangsung sampai sekarang dan terproyeksikan dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara di India, dua di antaranya berupa UU Anti-Penyembelihan di Karnataka dan kasus-kasus cow vigilantes. Sementara itu, usulan UU oleh JHU di Sri Lanka dilatarbelakangi oleh keresahan kelompok Sinhala-Buddha dan tentunya keresahan JHU sendiri, sebagai sebuah partai politik yang beranggotakan biksu-biksu Buddha, terhadap tindakan unethical conversion oleh kelompok Kristiani evangelikal.
b. Perbedaan antara Ketiga Kasus
Meski demikian, tetap terdapat tiga poin yang membedakan ketiga kasus tersebut. Pertama, terdapat perbedaan karakteristik negara. India merupakan negara yang secara konstitusional adalah negara sekular (Ahmed, 2011). Sementara itu, Konstitutsi Bhutan mengklaim Buddhisme sebagai “warisan spiritual” Bhutan (Rigyal & Prude, 2016, p. 70) dan Pasal 9 Konstitusi Sri Lanka memberikan Buddhisme “posisi utama” di Sri Lanka (Hertzberg, 2016, p. 194). Oleh karena itu, sejatinya bukan sesuatu yang mengherankan apabila dua kasus di atas terjadi di Bhutan dan Sri Lanka. Kasus di India-lah yang justru menarik untuk disorot, bagaimana bisa kelompok nasionalis yang mengatasnamakan agama tertentu begitu terakomodasi kepentingan golongannya dalam peraturan publik sebuah negara sekular? Faktor apa yang memungkinkan hal tersebut terjadi?
Kedua, masing-masing kasus tersebut mengorbankan kelompok agama yang berbeda. Kebijakan GNH dan ‘One nation, One people’ di Bhutan memberikan dampak diskriminatif terhadap kelompok agama Hindu, secara spesifik adalah kelompok etnoreligius Lhotshampa. Lain halnya dengan India, kebijakan dan UU Anti-Penyembelihan tersebut telah banyak merugikan dan memakan korban dari kelompok Muslim. Terdapat dua faktor yang memungkinkan terjadinya fenomena ini, yaitu adanya tradisi penyembelihan hewan kurban dalam agama Islam dan adanya sentimen historis kelompok Hindu terhadap kelompok Muslim. Sementara itu di Sri Lanka, UU yang diusulkan oleh JHU tersebut dapat merugikan dan memberikan implikasi yang signifikan terhadap kelompok Kristiani evangelikal. Hertzberg (2016, p. 199) secara eksplisit mengungkapkan bahwa proses birokratis dalam penyusunan UU Anti-Konversi tersebut sendiri telah mengeksklusikan kelompok Kristiani evangelikal serta hanya melibatkan kelompok Katolik dan Protestan. Menarik untuk ditelusuri lebih dalam penyebab dari dieksklusikannya kelompok Kristiani evangelikal. Apakah mungkin pengeksklusian tersebut sengaja dilakukan agar kepentingan JHU mendapat jalan yang mulus untuk terealisasi?
Kesimpulan
Sekularisasi di Asia Selatan masih sangat jauh dari kata sempurna. Alih-alih sempurna, mungkinkah sekularisasi di Asia Selatan justru hanya berjalan di tempat? Lebih jauh lagi, agama berperan signifikan dalam dinamika politik negara-negara di Asia Selatan. Dalam tiga kasus di atas, dapat dilihat bahwa agama merupakan salah satu alat politik dalam membentuk kebijakan dan diyakini merepresentasikan identitas nasional. India, yang secara konstitusional adalah negara sekular sekalipun, tidak lepas dari signifikansi peran agama dalam perpolitikannya.
Terdapat setidaknya tiga pola yang dapat ditemukan dalam agama dan politik di Asia Selatan melalui telaah tiga kasus dalam esai ini. Tiga pola tersebut yaitu: ada peran identitas keagamaan tertentu dalam pengambilan kebijakan, terdapat penggunaan agama sebagai alat politik oleh aktor politik, dan kecenderungan sentimen dari kelompok agama tertentu terhadap kelompok agama lain. Meski demikian, tetap terdapat dua poin yang membedakan tiga kasus tersebut. Dua poin yang dimaksud adalah: perbedaan karakteristik negara dan perbedaan kelompok agama yang menerima kerugian akibat dinamika politik tertentu.
REFERENSI
Ahmed, I. (2011). Secular versus Hindu nation-building: Dalit, Adivasi, Muslim and Christian experiences in India. In I. Ahmed (Eds.), The Politics of Religion in South and Southeast Asia (pp. 45-65). Routledge.
Ajay, S. (2021, 1 Januari). India state government pushes ahead with law banning cow slaughter. JURIST. https://www.jurist.org/news/2021/01/india-state-government-pushes-ahead-with-law-banning-cow-slaughter/
Ani (2021, 20 Januari). Karnataka minister says cases against 'cow vigilantes' will be withdrawn. The New Indian Express. https://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2021/jan/20/karnataka-minister-says-cases-against-cow-vigilantes-will-be-withdrawn-2252726.html
Arakal, R. A. (2020, 18 Desember). Explained: The highlights of Karnataka’s anti-cow slaughter Bill. The Indian Express. https://indianexpress.com/article/explained/explained-the-highlights-of-karnatakas-new-anti-cow-slaughter-bill-7099509/
Deegalle, M. (2004). Politics of the Jathika Hela Urumaya monks: Buddhism and ethnicity in contemporary Sri Lanka. Contemporary Buddhism 5(2), 83-103. doi: 10.1080/1463994042000319816
Evans, R. (2010). The perils of being a borderland people: on the Lhotshampas of Bhutan. Contemporary South Asia 18(1), 25-42. doi: 10.1080/09584930903561598
Fox, J. (2018). An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice (2nded.). Routledge.
Givel, M. S. (2015). GROSS NATIONAL HAPPINESS IN BHUTAN: POLITICAL INSTITUTIONS AND IMPLEMENTATION. Asian Affairs 46(1), 102-117. doi: 10.1080/03068374.2014.993179
Harris, J. & Thornell, C. (2019, 24 Juli). The violent rise of India’s cow vigilantes. Vox. https://www.vox.com/2019/7/24/20708435/cow-violence-india-muslims
Hertzberg, M. (2016). The Rhetorical Shadows of the Anti-Conversion Bill: Religious Freedom and Political Alliances in Sri Lanka. Nordic Journal of Human Rights 34(3), 189-202. doi: 10.1080/18918131.2016.1227532
Munro, L. T. (2016). WHERE DID BHUTAN'S GROSS NATIONAL HAPPINESS COME FROM? THE ORIGINS OF AN INVENTED TRADITION. Asian Affairs 47(1), 71-92. doi: 10.1080/03068374.2015.1128681
Rigyal, S. & Prude, M. A. (2016). Buddhism in Contemporary Bhutan. In M. Jerryson (Eds.), The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism (pp. 62-76). Oxford University Press. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199362387.001.0001
Vox. (2019, 24 Juli). India’s cow vigilantes are targeting Muslims [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rI_Iy1FoSn4
0 notes
Text
Menilik Pelanggaran HAM di Yaman: Intervensi Arab Saudi dalam Pendekatan Hukum Alam
Pengantar Studi HAM | 19 Juni 2021
Pada 2014, sebuah perang sipil pecah di Yaman. Perang ditandai dengan dilakukannya serangan oleh kelompok bersenjata Houthi dan pendudukan terhadap ibukota Sana’a (Hill, 2017). Perseteruan di ranah domestik Yaman tersebut kemudian bereskalasi menjadi sebuah konflik yang dipenuhi campur tangan pihak-pihak eksternal. Pada mulanya, Arab Saudi melakukan intervensi atas permintaan dari Presiden Hadi, yang kemudian mengungsikan dirinya ke Riyadh, Arab Saudi (Hill, 2017, p. 276). Serangan Arab Saudi pertama dilakukan pada Maret 2015 yang dilakukan oleh koalisinya bersama Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Maroko, Qatar, Sudan, dan Uni Emirat Arab (Hill, 2017, pp. 275-6). Serangan kedua yang dilakukan koalisi Arab Saudi pada April 2015 telah menghacurkan infrastruktur sipil Yaman yaitu jalan raya, pelabuhan, dan bandar udara (Hill, 2017, p. 276). Melihat hal tersebut, Orkaby (2017, p. 97) mengungkapkan bahwa intervensi koalisi Arab Saudi telah berubah menjadi upaya untuk menghancurkan berbagai infrastruktur ekonomi di Yaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa perang, di mana pun dan kapan pun itu, pasti membawa malapetaka. Perang tidak hanya pertikaian bersenjata antara pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga merugikan masyarakat sipil tidak bersalah yang hidup di zona perang. Kehidupan mereka menjadi terancam, tidak terkecuali penduduk Yaman.
Berangkat dari masalah tersebut, tulisan ini akan menganalisis intervensi Arab Saudi di Yaman yang menciptakan pelanggaran HAM. Persoalan tersebut menarik untuk dianalisis mengingat selama ini perhatian masyarakat internasional terhadap peran Arab Saudi dalam peperangan dan pelanggaran HAM, khususnya di Yaman, masih kurang. Analisis tulisan ini akan menggunakan pendekatan hukum alam. Menurut Dembour (2010, p. 2), sesuai dengan namanya, pendekatan ini melihat bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang absolut dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia. Donelly (2013, p. 15) mengungkapkan bahwa “hak asasi manusia bersumber dari moral alamiah manusia.” Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak yang secara alamiah, menurut hukum alam, dimiliki oleh manusia (Grotius & Tuck, 2005). Menurut Grotius & Tuck (2005) pula, hukum alam tersebut membuat setiap manusia memiliki hak otonom atas dirinya sendiri. Konsep hukum alam ini pun lebih jauh dieksplorasi dan diaplikasikan oleh Grotius & Tuck (2005, p. 189) dalam tingkat internasional yang disebutnya sebagai hukum bangsa. Dalam tingkat ini, maka setiap bangsa dan negara memiliki hak asasinya masing-masing dan otonomi atas dirinya sehingga dalam hubungan antarbangsa dan antarnegara terdapat prinsip non-intervensi.
Intervensi Militer Koalisi Arab Saudi dan Dampaknya
Bagian ini akan membahas beberapa tindakan militer menonjol yang dilakukan oleh Arab Saudi dan koalisinya dalam perang sipil di Yaman sebagai bentuk intervensi serta bagaimana serangan-serangan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat sipil di Yaman. Serangan pertama koalisi Arab Saudi dilakukan pada 26 Maret 2015 dengan sebuah operasi militer bernama Operation Decisive Storm (Hill, 2017, p. 275-6). Dalam serangan tersebut, Al-Arabiya, sebuah stasiun televisi yang berpusat di Riyadh, melaporkan bahwa Arab Saudi menurunkan 100 pesawat tempur, 150.000 orang tantara, dan sejumlah kapal perang (Wilkin, 2015). Negara-negara lain yang tergabung dalam koalisi ini juga turut menurunkan pasukan udara dan lautnya tetapi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dari yang diturunkan Arab Saudi (Wilkin, 2015). Kejadian ini meluas secara cepat karena beredarnya video-video di media sosial Twitter berisi cuplikan serangan yang dilakukan oleh koalisi Arab Saudi (Hill, 2017, p. 275). Serangan ini diklaim merupakan upaya koalisi Arab Saudi untuk menghalau serangan dan pendudukan yang dilakukan Houthi terhadap Sana’a. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa serangan menyasar pangkalan militer Al-Duleimi (“Saudi-led coalition jets hit,” 2015). Meski demikian, nyatanya serangan pesawat tempur koalisi menghantam konsentrasi pengungsi Al-Mazraq serta menyebabkan 40 orang tewas dan 200 orang mengalami luka-luka (Dearden, 2015).
Tidak cukup dengan serangan pertama, koalisi Arab Saudi kembali melancarkan operasi serangan kedua bernama Operation Renewal of Hope pada 22 April 2015 (Hill, 2017, p. 276). Hill (2017, p. 276) secara gamblang menyatakan bahwa serangan kedua ini menghasilkan kerusakan infrastruktur kehidupan yang lebih parah di Yaman. Dalam operasi militer kedua ini, koalisi Arab Saudi menjatuhkan bom ke bandar udara Yaman di Sana’a dan menghancurkan sebuah pabrik keramik di Yaman (“Yemen airport bombed,” 2015; “UK-made bomb,” 2016). Pengeboman bandar udara tersebut memiliki dampak yang lebih luas karena menyulitkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Yaman (Miles, 2015).
Pelanggaran HAM dalam Perang Sipil Yaman
Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa peperangan menimbulkan korban jiwa. Pada 2015 sendiri, PBB mengestimasikan sekitar 2.700 orang tewas dan lebih dari 5000 orang mengalami luka-luka (Hill, 2017, p. 276). Kehidupan di Yaman pun seakan perlahan mengalami kelumpuhan. Setelah sembilan bulan sejak perang dimulai, infrastruktur dasar seperti sekolah dan vaksinasi hancur serta terjadi kelangkaan bahan bakar (Hill, 2017, p. 276). Tiga tahun setelahnya, perang juga tidak kunjung mereda dan tidak memberikan penyelesaian apa-apa dari sengketa Presiden Hadi dengan Houthi. Alih-alih mereda, penduduk Yaman justru kesulitan untuk mendapatkan makan dan obat-obatan (Orkaby, 2017, p. 97). Pada 2017 juga, 7 juta orang di Yaman sulit untuk hidup dalam kemiskinan dan hampir 2 juta anak di Yaman mengalami malnutrisi (Orkaby, 2017, p. 97). Kolera juga menjangkiti lebih dari 600.000 orang dan menewaskan lebih dari 2000 orang (Orkaby, 2017, p. 98). Terjadinya perang di Yaman telah membuat Yaman berkali-kali diklaim sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia seperti oleh UNHCR, UNICEF, dan UN WFP.
Jika merujuk pada hukum internasional yaitu International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), terdapat hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun atau non-derogable rights. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk tidak ditahan karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk bebas dari hukum retrospektif, dan hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Dalam kasus di Yaman, pelangaran HAM yang terjadi adalah pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dikurangi berupa hak untuk hidup. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya korban jiwa akibat perang dan terancamnya kehidupan penduduk Yaman secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam ICCPR, “tidak ada seorang pun yang boleh dicabut haknya untuk hidup secara arbiter.” Kondisi di Yaman tentu tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Lebih lanjut lagi, upaya untuk mempertahankan dan mendukung kelangsungan hidup penduduk terdampak perang di Yaman melalui pemberian bantuan kemanusiaan justru menjadi terhambat karena pengeboman bandar udara Yaman dan blokade oleh Angkatan Laut Arab Saudi (Borger, 2015; Miles, 2015).
Selain itu, hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus ini adalah hak negatif atau negative rights. Hak negatif sendiri adalah hak yang ‘menahan’ tindakan-tindakan yang dapat merebut sesuatu dari manusia (Fried, 1978, p. 139). Hak negatif akan terpenuhi apabila duty bearer, dalam hal ini adalah negara, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar pemenuhan hak tersebut. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa tindakan pemerintah negara, dalam hal ini adalah Presiden Hadi, mengakibatkan terlanggarnya hak negatif penduduk Yaman. Tindakan Presiden Hadi tersebut membuat penduduk Yaman kehilangan haknya untuk dapat hidup dengan aman.
Analisis Pelanggaran HAM menurut Pendekatan Hukum Alam
Untuk meninjau pelanggaran HAM di Yaman, kita perlu melihat awal mula terjadinya perang. Serangan dan ‘pemberontakan’ yang dilakukan oleh kelompok Houthi dipicu oleh adanya kegagalan produksi minyak, lemahnya institusi pemerintahan, korupsi, dan kompetisi antarelit (Hill, 2017). Seperti yang telah disampaikan di awal bahwa Presiden Hadi meminta Arab Saudi untuk melakukan intervensi dan meninggalkan Yaman. Tindakan Presiden Hadi ini menunjukkan kegagalannya sebagai pemimpin negara, khususnya sebagai duty bearer, dalam penegakkan HAM. Presiden Hadi seolah-olah lepas tangan dari sengketa pemerintah dengan kelompok Houthi. Pelepasan tanggung jawab tersebut telah membuat adanya perusakan moral karena terjadi pelanggaran HAM di Yaman. Hak asasi manusia yang secara fundamental berkaitan erat dengan moral tidak dapat dipenuhi sejak kasus ini bermula.
Terjadinya pelanggaran HAM kemudian juga semakin diperkuat dengan adanya intervensi Arab Saudi. Intervensi tersebut tidak mampu menyelesaikan sengketa antara Presiden Hadi dengan kelompok Houthi secara baik dan damai. Premis ini terbukti dengan perang yang masih berlangsung hingga sekarang. Intervensi tersebut juga tidaklah sah apabila ditinjau dari hukum internasional dan secara jelas melanggar prinsip non-intervensi yang diusung pertama kali oleh Hugo Grotius. Meskipun intervensi terjadi atas permintaan dari Presiden Hadi, terdapat empat poin problematis mengenai tindakan Presiden Hadi dan intervensi Arab Saudi.
Pertama, permintaan Presiden Hadi tersebut problematis karena intervensi yang diminta sejatinya bukan merupakan upaya perlindungan diri. Dalam kasus ini, intervensi justru diminta saat awal terjadinya perang sipil, yang pada dasarnya merupakan perang antara sesama warga negara Yaman (Ruys & Ferro, 2016, p. 73). Intervensi tidak dilakukan atas dasar perlindungan dan pertahanan otonomi Yaman dari ancaman luar. Kedua, tindakan Presiden Hadi tersebut justru melanggar hak penduduk Yaman untuk menentukan nasib sendiri. Lebih lanjut lagi, intervensi Arab Saudi pun turut melanggengkan pelanggaran ini. Alih-alih mendorong resolusi konflik, intervensi tersebut malah menciptakan krisis kemanusiaan di Yaman. Apabila dikaitkan pada hal fundamental mengenai hak asasi manusia, permintaan Presiden Hadi dan intervensi Arab Saudi justru bertentangan dengan prinsip jus cogens. Dikutip dari Hossain (2005), jus cogens merupakan norma dengan superioritas dalam hukum internasional yang menekankan bahwa tindakan negara atau komunitas internasional lainnya harus menghormati hak-hak yang tidak dapat dikurangi. Norma ini menyebutkan bahwa negara tidak secara mutlak bebas dalam membangun hubungan terutama yang bersifat kontraktual (Hossain, 2005, p. 73).
Ketiga, masih berkaitan dengan poin kedua—intervensi yang dilakukan Arab Saudi tidaklah sah menurut hukum humaniter internasional. Pasal 33 dari Piagam PBB menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa, negara tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas. Negara harus melakukan upaya-upaya diplomatik secara damai terlebih dahulu. Dengan mempertimbangkan tindakan yang telah dilakukan Houthi di Yaman sebelum intervensi Arab Saudi, intervensi tersebut bukanlah suatu keharusan. Kembali merujuk pada prinsip jus cogens, intervensi dalam upaya resolusi konflik baru disebut sah apabila terdapat setidaknya salah satu dari empat kondisi berikut: genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Definisi, kondisi, dan elemen dari keempat hal tersebut secara lebih lanjut dijelaskan dalam Statuta Roma. Ketika Arab Saudi melancarkan serangannya di Yaman, tidak ada satu pun dari keempat hal tersebut yang terjadi di Yaman.
Terakhir, intervensi Arab Saudi di Yaman merupakan salah satu agenda politik Arab Saudi. Arab Saudi dan Presiden Hadi menuding bahwa Houthi merupakan boneka dari Iran. Tudingan tersebut kemudian dijadikan salah satu justifikasi intervensi Arab Saudi. Akan tetapi pada kenyataannya, intervensi yang dilakukan justru membuat Arab Saudi menjadikan Yaman sebagai arena peperangan untuk melawan pihak yang dianggap musuhnya, yakni Iran. Selain itu, Ruys & Ferro (2016, pp. 76-7) bahwa intervensi yang dilakukan Iran hanyalah berupa pemberian bantuan logistik dan tidak mencakup penentuan agenda serangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa intervensi Arab Saudi di Yaman tidak sebanding dengan intervensi yang dilakukan Iran dan—yang paling penting—justru menciptakan krisis kemanusiaan di Yaman atas nama pemenuhan kepentingan politik.
Kesimpulan
Intervensi Arab Saudi atas permintaan Presiden Hadi merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral kehidupan manusia. Pertentangan ini menciptakan pelanggaran HAM berupa pelanggaran hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dan pelanggaran hak negatif. Tindakan Presiden Hadi yang meminta intervensi dari Arab Saudi dan kemudian malah meninggalkan Yaman menunjukkan bahwa tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara tidak dipenuhi. Intervensi yang mulanya ditujukan untuk menghalau pemberontakan kelompok Houthi juga terbukti masih belum mampu menyelesaikan persoalan tersebut bahkan hingga saat ini. Terlebih lagi dengan adanya langkah-langkah—baik disengaja maupun tidak—oleh koalisi Arab Saudi yang menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan. Sejatinya pun, jika ditinjau dari hukum internasional, intervensi tersebut juga tidak memiliki justifikasi legal yang sah dan kuat. Hal ini semakin melemahkan permintaan Presiden Hadi dan intervensi Arab Saudi dan menguatkan perusakan moral yang dilakukan oleh Presiden Hadi dan koalisi Arab Saudi di Yaman. Sebagai pemimpin negara, seharusnya Presiden Hadi tidak meninggalkan Yaman dan tidak meminta intervensi yang begitu ekstensif dari Arab Saudi. Dengan demikian, pelanggaran HAM di Yaman dapat terhindarkan.
REFERENSI
Borger, J. (2015, 5 Juni). Saudi-led naval blockade leaves 20m Yemenis facing humanitarian disaster. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/saudi-led-naval-blockade-worsens-yemen-humanitarian-disaster
Dearden, L. (2015, 31 Maret). Saudi Arabia accused of killing 40 including children in air strike on Yemen refugee camp. The Independent. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-accused-killing-40-including-children-air-strike-yemen-refugee-camp-10145294.html
Dembour, M. (2010). What are human rights? Four schools of thought. Human Rights Quarterly, 32(1), 1-20. http://www.jstor.org/stable/40390000
Fried, C. (1978). Right and wrong. Harvard University Press.
Grotius, H. & Tuck, R. (Eds.). (2005). The rights of war and peace (Vol. 1). Natural Law and Enlightment Series. Liberty Fund.
Hill, G. (2017). Yemen endures: Civil war, Saudi adventurism, and the future of Arabia. Oxford University Press.
Hossain, K. (2005). The concept of Jus Cogens and the obligation under the U.N. Charter. Santa Clara Journal of International Law, 3(1), 72-98. http://digitalcommons.law.scu.edu/scujil/vol3/iss1/3
International Criminal Court. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. International Criminal Court.
Miles, T. (2015, 5 Mei). UN urges Saudi-led coalition to stop targeting Yemen airport. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-humanitarian/un-urges-saudi-led-coalition-to-stop-targeting-yemen-airport-idUSKBN0NP1VJ20150504
Orkaby, A. (2017). Yemen's umanitarian nihghtmare: The real roots of the conflict. Foreign Affairs, 96(6), 93-101. https://www.jstor.org/stable/44823824
Ruys, T. & Ferro, L. (2016). WEATHERING THE STORM: LEGALITY AND LEGAL IMPLICATIONS OF THE SAUDI-LED MILITARY INTERVENTION IN YEMEN. International and Comparative Law Quarterly, 65(01), 61–98. doi:10.1017/s0020589315000536
(2015, 26 Maret). Saudi-led coalition jets hit Houthi targets in Yemen for second night. Al Jazeera America. http://america.aljazeera.com/articles/2015/3/26/Saudi-airstrikes-yemen.html
United Nations. (1996). International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations General Assembly.
Wilkin, S. (2015, 26 Maret). Factbox - Saudi Arabia's coalition against Yemen's Houthis. Reuters. https://www.reuters.com/article/yemen-security-coalition/factbox-saudi-arabias-coalition-against-yemens-houthis-idINKBN0MM1AH20150326
(2015, 29 April). Yemen airport bombed. Reuters. https://www.reuters.com/news/picture/yemen-airport-bombed-idUSRTX1ATMJ
0 notes
Text
Tantangan dalam Mewujudkan Dunia Tanpa Senjata Nuklir
Studi Keamanan Internasional | 21 Juni 2021
Dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada periode Perang Dunia II telah menunjukkan kepada dunia betapa mematikan dampak dari senjata nuklir. Moran (2015, pp. 120-1) menjelaskan bahwa senjata nuklir dapat menghancurkan sistem dan perangkat elektronik yang tidak terlindungi, dapat menyebabkan kebutaan, kulit terbakar, dan menciptakan api, dapat berdampak pada hingga 50% populasi dalam radius 5 mil, dan menghasilkan radiasi nuklir. Meskipun telah terbukti bahwa senjata nuklir sangat berbahaya dan mematikan bagi kehidupan umat manusia, perwujudan dunia tanpa senjata nuklir masih sulit untuk dilakukan. Berangkat dari problematisasi tersebut, tulisan ini akan mengupas penyebab-penyebab sulitnya mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
Robinson (2015) mengungkapkan bahwa definisi dari proliferasi nuklir tidaklah jelas, dalam artian bahwa tidak ada definisi yang konsisten dan diakui secara universal di seluruh dunia. Beliau lebih lanjut lagi menyatakan bahwa definisi tersebut secara inheren bersifat subjektif sehingga menjadi rentan untuk dipolitisasi, khususnya oleh negara-negara pemilik senjata nuklir. Politisasi dilakukan sebagai upaya salah satu upaya pertahanan diri negara. Robinson (2015, p. 65) menggunakan contoh pemberian sanksi ekonomi oleh AS kepada India atas percobaan nuklir pada 1998. Uniknya, meskipun Perancis dan Rusia sama-sama mengecam percobaan yang dilakukan India, keduanya tidak memberi hukuman apapun (Robinson, 2015, p. 66). Hal ini menunjukkan bahwa kriteria proliferasi nuklir yang dimiliki oleh AS berbeda dengan yang dimiliki oleh Perancis dan Rusia (Robinson, 2015, p. 66). Perbedaan kriteria tersebut ironis karena telah ada dua rezim non-proliferasi nuklir yakni Traktat Non-Proliferasi (NPT) pada 1968 dan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) pada 2017. NPT—yang membatasi kepemilikan senjata nuklir—mendefinsikan proliferasi sebagai pemberian oleh negara pemilik senjata nuklir dan penerimaan oleh negara yang bukan pemiliki senjata nuklir, dalam bentuk berikut: senjata nuklir, mesin peledak, bantuan pengembangan senjata nuklir, dan hal-hal lain yang mendorong kepemilikan senjata nuklir. Sementara itu, TPNW secara lebih eksplisit melarang alih-alih hanya melarang kepemilikan senjata nuklir. Ironisnya, dengan merujuk pada situs ICAN, negara pemilik senjata nuklir tidak banyak terlibat dalam inisiasi TPNW. Fakta tersebut menunjukkan bahwa negara pemilik senjata nuklir memiliki kriteria dan definisi proliferasi nuklir yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam TPNW.
Secara substantif, NPT dan TPNW juga memiliki celah. Keduanya hanya mencakup proliferasi nuklir secara horizontal tetapi tidak secara vertikal. Yang dimaksud sebagai proliferasi horizontal adalah “the spread of nuclear weapons to non-nuclear weapons states or acquisition of capability to make nuclear weapons by such” (Bajja, 1997, p. 48). Sementara itu, proliferasi vertikal adalah “an increase in the numbers and types of nuclear weapons in the arsenal of nuclear weapon states” (Bajja, 1997, p. 48). Cakupan yang terbatas pada proliferasi horizontal dari kedua traktat tersebut dapat dilihat dengan merujuk pada Pasal 1 s.d. 3 dari NPT dan Pasal 1 dari TPNW. Dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa pembatasan dan pelarangan yang diatur hanya berupa penyebaran kepemilikan senjata nuklir. Tidak adanya rezim yang mengatur proliferasi vertikal membuat tujuan untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir menjadi mustahil. Tanpa regulasi mengenai proliferasi nuklir, negara-negara yang sudah memiliki senjata nuklir tetap dapat menambah jumlah dan tipe senjata nuklir mereka.
Ketetapan untuk melaporkan aktivitas pengembangan nuklir secara keseluruhan juga masih belum mampu mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir. Merujuk pada Pasal 3 NPT, negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir wajib melaporkan setiap aktivitas tenaga nuklir mereka sesuai dengan ketentuan IAEA. Akan tetapi pada faktanya, transparansi masih menjadi batu sandungan dalam hal ini. Nguyen & Yim (2017, p. 512) menggunakan Korea Selatan—yang tidak melaporkan keseluruhan aktivitas nuklirnya—dan Iran—yang diduga memberi laporan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Selain persoalan transparansi, NPT juga tidak mewajibkan negara-negara pemilik senjata nuklir untuk membuat laporan. Laporan yang mereka buat sendiri pun berbeda dengan ketentuan IAEA, bahkan terdapat perbedaan di antara mereka mengenai isi dari laporan mereka (Siegel, 2015, pp. 7-8).
Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa perwujudan dunia tanpa senjata nuklir dikendalai oleh tiga hal. Pertama, tidak ada definisi yang konsisten dan diakui secara universal mengenai proliferasi nuklir. Kedua, masih terdapat celah dalam dua rezim non-proliferasi nuklir saat ini. Ketiga, persoalan transparansi dan ketimpangan dalam pelaporan aktivitas nuklir. Tiga hal tersebut dapat dikerucutkan kembali menjadi dua, yaitu adanya dilema keamanan dan kebijakan rezim non-proliferasi nuklir yang belum komprehensif. Evaluasi dan perbaikan terhadap rezim non-proliferasi nuklir dapat menjadi salah satu solusi dari masalah-masalah tersebut demi mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
REFERENSI
Bajja, D. S. (1997). The Concept of Nuclear Proliferation : Need For Reconsideration. Indian Journal of Asian Affairs 10(1). 47-50. https://www.jstor.org/stable/41950402
ICAN. (n.d.). The road to a world free of nuclear weapons. https://www.icanw.org/history_of_the_tpnw
Moran, A. (2015). Nuclear proliferation. In P. Hough, S. Malik, A. Moran, & B. Pilbeam (Eds.), International security studies: Theory and practice (pp. 119-132). Routledge.
Nguyen, V. P., & Yim, M. S. (2017). Building trust in nonproliferation: transparency in nuclear-power development. The Nonproliferation Review, 24(5-6), 509-526. https://doi.org/10.1080/10736700.2018.1448036
Robinson, T. C. (2015). What Do We Mean by Nuclear Proliferation?. The Nonproliferation Review 22(1). 53-70. https://doi.org/10.1080/10736700.2015.1070048
Siegel, J. (2015). (Rep.) Expanding Nuclear Weapons State Transparency to Strengthen Nonproliferation. Center for International & Security Studies, U. Maryland. https://www.jstor.org/stable/resrep05006
United Nations. (n.d.). Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
United Nations. (2017). Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. https://treaties.un.org/doc/Treaties/2017/07/20170707%2003-42%20PM/Ch_XXVI_9.pdf
0 notes
Text
Pluralisme dan Kebenaran dalam HI: Fenomena Persaingan AS-Tiongkok melalui Perspektif Liberalisme dan Perspektif Konstruktivisme
Teori-Teori Hubungan Internasional (Lanjutan) | 29 Juni 2021
Dinamika hubungan internasional saat ini kerap diwarnai oleh persaingan dan rivalitas antara dua negara besar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan dan rivalitas antara keduanya dapat ditemui dalam berbagai aspek hubungan internasional hingga tidak jarang bersinggungan dengan dinamika politik kawasan tertentu dan politik luar negeri negara tertentu. Sebagaimana disiplin ilmu hubungan internasional tidak memiliki kebenaran tunggal, fenomena persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat dilihat melalui berbagai kacamata hubungan internasional. Perspektif yang berbeda akan memandang fenomena tersebut dengan cara dan pola pikir yang berbeda pula. Esai ini akan mengulas persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok melalui dua perspektif hubungan internasional yang memiliki posisi berbeda, yakni liberalisme pada spektrum positivisme dan konstruktivisme pada spektrum interpretivisme.
Liberalisme merupakan perspektif yang tertarik untuk menjelaskan bagaimana dan dalam kondisi yang seperti apa kerja sama internasional dapat terjadi (Viotti & Kauppi, 2012, p. 129). Menurut liberalisme, terdapat interdependensi dan keterikatan erat antara seluruh aktor hubungan internasional, baik aktor negara maupun non-negara, yang dinilai dapat membantu memoderasi perilaku negara (Viotti & Kauppi, 2012, p. 130). Interdependensi dan keterikatan tersebut membuat tindakan negara yang berdampak pada putusnya hubungan antarnegara seperti kompetisi, perang, dan konflik lainnya menjadi sangat mahal dan membutuhkan pengorbanan yang besar. Oleh karena itu, liberalisme memandang bahwa menginisiasi dan mempertahankan kerja sama sangatlah penting. Isu-isu yang dianggap penting dan relevan bagi liberalisme juga mencakup isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Viotti & Kauppi, 2012, p. 130).
Dilansir dari situs United States Trade Representative, Tiongkok merupakan mitra dagang barang terbesar ketiga bagi Amerika Serikat pada 2019. Tiongkok juga merupakan pasar ekspor barang terbesar ketiga dan penyuplai impor barang terbesar AS pada 2019. Lau (2019, p. 352) pun menyebutkan bahwa AS dan Tiongkok memiliki potensi keuntungan yang besar melalui kerja sama dagang dan investasi karena perbedaan ekonomi keduanya yang cukup signifikan. Tiongkok memiliki jumlah populasi empat kali lebih besar dari AS, memiliki rasio tabungan yang tinggi, dan tabungan yang melebihi investasi domestik dibandingkan AS (Lau, 2019, p. 352). Di sisi yang lain, AS memiliki tanah yang lebih subur, stok modal saham berwujud lebih banyak, sumber daya alam lebih banyak, dan memiliki stok modal riset dan pengembangan empat kali lebih banyak dari Tiongkok (Lau, 2019, p. 352). AS dan Tiongkok juga memiliki interdependensi, berupa peran yang sama penting, dalam hal menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Dalam hal hubungan AS-Tiongkok, liberalisme memandang bahwa rivalitas bukan jalan terbaik bagi masing-masing negara. Kedua negara seharusnya dapat dengan sedemikian rupa menjaga hubungan dan meningkatkan kerja sama yang telah dibangun. Upaya ini penting untuk dilakukan mengingat interdependensi yang ada antara AS dan Tiongkok. Dengan melihat dinamika persaingan dan tensi antara keduanya sampai saat ini, liberalisme menilai bahwa AS dan Tiongkok harus memikirkan kembali pendekatan yang digunakan terhadap satu sama lain. Hal ini khususnya penting untuk diperhatikan oleh AS, mengingat selama ini AS selalu memiliki prasangka buruk terhadap Tiongkok dan berupaya untuk mengeksklusikan Tiongkok dari sistem global yang ada. Kerja sama menjadi opsi yang lebih murah untuk direalisasikan karena pada faktanya saat ini pun Tiongkok berada dalam berbagai institusi internasional yang sama dengan AS seperti PBB, WTO, IMF, dan Perjanjian Iklim Paris. Keanggotaan kedua negara dalam institusi-institusi tersebut membuat perilaku kecurangan menjadi sesuatu yang mahal ongkosnya untuk ditempuh. Berbagai institusi internasional tersebut seharusnya bisa dijadikan sarana komunikasi oleh AS dan Tiongkok untuk meminimalisir dilema sosial antara keduanya. Dengan demikian, kepentingan bersama dalam jangka panjang dapat diprioritaskan atas kepentingan individu dalam jangka pendek.
Di sisi lain, konstruktivisme tidak melihat fenomena, struktur, dan aktor dalam hubungan internasional apa adanya. Alih-alih demikian, konstruktivisme meyakini bahwa realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial. Konstruksi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor ideasional seperti norma, peraturan, dan hukum (Viotti & Kauppi, 2012, p. 278). Struktur sosial yang berisi faktor-faktor ideasional tersebut kemudian mempengaruhi identitas dan kepentingan aktor (Viotti & Kauppi, 2012, p. 278). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepentingan aktor erat kaitannya dengan nilai, norma, dan gagasan yang dimiliki dan diyakini oleh aktor. Sebagai agen dalam struktur dan interaksi sosial, aktor selalu berusaha untuk merealisasikan nilai, norma, dan gagasannya tersebut melalui berbagai tindakan. Dalam konteks hubungan internasional, tidak jarang tindakan tersebut berupa kebijakan. Oleh karena itu, konstruktivisme selalu berusaha membongkar fenomena-fenomena dalam hubungan internasional dengan melihat peran dari nilai, norma, gagasan, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor.
Dalam melihat fenomena persaingan AS dan Tiongkok, konstruktivisme menilai bahwa persaingan tersebut disebabkan oleh adanya konstruksi musuh yang dibangun oleh AS mengenai Tiongkok. Konsekuensinya, AS melihat bertambahnya kekuatan ekonomi dan menguatnya peran Tiongkok dalam hubungan internasional sebagai ancaman. Konstruksi musuh yang dibangun AS lebih lanjut lagi berakar pada adanya perbedaan identitas antara AS dan Tiongkok. AS, yang selama ini mendominasi dinamika hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dingin, merupakan negara dengan identitas dan peradaban Barat. Sementara itu, Tiongkok memiliki identitas dan peradabannya sendiri berupa peradaban Tionghoa. Perbedaan identitas dan peradaban tentu berarti adanya perbedaan nilai pula. Presiden Biden pernah menyampaikan dalam pidatonya bahwa “Presiden Xi Jinping menganggap bahwa demokrasi tidak bisa berkompetisi dalam abad ke-21” (Campbell, 2021). Pernyataan tersebut secara implisit mengungkapkan garis ‘kami versus mereka’ karena AS memandang Tiongkok sebagai bagian dari negara yang tidak demokratis. Di sisi lain, Tiongkok selalu mengklaim bahwa negaranya adalah negara yang demokratis, hanya saja dengan caranya sendiri (Campbell, 2021; Lanteigne, 2020, p. 12). Perbedaan nilai inilah yang membuat AS memandang Tiongkok sebagai musuh sehingga tercipta kompetisi, rivalitas, dan pertentangan antara keduanya. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pun menyatakan bahwa “kuncinya terletak pada penerimaan AS atas kebangkitan yang damai dari negara besar dengan sistem sosial, sejarah, dan budaya yang berbeda” (Campbell, 2021).
Pertentangan yang berakar pada perbedaan identitas dan peradaban pun merupakan sebuah fenomena yang pernah ditulis oleh Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul ‘The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.’ Persaingan dan tensi antara kedua negara ini sejatinya merupakan implikasi dari upaya kedua pihak dalam merealisasikan nilai-nilai yang diyakini. AS dengan ideologi liberalismenya sangat menghargai nilai-nilai demokrasi, kebebasan individu, dan hak asasi manusia. Huntington (1996, pp. 183-4) mengungkapkan bahwa “negara-negara Barat, terutama AS, … meyakini bahwa orang-orang non-Barat sebaiknya mengkomitmenkan diri mereka dengan nilai-nilai Barat…” Keyakinan tersebut membuat AS, yang selama ini nilai-nilai Baratnya menjadi hegemon tunggal dunia, merasa terancam tatkala terdapat kekuatan baru dengan identitas non-Barat yang muncul dalam hubungan internasional. Secara spesifik, AS mengkhawatirkan bertambahnya kekuatan Tiongkok akan mengubah sistem internasional yang telah ada. Di sisi lain, Tiongkok hanya melakukan kebijakan luar negeri selayaknya negara lain dan tentu dengan nilai-nilai yang diyakininya berupa peradaban Tionghoa dan ideologi komunisme. Tiongkok menggunakan persepsi dirinya sebagai ‘pusat peradaban’ yang secara historis telah banyak menjalin hubungan tributary dengan tetangga-tetangganya (Breslin, 2010, p. 51) sebagai justifikasi kebijakan luar negerinya saat ini. Tiongkok mengklaim bahwa berbagai kebijakan luar negerinya saat ini adalah sebuah ‘sebuah kebangkitan yang damai’ setelah mengalami ‘abad penghinaan’ (Breslin, 2010). Oleh karena itu, ketika Tiongkok merasa bahwa nilai dan tindakannya terusik oleh upaya AS dalam menyebarkan nilai-nilai Barat, Tiongkok pun berupaya untuk menghalau tindakan AS tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dalam dokumen China’s Military Strategy yang dirilis pada Mei 2015 bahwa “kami tidak akan menyerang kecuali kami diserang, tapi kami tentu akan melakukan serangan balik jika diserang” (Lanteigne, 2020, p. 119). Akibatnya terciptalah persaingan dan rivalitas antara kedua negara tersebut.
Dari perbandingan yang telah disampaikan di atas, terdapat dua perbedaan kontras antara perspektif dalam kelompok positivisme dengan perspektif dalam kelompok interpretivisme. Esai ini telah menyajikan analisis perbandingan antara dua kelompok perspektif tersebut dengan menggunakan perspektif liberalisme dan perspektif konstruktivisme untuk menelaah fenomena meningkatnya persaingan tensi antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam hubungan internasional. Analisis menunjukkan bahwa perspektif liberalisme melihat realitas sosial melalui simplifikasi dan generalisasi untuk menemukan pola serta terbatas pada aspek-aspek materiil. Dari proses tersebut, pola yang didapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya suatu fenomena sosial dalam hubungan internasional. Perspektif ini juga berusaha untuk memberikan resep dalam menyelesaikan persoalan. Liberalisme memandang persaingan antara AS dan Tiongkok sebagai suatu pola yang harus dimitigasi dengan meningkatkan kerja sama dan komunikasi melalui forum dan institusi internasional yang sudah ada. Di sisi lain, perspektif konstruktivisme melihat bahwa realitas sosial adalah hasil konstruksi sosial oleh agen yang kemudian memberi makna atas berbagai objek dan aktor lain dalam kehidupan. Cara pandang yang berfokus pada aspek-aspek ideasional ini membuat konstruktivisme berusaha untuk memahami fenomena dengan membongkar makna yang sejatinya menyelubungi fenomena tersebut. Perspektif ini berargumentasi bahwa persaingan antara AS dan Tiongkok sejatinya dipengaruhi oleh adanya pertentangan identitas, nilai, dan norma.
Melalui tulisan ini, dapat dipahami pula bahwa kebenaran dalam hubungan internasional tidaklah mutlak. Kebenaran bergantung pada perspektif apa yang digunakan dalam melihat fenomena tertentu. Satu fenomena dapat dilihat dengan berbagai perspektif. Seperti yang telah disampaikan dalam esai ini, fenomena persaingan AS dan Tiongkok dapat dilihat baik menggunakan perspektif liberalisme maupun dengan perspektif konstruktivisme. Perbedaan perspektif tentunya menentukan kebenaran apa yang dilihat dan diyakini sebagai realitas sosial. Akhir kata, penting bagi pembelajar hubungan internasional untuk menerima dan memahami dengan baik keragaman dalam studi hubungan internasional.
REFERENSI
Breslin, S. (2010). Handbook of China’s international relations. Routledge.
Campbell, C. (2021, 29 April). In His Speech to Congress, Joe Biden Sets Out a Vision for ‘Competition, Not Conflict’ With China. Time. https://time.com/5995109/biden-congress-speech-china/
Huntington, S. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon & Schuster.
Lanteigne, M. (2020). Chinese foreign policy: An introduction (4th ed.). Routledge.
The People’s Republic of China. (t. t.). Office of the United States Trade Representative. https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china
UNTC. (t. t.). United Nations Treaty Collection. https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/XXVII-7-d.en.pdf
0 notes
Text
Tinjauan: Konseptualisasi Keamanan oleh Perspektif Positivisme
Teori-Teori Hubungan Internasional (Lanjutan) | 23 Mei 2021
Tulisan ini merupakan tinjauan dari tulisan David Baldwin (1997) yang berjudul “The Concept of Security.”
Keamanan merupakan isu yang tidak pernah terlepaskan dalam studi HI. Baik itu keamanan bagi dunia, bagi kawasan, bagi negara, maupun bagi individu. Studi HI pun pertama kali lahir dengan berfokus pada pencapaian keamanan dunia dengan mencegah terjadinya kembali perang. Meski sering mewarnai diskursus dalam studi HI, keamanan dalam HI sendiri belum memiliki konsep yang jelas. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi David Baldwin untuk menulis ‘The concept of security.’ Dalam tulisan tersebut, Baldwin (1997) mengkritisi literatur-literatur yang telah ada dalam mendefinisikan keamanan. Menurutnya, literatur yang ada masih terlalu berfokus pada hal “apa yang harus dilindungi dan bentuk ancaman yang mungkin terjadi” dan “masih kurang dalam aspek konseptual” (Baldwin, 1997, p. 5) padahal adanya konsep yang jelas dari keamanan sangatlah penting. Tanpa adanya konsep keamanan, kita tidak dapat mengetahui jika kita berada dalam kondisi yang terancam (Baldwin, 1997, p. 8). Baldwin menjelaskan bahwa perumusan konsep keamanan yang jelas memiliki urgensi yang didasari oleh tiga alasan: menjawab pertanyaan dasar dari ilmu sosial, “of what is this an instance?”, mendorong analisis kebijakan yang rasional melalui komparasi berbagai macam kebijakan keamanan, dan menciptakan common ground antara pandangan-pandangan yang berbeda (Baldwin, 1997, pp. 5-4). Selain itu, Baldwin juga mengutip Wolfers (1952, p. 483) bahwa tidak adanya spesifikasi dari konsep keamanan dapat menciptakan kekeliruan karena bersifat ambigu (Baldwin, 1997, p. 6).
Baldwin mengkritisi pendapat bahwa keamanan adalah konsep yang dikontestasi (Baldwin, 1997, p. 10). Kontestasi konsep menurutnya tidak menjadi penghalang dalam merumuskan konsep yang jelas dari keamanan (Baldwin, 1997, p. 12). Dalam menunjukkan komitmennya terhadap kritik tersebut, ia kemudian merumuskan konsep keamanan dengan berangkat dari karakteristik keamanan yang diusung oleh Wolfers (1952, p. 485), yakni “absennya ancaman terhadap nilai-nilai yang dimiliki” (Baldwin, 1997, p. 13). Dari karakteristik tersebut, konsep keamanan yang dirumuskan oleh Baldwin adalah “memelihara nilai-nilai yang dimiliki” (Baldwin, 1997, p. 13). Lebih lanjut lagi, keamanan dapat didefinisikan dengan menspesifikasi beberapa hal yaitu: “keamanan untuk siapa?”, “keamanan untuk nilai yang mana?”, “seberapa banyak keamanan yang dibutuhkan?”, “dari ancaman apa?”, “melalui cara apa?”, “dengan mengorbankan apa?”, dan “dalam periode waktu apa?” (Baldwin, 1997, pp. 13-17). Singkatnya, definisi dari keamanan dapat diperoleh dengan menspesifikasi sejelas mungkin aspek-aspek yang meliputi keamanan.
Dari substansi yang disampaikan dalam tulisannya, dapat dilihat bahwa Baldwin berada di posisi positivisme dalam teori HI. Posisi ini dapat dilihat secara nyata dari upaya Baldwin untuk mencari definisi tunggal dari suatu konsep yakni keamanan. Meskipun penting untuk memiliki definisi jelas dari suatu konsep, definisi yang ditawarkan Baldwin tidaklah memberi ruang bagi kemungkinan adanya definisi lain dari sudut pandang lain mengenai konsep keamanan. Bahkan upaya untuk menutup kemungkinan bagi berbagai definisi pun tampak dari pernyataan Baldwin bahwa pasti terdapat dasar yang sama dari semua konsep-konsep yang dikontestasikan (Baldwin, 1997, p. 12). Lebih lanjut lagi, Baldwin tidak memperhatikan dan tidak mempertanyakan bagaimana konsep keamanan tersebut bisa diperoleh. Selain itu, Baldwin mengungkapkan bahwa konsep keamanan berbeda secara fundamental dari kondisi spesifik di mana keamanan dapat dicapai (Baldwin, 1997, p. 8). Hal ini menunjukkan sifat positivisme karena mengabaikan keberhasilan implementasi keamanan dalam konseptualisasinya. Pernyataan tersebut juga semakin membuktikan posisi positivis dari tulisan Baldwin karena menunjukkan upaya generalisasi dalam menyusun konsep keamanan. Dengan mengabaikan kondisi-kondisi spesifik dalam implementasi keamanan, Baldwin memiliki asumsi bahwa konsepnya dapat berlaku kapan saja, di mana, dan dalam konteks apa pun.
Berikutnya, posisi positivisme Baldwin dapat dilihat dari pengadopsian kriteria dalam menjelaskan konsep dari Oppenheim yang salah satunya menarik untuk disorot. Kriteria tersebut adalah bahwa “konsep sebaiknya dapat digunakan dalam cara yang sangat luas” (Baldwin, 1997, p. 3). Penyusunan konsep secara luas ini merupakan ciri khas dari positivisme yang dimaksudkan agar konsep tersebut dapat berlaku lintas spasial dan temporal. Terakhir, posisi positivisme Baldwin juga ditunjukkan dari caranya dalam menyusun definisi keamanan. Baldwin menggunakan indikator-indikator (Baldwin, 1997, pp. 13-17) untuk mendapatkan definisi tersebut. Indikator-indikator ini pun tidak lain dan tidak bukan didapat dengan ‘mengidentifikasi’ sebagian kecil dari suatu realitas yang ada di dunia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan tulisan Baldwin berada di posisi positivis karena melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang dapat disimplifikasi dan diekstrak dalam menganalisis.
Tulisan dari Baldwin ini secara jelas merupakan tulisan yang berada di posisi positivisme. Tulisan tersebut mencoba untuk merumuskan definisi tunggal secara jelas dari konsep keamanan. Perumusan definisi pun dilakukan dengan cara yang sangat khas dari positivisme yaitu dengan melakukan simplifikasi dari realitas sosial dan menggeneralisasi bahwa definisi tersebut dapat berlaku secara umum. Baldwin juga tidak mempertanyakan bagaimana definisi dari konsep keamanan yang disusunnya dapat terbentuk, apakah terdapat bias tertentu yang mempengaruhinya dalam menyusun konsep tersebut atau tidak. Simplifikasi dan generalisasi yang dilakukannya bukan berarti sesuatu yang buruk. Sebagaimana Baldwin menyampaikan pentingnya konsep keamanan yang jelas dalam perumusan kebijakan, maka simplifikasi dan generalisasi ini penting agar tercipta efisiensi dan keringkasan dalam perumusan kebijakan. Di sisi yang lain, meskipun Baldwin banyak mengawali asumsi dan argumentasinya dari tulisan Arnold Wolfers, ia mampu memberikan pandangannya sendiri secara menarik mengenai konseptualisasi keamanan.
REFERENSI
Baldwin, D. A. (1997). The concept of security. Review of international studies 23, 5-26.
Wolfers, A. (1952). “National Security" as an Ambiguous Symbol. Political Science Quarterly 67, 481-502.
0 notes
Text
Tinjauan: Dekonstruksi Makna Kedaulatan oleh Perspektif Interpretivisme
Teori-Teori Hubungan Internasional (Lanjutan) | 16 Maret 2021
Tulisan ini merupakan tinjauan atas tulisan James Sidaway (2003) berjudul “Sovereign excesses: Portraying postcolonial sovereigntyscapes.”
Dalam tulisannya yang berjudul “Sovereign excesses: Portraying postcolonial sovereigntyscapes,” James Sidaway mencoba untuk memberi pandangannya mengenai konsep kedaulatan. Cara yang dilakukannya adalah dengan mendekonstruksi istilah dari ‘negara gagal atau lemah’ menggunakan Angola dan Kongo sebagai studi kasus. Sidaway secara eksplisit menyebutkan bahwa tulisannya ini merupakan bagian dari kontribusi kritik poskolonial terhadap konsep kedaulatan. Dari dekonstruksinya, Sidaway (2003) meyakini bahwa konsep dari ‘negara gagal atau lemah’ timbul sebagai hasil dari konstruksi yang bertumpu pada norma Barat mengenai negara yang dikatakan berhasil. Implikasi dari konsep Barat tersebut membuat kita dengan mudah mencap negara-negara di Afrika sebagai negara yang gagal atau lemah dengan asumsi negara-negara tersebut kekurangan otoritas yang berdaulat atas wilayahnya. Dengan kata lain, kedaulatan negara-negara di Afrika tidak berhasil terbentuk. Berangkat dari kondisi ini, Sidaway mengajak kita untuk memikirkan kembali, apakah benar bahwa negara-negara di Afrika adalah negara yang gagal? Apakah benar bahwa kedaulatan negara-negara tersebut tidak terbentuk? Bagaimana jika sebenarnya konsep mengenai kedaulatan tidaklah tunggal? Bagaimana jika sebenarnya kedaulatan yang ada di Afrika dan di Barat memiliki definisi yang berbeda? Bagaimana jika sebenarnya kondisi yang ada di Afrika adalah kedaulatan yang tidak gagal tapi memang seperti itu adanya?
Secara sederhana, Sidaway menjelaskan bahwa kedaulatan merupakan sebuah kondisi yang di dalamnya menjelaskan bagaimana institusi dan kekuasaan yang berdaulat berkuasa dan bagaimana kedua hal tersebut berkaitan dengan kerangka kompleks dari hegemoni dan kekuasaan (Sidaway, 2003). Definisi ini menunjukkan bagaimana kedaulatan adalah sesuatu yang tidak tetap melainkan bersifat dinamis sehingga dapat berubah-ubah. Sidaway juga menolak keyakinan bahwa kedaulatan negara-negara di Afrika merupakan kedaulatan yang “kurang atau tidak ada otoritas dan koneksi” (Sidaway, 2003). Alih-alih demikian, menurutnya kedaulatan negara-negara di Afrika justru tercipta karena “kelebihan” dari kedua hal tersebut (Sidaway, 2003). Hal ini dapat dilihat dari dua contoh kasus yang dijelaskannya. Angola, sejak sebelum berdiri sebagai sebuah negara modern hingga telah merdeka saat ini, selalu dipenuhi oleh dinamika berbagai ‘kekuasaan’ dari pihak-pihak yang berdaulat. Mulai dari Portugal sebagai penjajah, gerakan anti-kolonialisme, kelompok-kelompok dalam negeri—MPLA, FNLA, dan UNITA, invasi dari Afrika Selatan, pasukan dari Uni Soviet dan Kuba, hingga administrasi transisi PBB (Sidaway, 2003). Kongo/Zaire pun mengalami hal serupa. Mulai dari kolonialisme Belgia, intervensi PBB, aktor dalam negeri seperti CONACO, dinamika geopolitik Perang Dingin, tindakan dari negara-negara sekitar, dan akun bank-bank asing seperti Swiss yang memegang keuntungan arus keluar dan masuk di Kongo (Sidaway, 2003; Young & Turner, 1985).
Dari konsep yang dijelaskan oleh Sidaway, dapat dilihat bahwa posisi penulis dari bacaan ini dalam teori HI berada di posisi interpretivisme. Hal ini tampak dari upaya Sidaway untuk tidak menerima begitu saja konsep kedaulatan yang diusung oleh norma Barat. Menurutnya, pemahaman yang sudah ada mengenai kedaulatan suatu negara yang terlalu bersifat biner—hanya terdiri dari dua pembagian—tercipta dari sebuah pembingkaian diskursus dan ideologi (Sidaway, 2003). Sidaway mencoba untuk menyusun konsep kedaulatan dengan memperhatikan konteks di Afrika dan memahami kedaulatan seperti apa yang sebenarnya ada di Afrika. Konsepnya yang kontekstual tersebut disusun dengan memperhatikan dinamika dan sejarah yang ada di Angola dan Kongo. Dari caranya tersebut, kita dapat melihat bagaimana perspektif yang berada di posisi interpretivis memperhatikan dan menganggap penting peristiwa sejarah dan berbagai kompleksitas yang ada di suatu tempat dalam melihat fenomena. Lebih lanjut lagi, konsep yang dijelaskan Sidaway memiliki aspek emansipatoris, yakni melihat kondisi yang ada di Afrika bukan sebagai sebuah abnormalitas (Sidaway, 2003). Konsep kedaulatan yang diusungnya juga mengajak kita untuk memikirkan ulang realitas dalam hubungan internasional agar tidak selalu menjadikan norma-norma Barat sebagai acuan. Kedua hal tersebut kemudian selaras dengan prinsip dan sifat umum dari posisi interpretivis, yakni emansipatoris dan mencoba memahami dunia dari sisi yang berbeda dari perspektif Barat. Selain itu, posisi Sidaway yang berada di posisi interpretivis membuat pemaparannya relevan dan mampu memberi penjelasan komprehensif dari konsep kedaulatan.
Sidaway konsisten ketika ia menyatakan pada abstraksi bahwa tulisannya ini merupakan kontribusi bagi kritik poskolonial terhadap konsep kedaulatan yang telah lebih dahulu diusung oleh teori-teori positivisme. Pemaparannya tidak mencoba untuk menyederhanakan fenomena yang ada, justru berusaha untuk mengakomodasi sebanyak mungkin kompleksitas dari praktik kedaulatan negara. Kedaulatan menurutnya tidak hanya dapat dimaknai oleh beroperasinya kekuasaan dari otoritas tunggal suatu negara tetapi juga memperhatikan bagaimana kekuasaan lainnya seperti penduduk dan negara lain beroperasi dalam wilayah tersebut. Sidaway berusaha untuk menepis pandangan ‘eksotis’ dan inferior yang kerap melekat pada negara-negara non-Barat terutama di Afrika dengan mengungkapkan bahwa kedaulatan yang berhasil tidak hanya dimiliki oleh negara-negara Barat. Dengan sifat tersebut, dapat dimaknai bahwa tulisan Sidaway secara konsisten dan jelas mampu menawarkan konsep kedaulatan dari posisi interpretivisme.
REFERENSI
Sidaway, J. D. (2003). Sovereign excesses: Portraying postcolonial sovereigntyscapes. Political geography 22, 157-158.
Young, C. & Turner, T. (1985). The rise and decline of the Zairian state. The University of Wisconsin Press: Wisconsin.
0 notes
Text
Tinjauan Refleksi Teori: Bagaimana Feminisme Mengupas HI
Teori-Teori Hubugan Internasional (Lanjutan) | 22 Maret 2021
Feminisme merupakan salah satu paradigma pemikiran dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum berada di bagian spektrum interpretivisme. Dikatakan demikian karena paradigma ini mencoba untuk memahami Hubungan Internasional secara kritis, yakni dengan tidak menerima apa adanya realita yang terlihat kasat mata tetapi mencoba untuk memahami secara mendalam fenomena HI yang ada. Feminisme sejatinya merupakan pemikiran yang telah ada sejak lama. Akan tetapi, sebagai sebuah pemikiran dalam HI, feminisme baru berkembang pasca Perang Dunia II yaitu sekitar tahun 1980-an (Viotti & Kauppi, 2012). Sylvester (2001) menyebutkan bahwa jejak literatur feminisme dalam HI dapat dilihat dari buku berjudul ‘Bananas, Beaches, and Bases’ milik Cynthia Enloe yang terbit pada 1989 yang mengulas bagaimana dinamika dan aktivitas politik internasional sehari-hari memiliki pengaruh besar dari perempuan. Selain itu, Jean Bethke Elshtain yang melalui bukunya berjudul ‘Women and War’ tahun 1987 juga menyebutkan bahwa narasi mengenai perang yang kita dapatkan terlalu abai atas perspektif perempuan dan bahwa laki-laki berperang untuk melindungi perempuan di rumah (Sylvester, 2001). Dua contoh literatur awal feminisme tersebut memberi gambaran bagaimana feminisme memiliki pandangan terhadap dunia yang berbeda dengan apa yang dimiliki perspektif mapan HI. Perbedaan antara feminisme dengan perspektif HI dalam tradisi positivisme dapat dilihat dari bagaimana feminisme melihat dunia melalui aspek relasi sosial alih-alih melihat dunia sebagai realita abstrak dan tunggal (Sylvester, 2001). Menurut feminisme, persoalan dalam HI dapat diselesaikan dengan melihat pada struktur hierarki gender yang bekerja pada kehidupan sektor privat maupun publik terutama dalam konteks politik luar negeri. Realita sosial yang ada merupakan lebih dari sebatas negara sebagai unit politik utama.
Penting untuk diingat bahwa feminisme merupakan sebuah payung pemikiran besar sehingga di dalamnya terdapat banyak cabang teori dengan detail pandangannya masing-masing. Meski demikian, terdapat setidaknya tiga hal utama yang diyakini oleh feminisme secara umum. Pertama, feminisme menggunakan gender sebagai kategori utama analisis untuk menyoroti perspektif perempuan (Viotti & Kauppi, 2012). Penggunaan gender berarti adanya pengasosiasian isu sosial dan analisis dengan baik itu maskulinitas atau femininitas (Viotti & Kauppi, 2012). Kedua, konstruksi gender secara khusus penting dalam relasi kuasa tidak hanya di rumah tetapi juga dalam politik luar negeri dan hubungan internasional (Viotti & Kauppi, 2012). Relasi kuasa diciptakan oleh adanya hierarki gender yang melahirkan ekspektasi peran secara tidak setara antara laki-laki dan perempuan (Viotti & Kauppi, 2012). Terakhir, kebanyakan teori feminisme HI kontemporer memiliki keinginan emansipatoris yakni mencapai kesetaraan bagi perempuan dengan mengeliminasi relasi gender yang tidak setara (Viotti & Kauppi, 2012). Dalam poin terakhir ini, dapat dikatakan bahwa masing-masing cabang teori feminisme memiliki caranya tersendiri yang ditentukan oleh ontologinya.
Dalam gambaran yang paling sempit, setidaknya dapat dikatakan bahwa feminisme telah membantu memperluas makna mengenai hubungan internasional. Feminisme mencoba untuk menggali lebih dalam realita dunia yang ada dengan berfokus pada ketimpangan relasi dan hierarki gender serta implikasinya terhadap kelangsungan hubungan internasional. Sebagaimana disampaikan oleh Enloe (2014), memahami politik internasional harus dilakukan dengan melihat kekuasaan secara backward dan forward karena cara kekuasaan bekerja di lingkup domestik memiliki signifikansi terhadap cara kekuasaan bekerja di lingkup masyarakat, pemerintahan, dan internasional. Dengan demikian, relasi gender penting tidak hanya dalam lingkup publik tetapi juga dalam lingkup privat. Perhatian pada relasi gender dapat mengangkat signifikansi peran perempuan terhdapa hubungan internasional yang kerap terabaikan. Upaya feminisme untuk meletakkan perhatian lebih kepada peran perempuan nyatanya bukan tanpa alasan. Pasalnya, Machiavelli pernah mengungkapkan bahwa perempuan mendorong laki-laki untuk mencampur adukkan urusan publik dan privat sehingga dapat mengurangi rasionalitas pemimpin laki-laki atau prince (Sylvester, 2001). Pendapat ini melahirkan persepsi bahwa perempuan merupakan beban bagi urusan publik termasuk politik, Hobbes juga mengakui bahwa perempuan secara biologis sama kuatnya dengan laki-laki tetapi perempuan hanya memiliki satu tugas yang harus dilakukan yakni mengurusi anak-anak di rumah (Sylvester, 2001). Pandangan-pandangan tersebut membuat peran perempuan dalam hubungan internasional kerap diabaikan dan dianggap tidak memiliki signifikansi.
Selain itu, feminisme telah membantu pemahaman atas hubungan internasional melalui pandangannya secara implisit bahwa dunia ini memiliki masyarakat yang begitu beragam sehingga seluruh permasalahan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu preskripsi. Mengasumsikan bahwa negara berisikan entitas yang homogen merupakan cara pandang sempit yang mengabaikan konflik-konflik besar yang pernah terjadi selama 30 tahun belakangan (Stokes, 2015). Pemahaman kontekstual dan detail-detail seperti budaya masyarakat, hukum yang berlaku, dan kondisi tempat tinggal masyarakat yang dianalisis turut menjadi perhatian feminisme. Feminisme memiliki cabang-cabang teori seperti feminisme liberal, differences feminisim, feminisme pos-strukturalis (True, 2010), feminisme rasionalis (Hansen, 2010), feminsime pos-kolonial, dan feminisme kritis (Agathangelou & Turcotte, 2010). Setiap cabang tersebut memiliki epistemologi dan metodologinya masing-masing yang berusaha mengungkap persoalan hubungan internasional dalam konteks relasi gender melalui berbagai sudut pandang. Keberagaman dan partikularisme yang diperhatikan feminisme dapat membantu pemahaman hubungan internasional yang lebih komprehensif.
Salah satu contoh yang menunjukkan kontribusi feminisme bagi hubungan internasional adalah persoalan mengenai perang. Perang kerap diatribusikan dengan upaya untuk menjaga keamanan dan pertahanan, terutama untuk mereka yang dianggap sebagai kelompok lemah yaitu perempuan dan anak-anak. Akan tetapi, teori-teori mapan HI tidak melihat implikasi dari perang terhadap keamanan perempuan dan anak-anak. Perempuan kerap kali menjadi korban perang dan pengungsi yang rentan terhadap prostitusi (Tickner, 2014). Jika kondisinya seperti ini, apakah dapat dikatakan bahwa perang benar-benar menjaga keamanan? Studi keamanan feminisme mendefinisikan keamanan sebagai kondisi dengan kecilnya berbagai bentuk kekerasan termasuk fisik, ekonomi, dan ekologis (Tickner, 2014). Nyatanya, hierarki gender membuat perempuan sebagai makhluk yang sub-ordinat dan dapat diobjektifikasi sehingga mereka rentan menjadi korban-korban kekerasan baik yang terjadi saat perang maupun pasca perang. Selain itu, memperhatikan peran perempuan yang terlibat aktif dalam perang dan proses negosiasi perdamaian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai konflik (Stokes, 2015). Dengan demikian, analisis terhadap upaya menjaga keamanan dan mencegah konflik dapat menjadi lebih komprehensif dan inklusif.
Feminisme sebagai sebuah paradigma studi HI berada dalam sisi spektrum yang interpretivis. Hal ini disebabkan adanya upaya feminisme untuk memahami realita yang ada secara lebih mendalam dalam konteks ini realita tersebut banyak yang bersifat intangible. Feminisme berupaya untuk memberi pemahaman atas realita dunia yang lebih konkret alih-alih hanya berupa asumsi abstrak dan tunggal mengenai dunia, sehingga membuat studi HI menjadi lebih komprehensif. Selain itu, feminisme menawarkan pandangan yang lebih inklusif sehingga membuatnya menjadi sebuah paradigma yang bersifat emansipatoris. Satu hal cukup menarik yang ditawarkan feminisme terhadap studi HI adalah bahwa ranah publik dan privat saling berkaitan. Sebagaimana Cynthia Enloe mengungkapkan “the personal is international, the international is personal.” Dengan demikian, studi HI dapat dianalisis tidak hanya dengan memperhatikan dinamika dalam sektor publik tetapi juga dengan memperhatikan gagasan dalam sektor privat.
REFERENSI
Agathangelou, A. M., & Turcotte, H. M. (2010). Postcolonial theories and challenges to ‘First World-ism.’ In L. J. Shepherd (Eds.), Gender matters in global politics: A feminist introduction to international relations (pp. 44-58). Routledge.
Enloe, C. (2014). Bananas, beaches, and bases: Making feminist sense of international politics. University of California Press.
Hansen, L. (2010). Onthologies, epistemologies, methodologies. In L. J. Shepherd (Eds.), Gender matters in global politics: A feminist introduction to international relations (pp. 17-27). Routlegde.
Stokes, W. (2015). Feminist security studies. In P. Hough et al., International security studies: Theory and practice (pp. 44-56). Routledge.
Sylvester, C. (2001). Feminist international relations: An unfinished journey. Cambridge University Press.
Tickner, J. A. (2014). Gender in world politics. In J. Baylis, S. Smith, & P. Owens, The globalization of world politics: An introduction to international relations(pp. 258-273). Oxford University Press.
True, J. (2010). Mainstreaming gender in international institutions. In L. J. Shepherd (Eds.), Gender matters in global politics: A feminist introduction to international relations (pp. 189-203). Routledge.
Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2012). International relations theory (5th ed). Pearson Education, Inc.
0 notes
Text
Urgensi Kehadiran ASEAN di Sungai Mekong bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi ASEAN
Kerja sama Ekonomi di ASEAN | 19 Juni 2021
Sungai Mekong merupakan sebuah sungai yang terletak di daratan Asia. Sungai ini memiliki hulu di teritori Tiongkok dan mengalir melewati negara-negara ASEAN daratan yaitu Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Sungai yang panjang dan besar ini telah menopang kehidupan sekitar 66 juta orang di ASEAN daratan, khususnya mereka yang hidup di sekitar sungai (Hoang & Seth, 2021). Sungai ini telah dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti penambangan pasir, irigasi, dan pembangkit tenaga listrik melalui pembangunan bendungan (Hoang & Seth, 2021; Zhang, 2020). Akibatnya pemanfaatan yang berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan alam, volume air di Sungai Mekong kini mengalami penurunan. Lovgren (2020) mengukapkan bahwa volume air pada 2019 merupakan volume air terendah dalam 100 tahun terakhir. Tentunya hal ini mengancam kehidupan penduduk di lima negara ASEAN di atas. Meski demikian, kebanyakan Negara Anggota ASEAN memandang bahwa “persoalan ini lebih baik diselesaikan melalui kerangka sub-kawasan” karena hanya berdampak pada beberapa Negara Anggota (Hoang & Seth, 2021). Hal ini tentunya sangat disayangkan karena ASEAN seolah-olah enggan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terlebih lagi, apabila dibandingkan dengan kasus Laut Tiongkok Selatan, kasus ini memiliki karakteristik yang serupa. Berangkat dari problematisasi tersebut, tulisan ini berargumen bahwa ASEAN haruslah hadir dalam mengatasi persoalan di Sungai Mekong. Argumen ini akan didukung oleh argumen-argumen yang dielaborasi sebagai berikut.
Pertama, kelestarian dan keberlanjutan Sungai Mekong memiliki peran penting dalam perekonomian negara-negara Mekong. Delta sungai ini menghasilkan 15% dari total produksi beras dunia dan memiliki kandungan ikan segar senilai 17 Milyar Dollar AS setiap tahunnya (Sembiring, 2018). Secara lebih spesifik, waduk irigasi Mekong telah membantu Thailand menjadi eksportir beras terbesar dan Vitenam eksportir besar terbesar di dunia pada 2015 (Tong, 2017). Lebih lanjut lagi, sektor perikanan di sungai ini memiliki peran yang sangat penting terhadap ekonomi baik itu di sub-kawasan ASEAN daratan maupun kawasan ASEAN secara keseluruhan. Pada 2015, sektor perikanan dari Sungai Mekong berkontribusi terhadap 18% PDB Kamboja, 12.8% perekonomian Laos, 3.1% PDB Vietnam, dan 1.8% PDB Thailand (Hunt, 2016). Dengan persentase yang besar tersebut, akan menjadi suatu bencana serius apabila persoalan volume air di Sungai Mekong tidak segera diselesaikan.
Kedua, Sungai Mekong juga berperan penting dalam transportasi negara-negara Mekong karena sungai ini menghubungkan negara-negara tersebut dengan laut (Tong, 2017). Sebagai contoh, sekitar 73% transportasi kargo dan sekitar 27% transportasi penumpang di Vietnam melewat sungai ini. Hal ini sejatinya masih berkaitan dengan poin pertama. Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi memainkan peran besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apalagi khususnya bagi Laos, negara yang tidak memiliki pantai, tranportasi melalui Sungai Mekong tentu berperan vital bagi kehidupan negara tersebut.
Ketiga, kerangka kerja sama sub-kawasan dalam Sungai Mekong masih belum mampu memberi dampak besar dibandingkan dengan kerangka kerja sama ekonomi ASEAN secara keseluruhan. Hal ini memprihatinkan sebab keranga kerja sama sub-kawasan Sungai Mekong terdapat lebih dari satu, yaitu: Greater Mekong Forum, Lancang-Mekong Cooperation, the Mekong River Commission, dan Greater Mekong Subregion (Tong, 2017). Absensi ASEAN dalam isu ini semakin memprihatinkan jika melihat kenyataan bahwa Amerika Serikat memiliki program politik luar negerinya untuk pengembangan kawasan Sungai Mekong yang bernama Lower Mekong Initiative (Tong, 2017). Dorongan bagi ASEAN untuk hadir dan menyelesaikan persoalan Sungai Mekong bukanlah tanpa alasan. Jika kita membandingkan perkembangan isu ini dengan isu Laut Tiongkok Selatan dan perkembangan kerja sama ekonomi ASEAN secara keseluruhan, perkembangan isu Sungai Mekong sangatlah jauh tertinggal. Terkhususnya dalam kerangka Lancang-Mekong Cooperation, dapat dikatakan bahwa rendahnya efektivitas kerja sama disebabkan oleh adanya peran Tiongkok dan rendahnya daya tawar negara-negara Mekong di hadapan Tiongkok. ASEAN telah berkembang baik dalam kasus Laut Tiongkok Selatan dengan menysun Code of Conduct bersama Tiongkok sehingga bukan tidak mungkin ASEAN dapat menyelesaikan persoalan Sungai Mengkok karena adanya daya tawar yang lebih.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa urgensi kehadiran ASEAN dalam isu Sungai Mengkok sangat tinggi. Tingginya urgensi ini karena isu Sungai Mekong berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di ASEAN, baik secara agregat, bagi negara-negara secara individual, maupun bagi penduduk di sekitar sungai tersebut. ASEAN harus dapat hadir di kasus ini dan mengedepanka Sentralitas ASEAN. Tanpa kehadiran ASEAN, relevansi ASEAN sebagai institusi kawasan di Asia Tenggara menjadi dipertanyakan bahkan dapat berkurang. Jika hal ini sampai terjadi, tentunya akan menjadi fenomena kelam dalam catatan riwayat dinamika ASEAN.
REFERENSI
Hoang, T. H., & Seth, F. N. (2021, Mei 19). Why Asean needs to care about Mekong issues like it did with haze. SCMP. https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3133963/why-asean-needs-care-about-mekong-issues-it-did-haze
Hunt, L. (2016, 4 Januari). What Is the Value of the Mekong River?. The Diplomat. https://thediplomat.com/2016/01/what-is-the-value-of-the-mekong-river/
Lovgren, S. (2020, Januari 31). Southeast Asia’s most critical river is entering uncharted waters. National Geographic. https://www.nationalgeographic.com/science/article/southeast-asia-most-critical-river-enters-uncharted-waters
Sembiring, M. (2018). Examining Cooperation for Climate Change Adaptation in Southeast Asia: The Case of Lower Mekong River Basin. S. Rajaratnam School of International Studies. https://www.jstor.org/stable/resrep26806
Tong, L. (2017, 31 Oktober). Is Sustainable Development Along the Mekong Possible?. The Diplomat. https://thediplomat.com/2017/10/is-sustainable-development-along-the-mekong-possible/
Zhang. H. (2020, Maret 20). China’s ‘Development Approach’ to the Mekong Water Disputes. The Diplomat. https://thediplomat.com/2020/03/chinas-development-approach-to-the-mekong-water-disputes/
1 note
·
View note