Text

002.
Usai cekcok lewat pesan kemarin itu, sama sekali tak San lihat presensi sang majikan. Bahkan sekarang, kala jam sudah menunjukkan pukul delapan pagi, di mana seharusnya sang majikan kecilnya sudah berangkat ke sekolah sedari tadi, malah sama sekali tak ia temukan bayangnya yang seringkali tergesa turuni tangga.
Merasa aneh dan janggal, lantas Choi San naiki tangga menuju lantai atas. Ia berhenti di depan pintu kamar bercat putih itu, sedikit ragu untuk ketuk pintu sebab ia tahu si pemilik kamar akan merasa sangat terganggu. Beberapa detik ia hanya berdiri di sana, menimang keputusan untuk mengetuk pintu itu atau tidak, hingga suara benda jatuh dari dalam sana lantas buat ia dekatkan telinga dan kontan ketuk pintu berkali-kali.
“Wooyoung, are you okay? Ada yang jatuh? Jung Wooyoung?”
Sunyi. Tak ada sahutan dari dalam sana, lantas ia kembali dekatkan telinga. “Wooyoung, boleh buka pintu—”
BRUKK!
Sedikit San jauhkan wajahnya dari sana kala suara ribut benda yang menghantam pintu tiba-tiba kagetkan dirinya.
“Pergi sana lu, Choi San!”
San kembali mendekat ke pintu. “Wooyoung, ayo bicara sebentar. Saya minta maaf soal yang kemaren sore.”
“Gue gak mau denger omongan lu lagi! Pergi lu, bangsat!”
Ia ambil satu tarikan napas guna tenangkan diri sendiri, sebelum akhirnya kembali muntahkan kata dengan sedikit kencang supaya yang di dalam sana bisa mendengarnya dengan baik.
“Kamu masih marah? Is this my fault, Jung Wooyoung?”
Di balik pintu itu, Wooyoung berdiri tegang. Pening tiba-tiba menyerang.
“You think this is all my fault, Jung Wooyoung? Istri saya meninggal gara-gara kamu, dan sekarang kamu nyalahin saya karena semua orang jahat ke kamu? You deserve it all.”
Sunyi lagi. San berniat untuk kembali mengetuk pintu, namun tiba-tiba pintu itu sudah lebih dulu terbuka, kalakian Wooyoung keluar dari sana dan langsung menyambar kerah baju yang San kenakan.
“Fuck you! I hate the way you talk, asshole!” Matanya menyorot tajam manik gelap milik San kala kalimat itu mengudara, buat sang pengawal terkejut serta kebingungan.
“Wooyoung, kenapa?”
“Don't ever mention my name again, you bastard!”
“Wooyoung, I don't get it. Saya ada salah ngomong? Kalau iya, saya minta maaf. Saya sama sekali gak bermaksud nyakitin perasaan kamu, Wooyoung.”
Yang lebih muda kemudian lepaskan cengkramannya pada kerah baju San, lantas mundur dengan raut kesalnya. “Kenapa makin lama lu makin mirip Papa? I hate seeing it and I hate hearing it.”
“You hate me?”
"Yeah, asshole, I hate you! I hate the way you say 'saya' to me. I hate the way you say my name. I hate anything that makes me think of my dad. I hate it because you have the same personality as him. Fuck, I hate it...!”
San lantas terdiam. Dibubuhi fakta tentang bagaimana bencinya Wooyoung terhadapnya buat ia sedikit kebingungan. Bahkan ia sama sekali tak bersuara kala yang lebih muda mundur, lantas membanting pintu dengan kencang.
Ia sama sekali tak mengerti kenapa.
ㅤ

ㅤ
Sekitar pukul tiga sore, Wooyoung turuni tangga setelah mengurung diri seharian di dalam kamar. Bahkan kala San kembali ketuk pintu kamarnya tadi siang untuk hantarkan nampan berisi makanan, pemuda itu sama sekali tak beri sahutan. Dan sekarang, ia berlagak seolah tak ada yang terjadi, seolah sama sekali tak ada nyawa lain di dalam ruangan itu. Seolah tak ada Choi San yang tengah duduk di sofa dengan mata yang tak lepas dari setiap pergerakannya.
Wooyoung tenteng kresek putih di tangan, lantas pemuda itu keluar rumah, melewati sang pengawal begitu saja. Dan Choi San, tentu saja ia segera beranjak dari tempatnya duduk sekarang. Dikuncinya pintu, kalakian diiringinya Wooyoung dari belakang, dengan jarak yang cukup jauh tentu saja. Entah pemuda itu akan pergi ke mana, sebab tumben sekali ia hanya berjalan kaki, meninggalkan motor kesayangannya di garasi.
Sekitar seratus meter kemudian, pemuda kecil mendadak berhenti lantas dengan tiba-tiba berbalik, untuk kemudian mendapati sang bodyguard yang tengah kelabakan sebab ketahuan diam-diam telah mengikutinya.
“Pulang, bangsat, ngapain ngikutin gue?!” Teriakan itu terdengar sangat kesal, dan San berusaha keras mencari jawaban yang logis.
“Kamu ga seharusnya keluar sendirian. Jadi, saya temenin, ya? Takutnya ada yang jahatin kamu.”
Di depan sana, Wooyoung mendecak sebal, ia tak pernah suka dengan sifat Choi San yang selalu ingin mencampuri urusannya. “Orang tua banyak tingkah,” katanya selagi berbalik, kemudian melanjutkan perjalanannya susuri jalanan komplek.
Menunggu Wooyoung berjalan beberapa langkah lebih dulu di depan, barulah San kembali iringi pemuda kecil dengan jarak yang lumayan jauh. Ia tak tahu ke mana tujuan Wooyoung sekarang, dengan setelan celana hitam selutut serta sweater hitam panjang, pemuda itu berjalan dengan santai di depan sana. Beberapa meter kemudian, pemuda itu berbelok menuju taman komplek.
Sang majikan bergabung bersama empat anak kecil yang tengah duduk bermain pasir di dekat perosotan. San sempat berhenti sejenak, sedikit kebingungan melihat bagaimana Wooyoung berbaur dengan anak kecil berumur sekitar tujuh tahun, saling sapa selayaknya teman sebaya.
Ia tak benar-benar tengah mengasuh anak kecil, kan?
Selesai dengan rasa terkejut serta kebingungannya, San kemudian sedikit mendekat dan memilih bersandar di perosotan. Memantau bagaimana empat anak kecil itu menghujani Wooyoung dengan berbagai macam pertanyaan.
“Bang, kok udah jarang main ke sini?”
“Bang, bawa scooter lagi, dong.”
“Bang, punya gundam gak?”
“Bang, Bang, kemaren aku liat abang lagi beli es goyang depan sekolah ku.”
Okay, I'm definitely looking after a toddler, batin Choi San.
Setelah dihujani berbagai macam pertanyaan, Wooyoung tertawa, lantas kemudian menjatuhkan pantatnya di atas pasir. “Yechan, scooter-nya rusak belum sempet dibenerin. Abang gak punya gundam ya adek-adek, gak tertarik. Dan, Yujun, kamu liat abang kok gak nyapa?” Begitu caranya menjawab beberapa pertanyaan dari empat anak kecil yang juga tengah duduk di hadapannya.
“Aku liat sekilas doang, Bang, soalnya buru-buru udah bel.”
“Padahal kalo nyapa bakal abang traktir es goyang.”
“Yah, Bang, lain kali deh aku sapa...”
Dan pemuda dengan setelan serba hitam itu lantas tertawa. Mereka lanjut mengobrol, bermain pasir dengan mangkuk dan wadah berbagai macam bentuk. Hingga beberapa menit kemudian, satu pertanyaan terlontar dari salah satu anak kecil yang sedari tadi menatap ke arah Choi San.
“Bang, itu siapa? Daritadi berdiri di situ,” katanya selagi jari telunjuknya yang kecil tertuju ke arah San yang kini berdiri kebingungan sebab tiba-tiba ditatap empat anak kecil—mungkin lima.
“Gak tau, tukang galon kali.”
“Ajakin main pasir juga, Bang, kasian.”
Wooyoung ingin tertawa kencang mendengar kalimat barusan, namun berusaha ia tahan guna menjaga raut datarnya yang tengah pelototi San. “Heh lu, sini!”
Lantas dengan ragu sang bodyguard mendekat, ikut duduk melingkar di atas pasir, di samping Wooyoung.
“Tukang galon komplek kita ganteng ya ternyata,” anak yang tubuhnya lebih kecil di antara yang lainnya beri komentar usai perhatikan lamat-lamat perawakan Choi San, buat Wooyoung menoleh sinis ke arah yang lebih tua.
“Emang lu ganteng?”
“Menurut kamu?”
“Jelek.”
Dan Choi San hanya bisa tersenyum getir mendengar jawaban tanpa ragu itu. Setelahnya, ia hanya diam, hanya memperhatikan Wooyoung dan empat anak kecil itu berebut mangkuk pasir yang hanya berjumlah empat. Wooyoung sebenarnya mengacau.
Setelah tak dapat mangkuk pasir incarannya, Wooyoung diam, kemudian meraih kresek putih yang sedari tadi ia taruh di sampingnya. “Kita main game aja, yuk! Yang bisa jawab pertanyaan abang, nanti dapet jelly,” ujarnya bersemangat selagi pamerkan beberapa bungkus jelly di dalam kresek putih miliknya. Dan empat anak kecil di hadapannya kembali antusias, melupakan tumpukan pasir yang disusun dengan cetakan mangkuk pasir.
“Oke, kita mulai, ya,” katanya, memulai quiz game berhadiah jelly itu. “Pertanyaannya, kapan terjadinya inflasi terbesar di Indonesia?”
Dan tentu saja ia langsung dihujani protes dari empat anak kecil serta San yang diam-diam menyimak pertanyaan. “Mereka gak akan ngerti apa itu inflasi, Wooyoung.”
“Lu diem!” Dipelototinya Choi San, kemudian nyengir merasa lucu melihat eskpresi kesal empat anak di hadapannya. “Ya udah, pertanyaannya ganti yang basic aja, ya?”
Usai berpikir sejenak, ia kembali melontar pertanyaan. “Bahasa Inggris nih, gak apa-apa, ya? Hunter dulu, apa Bahasa Inggrisnya pisang?”
“Easy, Bang. Banana!”
“Iyup, bener!” Wooyoung beri tepukan tangan, kemudian ulurkan satu bungkus jelly berbentuk buah kepada Hunter. “Sekarang Seeun. Apa kepanjangannya cireng?”
“Aci digoreng, aci digoreng!”
“Bener, bener!” Diberikannya lagi satu bungkus jelly rasa cola kepada Seeun. “Oke Yujun, apa kepanjangannya SD?”
“Sekolah Dasar, Bang! Mudah banget ini.”
Wooyoung terkekeh, kemudian ulurkan satu bungkus jelly kepada Yujun. “Terakhir Yechan. Apa nama scooter abang?”
Anak kecil itu tampak berpikir sejenak, lupa ingat nama apa yang Wooyoung berikan untuk scooter elektriknya yang sering ia pinjam. “Oh, inget. Woosh, kan, Bang?”
“Yup yup, bener!” Diulurkannya lagi satu bungkus jelly kepada Yechan. Dan sekarang, ia sedikit condongkan badan menghadap San yang diam-diam menyimak permainan kuis mereka. “Sekarang lu.”
Pemuda tinggi angkat alisnya, bingung. “Saya gak apa-apa, gak usah—”
“Hewan apa yang gak punya titit?”
“Jung Wooyoung?!”
Yang lebih kecil tertawa terbahak-bahak bersama empat anak kecil lainnya, merasa lucu mendengar pertanyaan demikian keluar dari mulut Wooyoung. Sedangkan sang bodyguard beri tatapan tak menyangka serta tak habis pikir.
“Kenapa, sih? Emang ada hewannya, tau. Tinggal jawab aja, kalo gak tau tinggal skip, lu gak akan dapet jelly.”
“Ganti aja pertanyaannya,”
“Enggak! Jawab aja, sih, ribet lu! Ini tuh edukasi, gak ada hal cabulnya juga ngapain takut jawabnya?!”
San hela napas sejenak, sebelum akhirnya muntahkan kata untuk jawab pertanyaan nyeleneh dari Wooyoung. “Hewan yang gak punya alat kelamin—”
“Yang gak punya titit, lebih tepatnya!”
“Iya, Wooyoung. Ada tiga. Burung, hiu, laba-laba,”
“Tuh, tau! Lama bener jawab tiga itu doang,” omelnya, selagi tangan ulurkan dua bungkus jelly pada Choi San. Setelah San sambut bungkusan terakhir jelly itu, Wooyoung sejenak diam, perhatikan lamat-lamat wajah sang bodyguard.
“Kenapa, Wooyoung?”
Namun, alih-alih menjawab, sang majikan malah pasangkan kresek putih yang telah kosong ke kepala sang bodyguard. Dan ia kemudian beranjak, lalu berlari kencang menjauh dari sana. Sisakan Choi San yang menahan amarah serta empat anak kecil yang terbahak melihat tingkah dua orang dewasa itu.
“Jung Wooyoung, you little shit...!”
0 notes
Text

With all his efforts.
Agenda makan siang itu nyaris batal terealisasi kala sang Papa berkali-kali menelponnya untuk datang ke kantor, ada yang perlu dibicarakan, katanya. Tapi syukurlah Salazar punya Mama yang selalu bisa membantu disaat-saat seperti ini. Mamanya berhasil bujuk sang Papa untuk tidak mengganggu Salazar dulu sampai sore nanti. Dan sampai sore nanti, Salazar punya banyak waktu untuk mengobrol bersama Wave di kediamannya.
Usai menjemput Wave pukul setengah dua belas siang, mereka langsung menuju rumah makan untuk realisasikan agenda makan siang yang mereka rencanakan tadi malam. Usainya, Salazar langsung ajak Wave pergi menuju rumahnya. Rumah yang dulu menjadi tempat perpisahan mereka sebelum Salazar berangkat ke Australia.
Rumah itu tak banyak berubah semenjak ditinggal bertahun-tahun dulu oleh pemiliknya. Hanya saja, hangatnya nyaris menghilang. Sudut-sudutnya nyaris beku sebab lebih sering ditinggal oleh pemiliknya dari pagi sampai sore hari. Namun, bagi Salazar, rumah ini jauh lebih baik daripada rumah mereka yang berada di Australia.
Lampu ruang tamu dinyalakan oleh Salazar kala mereka akhirnya berhasil injakan kaki ke dalam rumahnya. Ia lepaskan jaket kulit miliknya, sisakan kaos hitam polos, sebelum akhirnya ia beralih tatap Wave yang berdiri diam didepan pintu.
“Kok diem aja di situ? Sini duduk dulu, nanti aku bikinin minum.”
“Keinget waktu kita kumpul buat latihan drama dulu,” katanya, lantas berjalan menuju sofa setelah lepaskan topi miliknya.
“Iya? Dulu waktu kita latihan drama itu, menurut kamu seru gak?”
“Seru aja, kok. Kenapa?”
Salazar beranjak, pergi ke dapur yang bersebelahan dengan ruang tamu, hanya bersekat dinding tipis tak terlalu lebar. Ia buka kulkas, keluarkan dua kaleng minuman soda, lantas dibawanya menuju Wave di ruang tamu.
“Waktu itu kan aku belum inget sama kamu. Aku lebih banyak diemin kamu selama kita latihan drama itu,” ia berkata, selagi tangan ulurkan satu kaleng minuman kepada Wave.
“Iya, gue sedih banget waktu itu.” Tentu saja kalimat itu Wave lemparkan hanya untuk candaan, sertakan kekehan setelahnya. Dan Salazar pun demikian, walau masih merasa bersalah tentang banyak hal di belakang. Namun, jika diingat-ingat kembali, sedikit lucu bagaimana minimnya interaksi mereka kala itu.
“Mau main ke kamarku gak?” Tanya pemuda tinggi tiba-tiba, buat yang lebih kecil hampir tersedak minuman bersoda di dalam genggaman.
“Hah? Mau ngapain?” Tanyanya.
“Gak ada, sih. Aku mau kasih liat sesuatu ke kamu.” Begitu katanya. Lantas dengan ragu Wave ikuti langkah Salazar menuju kamar miliknya.
Kamar yang terletak di lantai dua, paling ujung ruangannya. Wave cukup kaget sebab ruangan itu ternyata masih sama, tak banyak yang berubah dari terakhir kali ia menginap di sini sebelum Salazar pamit untuk pergi. Mungkin yang berbeda hanya beberapa dekorasi yang sebelumnya tak pernah ada, seperti beberapa poster artis dan film kesukaan si tuan kamar. Warna kamarnya masih monokrom seperti dulu, seperti tak diberi nyawa, namun hangatnya tetap ada.
“Bagus gak kamarku? Waktu pindah ke sini lagi sempet aku rombak dikit.”
Pemuda kecil menoleh sejenak, sebelum akhirnya kembali taruh fokus pada kaca besar yang diletakkan di sudut ruangan. “Iya? Tapi gak terlalu beda, sih, dari kamar lu yang dulu. Cuma warnanya makin suram aja,” katanya, mengundang tawa dari pemuda tinggi yang tengah tutup pintu.
“Padahal udah aku tempel banyak poster biar gak suram-suram banget.”
“But I like the way you arranged the decorations, sih, especially kaca sama tanaman gede itu,” Wave berkata selagi telunjuknya mengarah pada tanaman hias lumayan besar yang Salazar taruh di depan kaca besar. “So it warms up the room,” lanjutnya.
“Kamu suka? Nyaman gak?”
Wave tak tahu pasti apa maksud Salazar tanyakan dua hal itu, namun ia beri anggukan tanpa ragu. Dan Salazar hanya tersenyum, merasa puas atas jawaban lewat anggukan kepala dari Wave Joelian.
Pemuda tinggi kini beralih, capai laci meja belajarnya, lantas keluarkan selembar kertas yang ia lipat rapi. Di samping tempat tidurnya ia berdiri, menghadap Wave yang kini berdiri belakangi kaca besar dalam ruangan.
Ia berdeham, tampak gugup entah mengapa, sebelum akhirnya ia muntahkan kata usai pemuda kecil beri atensi penuh padanya.
“So...Wave, I made a poem for you. Gak tau ini bisa dibilang puisi atau bukan, but I made this for you with all my effort. Tolong didengar sebentar, ya?”
Wave tiba-tiba kebingungan, pun ikut merasa gugup kala Salazar angkat selembar kertas itu di depan dadanya untuk kemudian ia baca.
“10 things I love about you...,” begitu ia mulai puisi itu, matanya sempat curi pandang pada sosok pemuda kecil di hadapannya, sebelum ia lanjut baca selembar kertas dengan senyum tertahan.
“I love your smile, and the way you talk to me.
I love the way you look at me, and how I get caught up in your gaze.
I love the way you laugh, but I hate it when I see you cry.
I love the way you write, and all the poems and letters you write.
I love the shabby paper of your poems, and seeing your neat writing on them.
I love listening to your chatter on the swing in the afternoon, and your wave when I said goodbye.
I love the feeling of missing you even though it makes me sick.
I love the way you hold my hand, and the way you stroke my hair.
I love your spoiled side, and the way you pout and ask for your back to be rubbed.
And mostly I love the way you make me fall in love. I love everything as long as it's you.
From the beginning until now, I love everything about you. Not just 10 or even 100. I love you because it's you.”
Pipi pemuda kecil memerah, sertakan panas dan juga salah tingkah. Sedangkan pemuda tinggi kini tutupi seluruh wajahnya menggunakan selembar kertas puisi di tangannya. Padahal ia sudah siapkan seluruh keberanian dan kepercayaan dirinya untuk lakukan ini dari beberapa hari sebelumnya, namun akhirnya tetap saja ia berakhir malu dan salah tingkah setelah bacakan puisi miliknya.
“Puisinya bagus,” puji Wave setelah berhasil lawan perasaan salah tingkahnya.
Di depan, Salazar mulai singkirkan kertas dari wajahnya. “Serius? Thanks to Kat Stratford for inspiring me to write this poem, i guess.”
Keduanya lantas tertawa.
Salazar maju, kikis jarak antara ia dan Wave. Mereka sempat bersabung mata untuk waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya pemuda tinggi lempar pandangan ke kaca di belakang pemuda kecil.
“Aku pernah janji buat ngenalin kamu ke crush-ku, inget gak?”
Wave sontak menengadah, tatap Salazar di hadapannya. Oh, ya, ia hampir lupa Salazar pernah menjanjikan itu padanya.
“Turn around and see for yourself,” bisiknya selagi sentuh pundak Wave untuk beri isyarat agar pemuda itu segera berbalik.
Lantas kala ia berbalik, yang dilihatnya hanyalah pantulan dirinya serta Salazar yang berdiri di belakangnya sertakan senyum hangat miliknya. “Am I your crush?” Tanyanya, tanpa basa-basi, dan tentu saja hal itu mampu buat pipi serta telinga Salazar menjadi merah.
“You are. And sorry for being annoying all this time, but I tried to tell you about all my feelings for you.” Ia sentuh pundak Wave, meminta atensi pemuda itu agar menghadapnya kali ini. “Kayaknya dulu itu, waktu kita masih sering main bareng, aku udah jatuh cinta sama kamu. Tapi karena masih kecil dan belum ngerti cinta-cintaan, aku anggapnya cuma perasaan suka dan seneng aja. But I swear, I loved it when we kissed—no no! I mean, ga bermaksud cabul, tapi...bener kok.”
Wave tertawa, entah Salazar tengah serius atau tidak sekarang, namun mendengar pemuda itu berbicara perihal ciuman itu lagi membuat ia merasa lucu.
“Kenapa ketawa? Aku lagi confess ke kamu, loh.”
Dengan sisa tawanya, Wave mencoba untuk rangkai kata, sebelum Salazar merajuk dan tak ingin lanjutkan sisa kalimatnya. “Gak bermaksud ketawa, tapi cara kamu confess lucu banget. Puisinya juga bagus banget, thank you for putting all your effort into that poem, ya, Salazar. Aku juga udah suka kamu dari kita SD dulu, tau.”
“Ya udah, ayo pacaran!”
“Hah?”
“Kamu juga udah balik ke setelan pabrik cara ngomongnya. Udah pake aku-kamu lagi, I mean. Berarti kita udah bisa pacaran dong? Mau gak pacaran sama aku?”
Wave sesaat membeku, sedikit tak menyangka akhirnya Salazar akan nyatakan perasaan padanya hingga mengajaknya untuk berpacaran. Dan walaupun dengan sedikit keraguan, pemuda itu akhirnya beri anggukan kepala.
“Mau?”
“Mau. Ayo pacaran.”
Kalakian, tubuh Wave menghilang ditelan dekapan Salazar. Pemuda tinggi tersenyum begitu lebar usai dengar jawaban dari yang lebih kecil. Mungkin merasa lega karena usahanya tak berakhir sia-sia. Dan pemuda kecil ikut salah tingkah di dalam dekapan itu, antara tak percaya apakah semua ini nyata.
Sahabat dari kecil dan sempat terpisah untuk waktu yang cukup lama, mereka berdua tak pernah menyangka akan jatuh cinta lalu berakhir berpacaran. Kiranya, perasaan yang sempat diabaikan sebab diri sendiri belum mengerti perkara hati, sekarang akhirnya temui jawaban atas keresahan selama mereka berpisah.
Salazar lepaskan dekapannya, sentuh kedua pundak Wave dengan lembut selagi mata mereka bersabung satu sama lain. Tangannya bergerak, terus ke atas hingga berhenti pada pipi berisi milik pemuda kecil. Cukup lama ia diam, mengunci netra jelaga milik Wave pada tatapan lembutnya, seolah meminta izin pada sang tuan untuk tindakan yang akan ia lakukan selanjutnya.
Kalakian perlahan, ia kikis jarak, lantas daratkan ciuman di atas bilah bibir milik pemuda kecil. Sejenak ia berhenti, beri waktu untuk keduanya terbiasa. Namun, Wave pejamkan mata dengan gelisah, lantas tiba-tiba dorong pundak Salazar agar menjauh darinya.
“Wave, kenapa?”
Yang lebih kecil menengadah dengan raut wajah tegang serta mata yang berkaca-kaca, “Salaz, aku takut...”
0 notes
Text
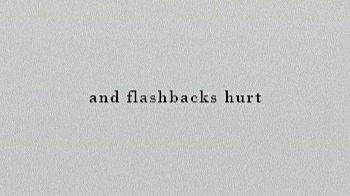
And flashbacks hurt.
Siang itu, dua puluh lima menit sebelum pukul dua, pertandingan basket antar sekolah mereka dimulai. Wave dengan jiwanya yang masih sangat membara untuk harumkan tim basket mereka; bermain dengan sangat serius sampai rasanya pertandingan kali ini terasa sangat panas dari pertandingan-pertandingan yang pernah ia ikuti sebelumya.
Ia ingat sekali, kala itu, ia pernah miliki perasaan optimis ini sebelumnya, kala dunianya masih sangat baik-baik saja. Ia ingat pernah menjadi anak basket dengan jiwa membara, yang kalau bisa dilihat mungkin punggungnya akan mengeluarkan api saking semangatnya ia di tahun-tahun awal menginjak bangku SMA.
Ia juga ingat, ia pernah miliki banyak sekali kenalan antar sesama anak basket, bahkan beberapa diantaranya adalah anak-anak dari sekolah berbeda yang sebelumnya sempat menjadi rival mereka di lapangan basket.
Dulu, saat semuanya masih baik-baik saja.
“Dan, lempar airnya satu!” Di sebelah, Yessa berseru kepada Daniel, minta dilemparkan satu dari belasan botol air mineral yang mereka bawa kemari.
Pertandingan selesai lima menit lalu dengan perbandingan skor yang lumayan tipis. Tim mereka mendapat 125 poin, sedangkan tim lawan 129 poin. Mereka kalah. Namun, si tuan rumah berjanji akan undang mereka untuk bermain ke lapangan ini lagi lain kali. Dan mereka mau tak mau terima kekalahan dengan lapang dada.
“Panas banget, anjir, ini AC-nya gak nyala apa, ya?”
Protes itu datang dari Rian, lelaki bertubuh tinggi jangkung dengan fitur wajah tegas. Harrol di sebelahnya beri anggukan dengan tangan yang mengibas baju bagian dada, tampaknya sama gerahnya dengan Rian. “Mati kali AC-nya,” katanya.
Wave yang baru saja usai menenggak minumannya, kalakian berdiri dari bangku panjang dipinggir lapangan, mencuri atensi beberapa anggota tim yang ikut duduk di sana.
“Gue ke toilet bentar, ya. Air minum gue jangan dibuang!”
Lantas ia beranjak dari sana, telusuri pinggiran lapangan, di ujung lorong ia berbelok ikuti papan rambu yang menunjukkan ke arah mana toilet pria berada. Hingga saat kakinya injak lantai putih toilet yang lembab itu, tangan seseorang tarik dirinya menepi, lantas buat ia tubruk wastafel di dekat pintu masuk.
Ia sempat merintih sebab nyeri pada pinggangnya yang berhasil menubruk pinggiran wastafel dengan cukup kencang, sebelum akhirnya ia sadar siapa yang tengah berdiri dengan setelan jersey futsal di depannya.
“Apa kabar?”
Jangan pernah sangka kalimat itu akan terdengar ramah di telinganya, sebab yang terjadi adalah sebaliknya. Seringai menjengkelkan itu hantarkan perasaan ingin memukul kala akhirnya ia sadar seseorang di depannya adalah si pengacau hari-harinya yang damai.
Si bangsat Roki itu muncul lagi.
“Kok gak bareng dua temen lu yang cupu itu? Ditinggal lagi kayak Salaz sebelumnya?”
“Berisik lu, anjing!”
Wave pernah diberi amanat oleh Yonathan; jika berhadapan dengan orang seperti Roki, sebisa mungkin harus dilawan, jangan diam aja. Dan setidaknya, kali ini Wave memakinya.
“Jawab basa-basi gue dong, Wave. Lu apa kabar?” Suaranya menggema lagi di ruang kosong juga dingin dan lembab itu, buat Wave keraskan rahang demi tahan segala umpatannya yang ingin ia layangkan di depan wajah lelaki itu.
Dan sialnya, saat ia ingin beranjak dari sana, lelaki itu malah mengungkungnya. Masing-masing tangannya diletakkan dipinggiran wastafel yang Wave belakangi, menguncinya, buat jarak diantara mereka menipis.
“Minggir, bangsat, gue mau kencing!”
Dan bahkan dorongan yang Wave beri pada pundak Roki sama sekali tak berarti, tubuh lelaki itu bahkan tak bergerak barang sesenti.
Seringaian itu berubah menjadi decakan dengan gerak bibir sinisnya. Tatapannya seolah merendahkan, menatap Wave seolah lelaki itu orang yang paling rendah di dunia. “Gue benci banget liat lu sekarang. Sok keras, padahal aslinya bocah cengeng gampang mewekan. Lu tau gak, muka cengeng lu itu kesukaan om-om sangean?!”
Matanya membola, diwaktu yang sama, binar di dalam sana meredup kemudian menghilang. Mendengar kata-kata menjijikkan itu keluar dari mulut orang yang sangat dibenci adalah hal yang paling menjengkelkan.
“Lu kenapa cuma mau temenan sama orang-orang kayak Salaz? Kenapa gak mau temenan sama gue? Huh? Kenapa waktu gue ajak kenalan dulu, lu melengos seolah gue gak pantes buat temenan sama orang kayak lu?! Jawab gue, bangsat!”
Rambut belakang Wave dijambak, dipaksa mendongak demi tatap manik legam milik Roki yang kian tajam bersama rahangnya yang kian mengeras. “Gue ajak lu kenalan baik-baik waktu itu, tapi lu melengos dan nyamperin Salaz tanpa sambut uluran tangan dari gue. Cowok murahan kayak lu emang gak bisa dibaikin, ya, anjing! Lu kira bocah SD gak bisa sakit hati?! Kalau waktu itu lu gak nolak ajakan gue buat temenan, mungkin gue gak akan gangguin lu selama ini. Tapi emang gue bego aja demen sama orang kayak lu!”
Napas Wave tercekat, kepalanya yang terus dipaksa untuk mendongak tiba-tiba pening. Ia sama sekali tak mengerti. Ia tak mengerti apa yang Roki pikirkan hingga lelaki itu taruh dendam padanya selama ini.
“Dikasih apa lu sama Salaz sampe gak mau temenan lagi sama yang lain? Gue mati-matian temenan sama Salaz biar bisa deketin lu, fitnah Salaz biar kalian berantem, tapi lu tetep gak mau lirik gue, bangsat!”
Wave jauhkan kepalanya kala tangan Roki yang lainnya sentuh rahangnya dengan kencang. Tatapan mereka sempat bertemu, sebelum akhirnya Wave buang pandangan.
“But thank goodness he's finally gone now. He left you for me.” Dia dekatkan wajah, mengikis jarak untuk kemudian bisikkan satu kalimat tepat di telinga milik Wave. “Salaz lu itu udah bosen dan milih buat ninggalin lu.”
Wave akhirnya berontak, berusaha mendorong tubuh Roki untuk menjauh. Namun, lelaki sialan itu malah menarik tengkuk Wave lantas daratkan ciuman pada bilah bibirnya. Memaksa Wave untuk berhenti bergerak dengan menjatuhkan tubuh mereka ke lantai, kalakian diraupnya bibir itu dengan rakus dan tak tahu diri.
Wave menangis. Berusaha berontak dari kungkungan tubuh Roki yang menimpanya di atas sana. Berkali-kali ia layangkan pukulan pada tubuh Roki, tetapi beku atas situasi yang tiba-tiba menimpanya justru adalah hal yang lebih dulu kuasai dirinya. Kala akhirnya, bibir itu berhenti dan mulai sambar lehernya, Wave kembali sadar dan akhirnya menjerit meminta pertolongan.
Tak berselang lima detik, seseorang datang, menyambar tubuh Roki, disudutkan ke tembok, lantas dipukuli. Berkali-kali. Wave dengar suara pukulan yang dilayangkan berkali-kali pada wajah dan juga tubuh Roki.
Ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya terduduk dilantai dengan tangisan yang tak bisa ia kendalikan. Hingga akhirnya, Harrol dan Sadam datang.
“Stop, Simon, anak orang bisa meninggal!”
Ia yang kalut akan perasaan seolah direnggut sesuatu dari dalam dirinya akhirnya beranikan diri untuk mendongak, dan temukan Simon yang tengah ditarik paksa oleh Harrol, serta Roki dengan wajah yang sudah habis dipenuhi lebam dan luka.
Kilas balik ini menyakitkan.
Ia tak pernah sangka akan dilecehkan oleh seseorang yang selama ini suarakan rasa benci untuk dirinya. Seandainya ia tahu Roki bersekolah di sini, ia mungkin tak akan ikut pertandingan hari ini. Dan mungkin kejadian beberapa menit lalu tak akan terjadi. Seandainya ia tahu lelaki itu taruh dendam atas rasa sakit hati akan sikapnya di masa lalu, mungkin Wave akan lebih dulu meminta maaf dan tak perlu alami semua ini. Andai semuanya tak terjadi, mungkin rasa trauma ini tak akan serang dirinya hingga hilangkan rasa percayanya kepada seseorang yang selama ini ia tunggu kabarnya.
Ia benci kilas balik ini.
0 notes
Text

Semua hanya tentang waktu.
Kapan Salazar pulang?
Pertanyaan itu bahkan sudah terucap dari satu jam usai Salazar pamit padanya untuk berangkat ke bandar udara. Padahal, sudah ia bubuhkan janji untuk tidak menangis kala usapan di kepala menjadi salam perpisahan dari Salazar seusai mereka habiskan waktu di warnet tempat biasa mereka bermain. Padahal, ia mengaku tak akan lagi menjadi anak cengeng di hadapan Salazar. Namun, nyatanya, sepulang ia dari warnet siang itu, ditumpahkannya segala resah serta kecewa lewat tangisan di dalam dekapan sang Papa.
Seharian anak itu menangis, merajuk tak ingin makan malam, sampai sang Mama kebingungan harus membujuknya dengan cara seperti apa. Dan besoknya, Wave yang berumur sepuluh pulang sekolah dengan mata sembab, mengadu kepada sang Mama yang saat itu baru saja selesai masak untuk makan siang. Ia bilang tak ada Salazar di sekolah, lantas ia menangis sendirian di toilet sampai jam istirahat selesai.
Hal itu berlanjut sampai hampir satu minggu, hingga akhirnya ia terbiasa dengan situasi di sekolah. Terbiasa dengan hilangnya sosok Salazar di bangku sebelahnya.
Terkadang anak itu juga tak mengerti. Rasanya terlalu kekanakan baginya untuk menangisi seseorang hanya karena ia pindah ke luar negeri. Rasanya terlalu tak masuk akal baginya untuk merajuk pada semua orang hanya karena kehilangan sosok teman. Namun, nyatanya, hingga sekarang, masih belum juga ia temukan seseorang yang bisa gantikan sosok Salazar. Ia bahkan memilih untuk tak banyak berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Ia lebih memilih sibukkan diri dengan ikut les dan bimbingan belajar, berharap hal itu bisa menjadi distraksi agar ia tak melulu memikirkan pertanyaan perihal; kapan Salazar pulang?
Namun, rasanya sama saja. Satu bulan sekali, anak itu akan menangis sendirian. Mengurung diri di dalam kamar, membuat surat untuk sosok yang sama sekali belum memberi kabar. Ia merasa usahanya untuk mengirim kabar lewat surat juga akan berakhir sia-sia, sebab alamat Salazar di Australia saja dirinya sama sekali tak tahu. Kendati demikian, ia tetap nekat dengan berpikir; mungkin suatu saat nanti surat-surat itu akan sampai di tangan Salazar, entah dengan cara yang bagaimana.
Dan hal itu ia lakukan terus-menerus setiap bulan. Sampai saat hari di mana ia jatuh sakit, suratnya terhenti. Wave yang saat itu hampir menginjak usia dua belas tak berhenti menangis di dekapan sang Papa. Minta dipangku bagai anak koala. Anak itu mengigau, meracaukan segala hal yang menjadi keresahannya kala itu.
“Aku kenapa gak kayak anak-anak lainnya, ya, Pa?” anak itu berkata selagi lengannya ia kalungkan pada leher sang Papa yang memangkunya di atas sofa ruang tengah.
“Apanya yang gak kayak anak-anak lainnya, Wave? Semua orang 'kan beda-beda, gak harus sama.”
Ia jatuhkan dagunya di atas pundak sang Papa, cemberut atas jawaban yang tak memuaskan itu. “Aku liat temen-temen kelasku gampang banget nyari teman, tapi kenapa aku susah banget. Gak ada yang mau temenan sama aku...”
Telapak tangan besar itu bergerak, mengusap punggung belakang sang putra yang kembali murung hari ini. Cooling patch di dahi sang anak ikut mengkerut kala alis itu terangkat, bingung apa yang salah dengan diri sendiri sampai sesulit ini untuk memulai pertemanan.
“Sebelumnya kamu udah pernah ajak mereka buat temenan belum?”
Yang di atas pangkuan beri gelengan, lantas sang Papa kembali lempar pertanyaan. “Kenapa belum?”
“Cara mereka natap aku gak kayak Salaz. Mereka natap aku dengan judging look, aku jadinya takut,”
“Emang kalau Salaz natapnya kayak gimana?”
Wave tegakkan badan, beri unjuk tatapan lembut dengan senyum tipis miliknya pada sang Papa. “Kayak gini. Dia selalu tatap aku kayak gini sambil senyum sedikit. Beda banget kayak temen-temen kelasku, tatapan mereka gak ramah.”
Sang Papa ikut tersenyum kala Wave peragakan sosok Salazar untuknya. Diberinya anggukan kecil, sebelum kembali ia dekap tubuh itu.
“Lagi kangen Salaz, ya?”
Sendu itu kembali datang. Hantarkan kelabu pada awannya yang sudah jarang sekali menjadi biru. Dan Papanya jelas tahu, sudah hapal sekali isi kepala anak itu.
“Berlebihan gak ya, Pa, kalau aku bilang aku kangen Salaz?”
“Enggak, sayang, sama sekali gak berlebihan,”
“Aku kangen Salaz, Pa...“
Papanya tersenyum, beri usapan pada tengkuk leher sang anak. Kiranya, sudah banyak sekali rasa rindu itu Wave tampung sendiri. Disuarakan pada orang-orang, berharap sang pemilik nama mendengar dari angin yang tak sengaja menguping. Namun, dari sekian banyak rasa itu, sang anak lebih memilih untuk memendamnya di dalam hati, dinikmati sendiri. Lantas kala perasaan itu membuncah, ia tumbang lalu jatuh sakit.
“Papa tau gak, sebelum Salaz pindah, dia sempet bilang ini ke aku,”
“Hm? Bilang apa?”
“Dia bilang, Wave, cari temen yang banyak, ya. Katanya, dia pengen aku punya setidaknya satu temen yang kayak dia. Maksudnya apa? Nyari temen yang kayak Salaz tuh susah, loh. Nyari temen yang bisa ngerti perasaanku kayak Salaz tuh susah, tapi dia ngomong gitu kok gampang banget. Dia maunya aku lupain dia, terus cari temen baru yang kayak dia? Aku kadang gak ngerti sama pikirannya.”
Papanya terdiam, berusaha cerna tiap kalimat sang putra, hingga saat ia mengerti sepenuhnya, ia beri ulas senyum dengan bubuhkan usapan lembut di belakang kepala.
“Salaz mungkin takut kamu sendirian di sini. Dia pengen kamu cari temen yang banyak biar kamu gak ngerasa kesepian,”
“Dia ngomong gitu seolah dia gak akan pulang lagi ke sini,”
“Kok ngomongnya gitu? Salaz udah janji ke kamu buat pulang lagi 'kan?”
“Iya, tapi hampir setahun kok dia belum juga ngasih kabar?”
“Coba hadap Papa bentar. Ada yang mau Papa sampaikan.”
Lantas sang putra Hansen bergerak, tegakkan tubuh selagi mata beri tatap pada netra jelaga milik sang Papa yang persis seperti miliknya.
“Wave sayang, dengar ini baik-baik, ya. Di dunia ini, manusia gak cuma dikasih kesempatan berteman sama satu orang. Masih banyak manusia-manusia lainnya yang mau berteman sama Wave. Kalau bukan sekarang, mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau mungkin nanti waktu Wave masuk SMP?”
Dibenahinya helaian rambut sang anak yang berantakan, disisir pelan dengan jemari telunjuknya. “Semuanya hanya tentang waktu. Kalau sudah ditakdirkan buat ketemu lagi, pasti bakal ketemu, entah tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya. Sabarnya tolong diperbanyak lagi, ya?”
Dan anggukan kecil itu lantas munculkan sedikit cerah bak matahari pagi di luar sana. Kurva kecil pada sudut bibirnya beri sedikit nyawa untuk kelabunya hari yang ia punya.
Ia selalu tak mengerti kenapa ia selemah ini sampai rasa rindu itu kuasai diri. Ia selalu tak mengerti disebut apa perasaan ini; perasaan berdebar tiap kali sosok Salazar jajah isi kepalanya tanpa henti. Kiranya, rasa rindu itu menjelma menjadi perasaan asing yang sama sekali belum ia rasakan sebelumnya. Menjajah isi kepala bersama bayang Salazar hingga rasa itu membuncah.
“Kalau nanti Salaz pulang, aku boleh marahin dia gak?”
“Kenapa?”
“Karena dia gak ngasih kabar.”
Papanya terkekeh, beri anggukan tanpa ragu. “Iya, gak apa-apa marahin, biar dia tau kalau kamu selama ini udah sabar nungguin kabar dari dia.”
“Kira-kira, dia kangen aku juga gak, ya, Pa?”
“Kalau itu Papa gak tau. Biar jadi urusan dia sama perasaannya.”
0 notes
Text

Letters written but never sent.
Bermodal video tutorial dan titah dari sang Mama lewat panggilan video, Salazar berhasil buatkan sup sayur dan nasi merah untuk Wave Joelian. Bermodal internet juga ia pilihkan menu makan siang untuk Wave yang katanya bagus untuk dikonsumsi oleh orang pengidap gerd dan asam lambung. Dan syukurnya, pemuda kecil tak banyak protes saat ia sodorkan menu sederhana yang ia buat dengan penuh usaha. Mungkin karena setiap suapnya akan dihadiahi usapan lembut di kepala, pun apresiasi yang ia bubuhi tak kalah banyaknya dari semangkuk nasi.
Usainya, setelah habiskan makan siang dan lewati banyak konversasi di meja makan, Salazar beri pelukan hangat yang sudah ia janjikan, sertakan juga usapan-usapan lembut dan menenangkan di punggung juga surai. Memangku tubuh yang lebih kecil selagi lengan itu melingkar di sekitar lehernya. Pundak Salazar juga bermain peran, menjadi tumpuan untuk kepala yang dijatuhkan kala kantuk mulai rayapi kelopak mata si kecil dalam pelukan.
Ia tak pernah bubungkan harap akan terjadinya semua peristiwa hari ini. Tak pernah ia berharap akan pangku Wave bak anak koala yang sedang manja, tak pula berharap akan hadapi sisi lain dari teman masa kecilnya. Ia tak kuat. Perasaannya membuncah, meletup-letup saat akhirnya ia dengar Wave sebut dirinya aku dan panggil ia dengan kamu. Padahal sebelumnya juga begitu, saat mereka masih sama-sama dahulu kala sekali, saat jarak belum pisahkan mereka berdua. Namun, entah kenapa, kali ini rasanya berbeda.
Ada desiran aneh yang ia rasa, kala manisnya ucap juga kalimat yang keluar dari bilah bibir yang lebih kecil ditujukan untuk dirinya. Ia ingin asumsikan ini sebagai rasa cinta, namun, rasanya seperti ada yang salah. Ia takut dengan fakta. Ia takut mengetahui bahwa ia pikul rasa itu sendirian, tanpa orang kedua.
Gerakan kecil dari pemuda dalam pelukan lantas buat matanya yang sempat terpejam kembali terbuka. Tangannya yang sempat terhenti beri usapan, kini kembali bekerja, tak ingin pemuda kecil terganggu tidurnya.
“Usapnya jangan berhenti...”
Ah, ia beri protesan.
“Iya, ini diusap lagi.”
Namun, tiba-tiba Wave tegakkan diri, lepaskan kalungan lengan pada leher Salazar. “Aku mau tiduran di kasur aja.”
“Kenapa?”
“Takut, nanti paha kamu kesemutan.”
Pemuda tinggi beri ulasan, “Gak apa-apa, semut gak bakal berani deketin, kok.” Padahal aslinya, paha itu sudah kram dan mati rasa. Namun, pemuda kecil kukuh, lantas langsung tarik diri dari pelukan sang pemuda tinggi.
Selimutnya ditarik untuk kemudian tutupi sebagian diri, kembali pejamkan mata; berusaha temui kembali alam bawah sadarnya. Sedang yang di sana masih sandarkan diri di kepala kasur milik yang tengah tidur, merekam bagaimana pemuda kecil rebahkan diri dengan posisi menghadap tempatnya duduk sekarang.
Lengan, paha, dan dada yang sempat beri dekapan masih sisakan panas, pun degup jantung yang tak normal itu masih bekerja layaknya dipacu dengan kencang. Ia benar-benar tengah jatuh, ya? Jatuh pada teman masa kecilnya. Jatuh cinta, namanya, kalau ia tak salah duga.
ㅤ
ㅤ

ㅤ
ㅤ
Lembayung senja diluar sana datang mengintip dari celah jendela, kala si pemilik kamar masih pulas dalam tidurnya. Nyawa lain di dalam sana lantas sigap tutup jendela juga tirai untuk halau jingga yang berniat bangunkan pemuda yang masih terbaring di atas kasurnya.
Tak ia sadari sudah seharian ia berada di kediaman Wave, temani putra tunggal Hansen yang tengah sakit. Sampai pukul lima sore pun, sang wanita yang titipkan anaknya pada dirinya belum juga pulang ke rumah, kiranya masih sibuk dengan jam kerjanya.
Setelah cukup lama rekam langit jingga di luar sana, kini matanya beralih pada satu kardus berukuran sedang yang ditaruh di atas meja belajar. Ia bukan orang yang kepoan, namun melihat kardus dengan untaian kata berbunyi “memori kita” di atasnya, buat ia dilanda jutaan ton rasa penasaran. Lantas tanpa pikir panjang, ia dudukkan diri pada kursi, kalakian, dibukanya kotak persegi.
Ia tercekat.
Tumpukan surat dengan kertas yang menguning, juga lembar sisa kertas yang disobek asal; penuhi kotak yang ia buka dengan tangan yang bergetar. Ia temukan beberapa bungkus permen warna-warni di dalam sana, juga satu permen cincin yang masih terbungkus plastik bening.
Diambilnya sebagian surat. Tertulis namanya di sana, dengan alamat rumah yang hanya tertera; Australia. Kalakian, dengan tergesa jemarinya buka amplop yang bungkus satu lembar kertas kekuningan. Terukir banyak kalimat di atas sana, dibubuhkan melalui tinta hitam dengan tulisan tangan tak terlalu rapi. Entah tahun berapa surat ini dibuat, namun yang pasti, itu adalah saat mereka dipisah dengan jarak tiga ribu kilometer lebih.

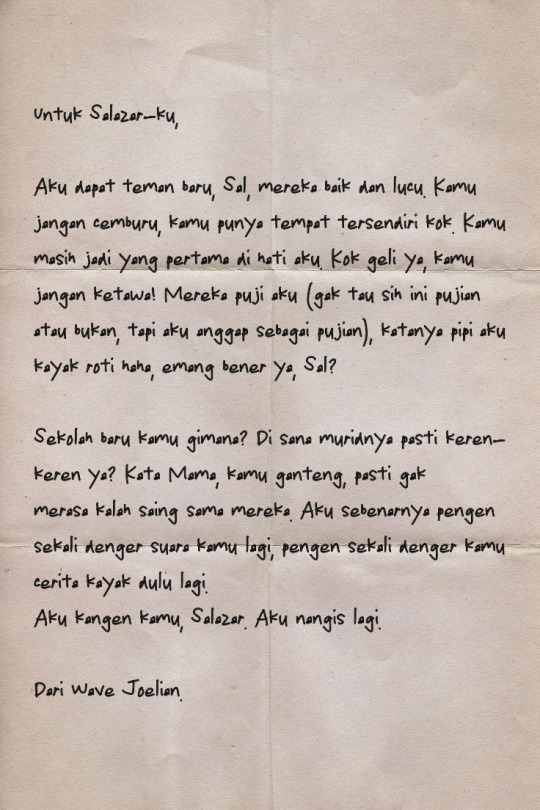
Ia sejenak berhenti usai buka dua surat yang secara garis besar, isinya pertanyakan kapan ia kembali. Atur napas yang semakin tak karuan. Ia mana tahu. Ia mana tahu teman masa kecilnya itu juga buatkan ia surat, namun tak pernah dikirim ke tujuan. Ia tak pernah terpikir untuk beri alamat rumahnya di negeri kanguru kala ia pamit pada Wave waktu itu. Ia mana tahu, kepindahannya akan bangkitkan berjuta rasa rindu.
Ia tak pernah tahu, mereka pikul perasaan itu dengan jarak beribu-ribu.
Jemarinya kembali bergerak, sentuh surat-surat lain di dalam sana, dan berakhir ambil dua amplop yang kemudian ia buka. Tulisan di atas lembar kertas itu cukup berbeda dari surat-surat sebelumnya; yang dua ini jauh lebih rapi. Jauh lebih banyak pula kalimat yang ditorehkan di atas sana.



Tangisnya tumpah. Tak tertampung, usai ia baca dua surat terakhir. Ia bagai disiksa. Penyesalan serang dirinya bersama sesak yang berburu.
Ia menyesal tak banyak usaha untuk bisa hubungi Wave saat mereka berpisah, menyesal hanya kalut dalam pikiran buruk bahwa Wave tak menginginkan ia dan pertemanan mereka. Ia menyesal tak cari cara dan malah berpasrah kala kewarasannya hampir dibunuh oleh rasa rindu.
Sesenggukan ia menangis, selagi tangan genggam lembar surat yang hampir basah oleh air mata. Fakta bahwa perkataan Simon tentang Wave, surat, dan puisi-puisinya ternyata benar adanya. Ia seperti menggila, menyesali semuanya, padahal segala sesuatu sekarang sudah baik-baik saja. Namun, ada sisi dalam dirinya yang belum bisa ia maafkan, sebab pernah abaikan Wave dan percaya pada pikiran buruknya.
“Umh, Salaz...”
Rengekan halus itu berasal dari pemuda yang baru saja terjaga dari tidurnya. Menyingkap selimut, lantas tegakkan diri selagi punggung tangan usap mata yang agaknya bengkak usai tidur berjam-jam. Ia berdiri, hampiri Salazar yang duduk belakangi tempat tidurnya. Kalakian, ia berhenti, membeku beberapa sekon usai mata tangkap pemuda tinggi tengah tangisi isi kotak persegi. Sebelum akhirnya, dengan sigap ia sambar kotak serta surat-surat di dalam genggaman Salazar, marah atas lancangnya pemuda itu sentuh sesuatu yang tak seharusnya ia tahu.
Tubuhnya gemetar. Tanpa sadar, ia cengkram surat-surat itu hingga kertasnya berantakan. Ia benar-benar lupa untuk singkirkan kotak itu dari tempat yang mungkin akan tertangkap pandangan Salazar. Ia tak tahu kenapa dirinya setakut ini, ia tak mengerti sama sekali.
“Kenapa diambil? Kamu takut aku baca surat-suratnya?”
Salazar berdiri di hadapan Wave, sisa tangisnya masih ada, pipinya yang basah dibiarkan begitu saja. “Aku udah baca setengahnya.”
Pemuda kecil menengadah, tatap wajah kacau pemuda tinggi. Ia tak tahu, tapi dirinya kesal. “Lu lancang!”
Yang lebih tinggi agaknya tak mengerti kala tatapan tajam miliknya ia lempar, ada nyawa lain yang merasa diintimidasi. Ia tiba-tiba ikut kesal, sesak yang berkali-kali hantam dadanya tak dipedulikan, ia tak bisa kendalikan semua perasaan yang serang dirinya hari ini.
“Kenapa gak kirim semua surat itu ke aku? Kenapa disimpan buat diri sendiri?”
“Alamat lu aja gue gak punya, gimana bisa kirim surat ke lu!”
Ia usap wajahnya dengan kasar, “then at least, biarin aku baca semua suratnya.”
“Enggak!”
Tangan pemuda tinggi terangkat, dengan lancangnya raih kotak dalam dekapan Wave, namun sang pemilik lebih dulu beri dorongan agar ia menjauh.
“Lu tuh sadar gak sih, Sal? Selama ini lu gak pernah usaha buat hubungin gue. Lu gak pernah kirim surat ke gue, padahal lu jelas tau alamat rumah ini.”
“Kata siapa?! Kata siapa gue gak pernah usaha?!” Bentakan itu akhirnya lolos juga. Kiranya, ia benar-benar kesulitan untuk kendalikan semua perasaan yang membuncah.
“Gue selalu coba buat kirim surat ke lu, tapi Papa gak suka. Dia selalu berusaha buat ganti alamatnya, dan akhirnya surat-surat gue gak pernah sampe. Gue udah usaha selama ini, Wave! Gue udah coba cari lu lewat sosmed. Facebook, instagram, twitter, di semua platform udah pernah gue cari, tapi akun lu gak ada! Terus lu masih salahin gue juga?! Kalo lu mau komunikasi kita lancar waktu itu, seharusnya lu juga usaha buat hubungin gue lewat apapun. Tapi ternyata lu, enggak, kan? Usaha lu cuma sampe nulis surat doang!”
BUGH!
Wave daratkan pukulan, tepat pada tulang pipi Salazar. Buat kewarasan pemuda tinggi terkumpul kembali setelah beberapa sekon menghilang. Buat ia tersadar telah bentak dan teriaki Wave hingga buat pemuda itu menangis.
“Lu gak ngerti..! Lu gak pernah tau apa aja yang gue lewati selama ini!”
Perasaan Salazar mencelos. Melihat bagaimana Wave menangis karena perkataannya; hal yang tak akan pernah bisa dimaafkan oleh dirinya sendiri. Ia bak orang gila, diselimuti amarah atas rasa sesal yang dirasa, dan dengan bodohnya ia malah limpahkan semuanya kepada pemuda yang presensinya sungguh ia jaga untuk tak lagi dibuat terluka.
Ia sungguh sudah gila.
“It was all my fault. Aku gak bermaksud buat bentak-bentak kamu, Wave, maaf...” Ditangkupnya pipi berisi itu, diberi usapan lembut kala pemuda kecil ingin berontak. Tatapan keduanya bertemu, bersabung lama dengan sisa-sisa bulir jernih di ujung mata. Sebelum akhirnya pemuda tinggi muntahkan untaian bunyi bahasa dengan sangat lembutnya.
“Aku emang gak pernah tau semuanya, Wave, aku clueless soal semuanya semenjak kita pisah. Aku pengen tau semuanya dari sudut pandang kamu, aku pengen tau apa yang bikin kita gak pernah bisa komunikasi selama enam tahun itu.”
Pemuda kecil tak beri protesan, kiranya usapan di pipi itu berhasil tenangkannya yang juga sempat dikuasai amarah tak berarti.
“So, please, tell me everything. Aku perlu tau, aku gak mau kita terus-terusan salah paham. Ceritain semuanya, ya? Pelan-pelan aja. Apapun itu, aku gak akan hakimi kamu.”
Lantas kala pemuda di hadapannya beri anggukan, ia ulas senyuman, sertakan usapan lembut di pipi pemuda kecil. Kembali beri nyawa atas hilangnya sejenak akal sehat mereka berdua.
0 notes
Text
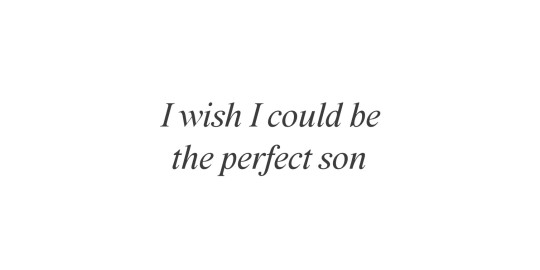
Kamu sama sekali bukan beban.
Titik embun yang menetes dari setangkai daun sambut kedatangan Salazar di kediaman Wave pagi ini. Kicauan burung di atas tiang listrik semakin jelas kala kuda bermesin miliknya berhenti di pekarangan rumah, lantas ia matikan laju mesinnya.
Pukul enam pagi saat ia ketuk pintu sertakan panggilan untuk si tuan rumah agar segera bukakan pintu untuk dirinya. Ekspektasi akan disambut figur kecil dengan rambut berantakan serta wajah bantal sehabis tidur harus ia kubur dalam-dalam; kala sosok wanita berdiri di depannya setelah pintu dibuka lebar.
Dengan tergesa wanita itu kenakan flatshoes miliknya selagi tangan tenteng tas kulit berwarna coklat. Perlihatkan senyuman sebagai sambutan untuk tamu mereka di pagi buta, sebelum akhirnya ia sentuh pundak pemuda yang masih berdiri tatap dirinya sedari tadi.
“Pagi, Salaz! Boleh titip Wave, gak? Tante lagi buru-buru banget, harus ke tempat kerja sekarang.”
Yang ditanya melongo, “Kenapa dititip, Tante?”
“Dia lagi gak enak badan. Semalem gerd-nya kambuh, sekarang harus istirahat, tapi Tante lagi ada masalah di tempat kerja. Titip ke Salaz bisa, ya?”
Matanya melebar, dengar kalimat barusan buat jantungnya berdetak tak nyaman. “Wave di atas?”
“Iya, masuk, gih. Titip anak ganteng Tante, ya!”
Lantas usai tepuk dua kali pundak Salazar, wanita paruh baya itu berlalu keluar dari pekarangan rumah. Sedang yang berdiri di sana kebingungan; tak habis pikir kenapa wanita itu sangat santai sedangkan sang anak tengah kambuh penyakitnya sekarang.
Kalakian, ditutupnya pintu usai lepaskan sepatu kets yang dipakai, lantas ia naik ke lantai atas. Injak anak tangga satu persatu hingga saat dicapainya lorong lantai atas, ia berhenti lalu berdiri tepat di depan pintu bercat putih. Sedikit ragu, ingin ketuk pintu terlebih dahulu kala ingat, semalam, ia berjanji tak akan mengganggu. Namun, tangan kanannya tiba-tiba sudah sentuh knop pintu, lantas didorongnya hingga pintu terbuka dan ia masuk ke dalam sana.
Buntalan selimut yang tutupi sebagian tubuh Wave menjadi pemandangan pertama yang ia lihat kala dirinya berhasil injakan kaki ke dalam sana. Perlahan, ia mendekat usai tutup kembali pintu, duduk di tepi kasur selagi matanya rekam sosok yang meringkuk belakangi dirinya.
“Wave?”
Tubuh itu menggeliat kecil, beri respon atas namanya yang diudarakan oleh nyawa lain di dalam kamar dingin miliknya. Sentuhan kecil di puncak kepalanya lantas buat dirinya terjaga dari tidur ayamnya. Ia berbalik, terlentang dari posisi meringkuknya. Matanya masih terpejam, hanya saja nyawanya sudah terkumpul sebagian, dan bahkan nyeri di pelipis berusaha dihiraukan.
“Papa...”
Alis Salazar yang bertaut beri respon terkejut sekaligus kebingungan saat sosok yang terbaring dibungkus selimut itu tiba-tiba panggil sang Papa. Kiranya, pemuda itu tengah mengigau; tangannya bergerak cari apa saja untuk digenggam, dan berakhir cengkram jaket parasut milik Salazar.
“Papa, maaf...aku bikin Mama sibuk terus. Aku ini beban, ya? Setiap Papa mau pergi berlayar, Papa selalu bilang kalo semuanya bakal baik-baik aja, semuanya bakal berjalan lancar, tapi sekarang semuanya kacau, Pa. Plan yang Papa bikin untuk kehidupan kita bertiga gak pernah berjalan karena Papa udah gak ada sekarang. Papa...aku ini gak bisa apa-apa, ya?”
Tetes bulir jernih itu jatuh basahi bantal empuk miliknya. Tangisnya pelan, ia tak sesenggukan, bahkan mata itu masih setia terpejam kala napasnya mulai tak beraturan. Sedang cengkramannya pada jaket milik Salazar menguat, berikan getar dari buku-buku jari yang memutih.
“Aku—aku bahkan gak bisa apa-apa waktu tau kalo ternyata Mama kerja di bar. Aku gak bisa bantu apa-apa, sedangkan Mama banting tulang sampai malam. Aku gak berguna, ya, Pa? Aku gak pernah bisa jadi anak sempurna. Maaf karena aku banyak kurangnya...”
Sakit. Hati Salazar rasanya teriris. Dengar untaian bunyi bahasa yang diucap dengan segala resah juga air mata yang tumpah ruah; cekik Salazar tepat pada kerongkongannya.
Ia tak tahu apa saja yang telah pemuda itu lewati hingga dirinya tumbuh bersama nestapa atas malapetaka yang renggut satu nyawa dari bagian keluarganya. Ia juga tak bisa terka sudah berapa lama resah ini dipendam sendirian hingga gerogoti kewarasan.
Kalakian, tubuhnya ditarik untuk merunduk oleh salah satu lengan yang sentuh pundak kokohnya. Tuntut dekapan untuk lepaskan sisa tangis yang masih kesulitan untuk ditumpahkan. Lantas tak perlu waktu lama untuk Salazar cerna semuanya. Dipeluknya pinggang itu erat kala Wave kalungkan kedua lengan di leher selagi dirinya naik ke atas pangkuan.
Dan benar saja, tangis itu benar-benar tumpah ruah hingga basahi jaket milik pemuda tinggi yang niat awal dikenakan untuk lari pagi. Ia sama sekali tak masalah, bahkan kala punggungnya hantam kepala kasur di belakangnya, alih-alih beri protesan, ia malah pamerkan senyum hangat miliknya.
Dalam posisinya yang memangku Wave Joelian dengan lengan yang dekap erat pinggangnya, Salazar bisikkan kalimat penenang berkali-kali tepat di telinga pemuda kecil. Kalimatnya sederhana, kurang lebih seperti; tak apa, kamu sama sekali bukan beban untuk siapa-siapa.
Tangisnya memang belum sepenuhnya usai, namun setidaknya, Salazar tenang sebab ia bisa jamin pemuda kecil akan selalu aman dalam dekapan. Ia janji akan berikan tenang melalui usapan lembut yang ia bubuhkan pada punggung itu dengan penuh kasih sayang. Ia ingin Wave merasa aman.
“Jangan, ya...?” Tiba-tiba yang kecil berkata.
“Hm?”
Yang di atas pangkuan eratkan cengkraman pada jaket parasut milik yang lebih tinggi, sebelum kalimat selanjutnya dimuntahkan dengan lirihnya.
“Kamu...jangan pergi kayak Papa. Jangan pergi lagi kayak dulu, aku gak mau! Kalau kamu pamit lagi, aku gak bakal kasih izin kali ini. Kamu denger aku? Aku—aku gak mau ditinggal lagi kayak dulu!”
Entah pemuda itu sadar atau tidak kala bibir ucapkan rentet kata memohon supaya tak ditinggal pergi untuk yang kedua kali. Entah seberapa sungguh-sungguh ia dalam ucapkan kalimatnya barusan, namun Salazar tak akan anggap itu sebagai angin lalu.
“Aku gak akan pergi lagi, Wave. Gak akan berani tinggalin kamu lagi.”
“Kamu jangan pernah lupain aku lagi!” Dipukulnya pundak itu, tak kuat, bahkan rasa sakitnya tak berarti. “Kamu gak tau gimana rasanya nungguin seseorang, padahal udah ketemu. Kamu gak tau, kan, gimana rasanya kangen sama seseorang padahal orangnya udah di depan mata? Kamu pernah bikin aku rasain itu semua, Salazar!”
Salazar meringis, lagi-lagi hatinya terasa teriris. Ia tak pernah tahu bagaimana Wave lewati hari tanpa dirinya, kala jarak dengan jahatnya pisahkan mereka tanpa komunikasi sama sekali. Dan kala, akhirnya, mereka kembali dipertemukan, malapetaka iringi keduanya untuk yang kesekian.
“Maaf. Maaf aku pernah bikin kamu rasain itu semua. Maaf aku gak langsung kenali kamu waktu kita ketemu lagi waktu itu. Aku sekarang udah di sini, Wave, kamu jangan takut. Aku gak akan bikin kamu rasain itu lagi. Aku janji.”
Dekapan itu semakin erat kala Wave tenggelamkan wajahnya pada pundak kokoh milik Salazar. Melankolis sekali rasanya, namun tumpahkan segala isi hati yang telah ia pendam untuk waktu yang lama, bukanlah hal yang buruk ternyata. Entah sejak kapan ia sadari, dekapan Salazar terasa seperti rumah yang paling aman untuk ia tempati berhari-hari, bertahun-tahun, atau mungkin selamanya. Entah sejak kapan, peluk hangat dengan usapan lembut di punggungnya dapat hentikan tangis yang tak pernah bisa ia kendalikan.
Dan entah sejak kapan, kala akhirnya Salazar sadari bahwa sosok dalam dekapan sudah kembali jemput tenang. Napas yang mulai teratur dengan cengkraman jemari yang mulai mengendur, buat Salazar sadar bahwa sosok itu sudah benar-benar tertidur.
“Everything will be fine, my Dear.”
0 notes
Text

011.
Pengawal bukanlah pekerjaan pertama Choi San. Dirinya pernah bekerja sebagai pelatih di dua tempat kursus olahraga bela diri di Jakarta. Tinju dan taekwondo adalah keahliannya, dan mendiang sang Ayah adalah salah satu alasannya bertahan di dunia olahraga dan bela diri sampai saat ini. Ayahnya yang sebelumnya berprofesi sebagai atlet bela diri pernah berkata bahwa; jadilah kuat agar kamu tak diinjak-injak. Klise memang, namun pesan dari sang Ayah tak akan pernah pemuda itu lupakan sampai sekarang. Atau saat Ayahnya berkata; kemampuan bela diri kamu jangan dipakai sembarangan, gunakan untuk jaga orang yang kamu cinta dan sayang.
Maka akhirnya, mulai saat itu San putuskan untuk mendalami ilmu bela dirinya di salah satu sekolah ilmu bela diri yang cukup terkenal di tempat kelahirannya.
Dan persoalan mengapa ia tiba-tiba menjadi seorang pengawal di Jakarta?
Dulunya ia direkrut sebagai pelatih di salah satu tempat kursus tinju yang cukup terkenal di pinggiran kota Jakarta. Dari sanalah ia bertemu dengan Jung Ilwoo, Ayah Wooyoung, yang memperkenalkan diri sebagai rekan dari pemilik tempat kursus, tempat di mana ia bekerja saat itu.
Pria itu janjikan gaji yang cukup besar jika San sanggup untuk menjadi pengawal bagi anaknya yang miliki sikap sedikit angkuh dan kurang ajar. Awalnya, San ragu. Ia tak pernah miliki pengalaman sebagai pengawal sebelumnya, terlebih menjadi pengawal anak SMA yang sedang nakal-nakalnya. Namun, katakanlah, ia gila uang sebab kebutuhan keluarganya harus ia tanggung sebagai tulang punggung keluarga, maka saat itu, tanpa ragu ia setujui permintaan Jung Ilwoo.
Dan di sinilah ia akhirnya, tinggal di pusat kota yang penuh keramaian, menjaga seorang anak dari pengusaha kaya raya. Dirinya yang awalnya ragu, menjadi tertarik dengan pekerjaannya di hari pertama ia dan Wooyoung dipertemukan di ruang kerja milik Jung Ilwoo. Kiranya, pekerjaan ini akan menantang, sebab pertama kalinya ia temukan anak dengan sikap sembrono dan lancang terhadap seseorang yang bahkan lebih dewasa empat tahun umurnya.
Tiga hari sudah ia lewati hari bersama Wooyoung di kediaman pemuda itu. Ia beberapa kali dapat teguran dari si pemilik rumah karena sikap dan perilakunya yang terkadang sedikit sesuka hatinya. San sedikitnya empat kali langgar aturan yang ditetapkan sendiri oleh Wooyoung di dalam rumah, namun tak pernah ia berpikir untuk menyerah. Ia harap dugaan Wooyoung yang disampaikan di hari pertama mereka bertemu tak akan benar-benar kejadian.
Ia harap umur pekerjaannya lebih lama dari satu bulan. Ia harap dirinya diberi banyak kesabaran.
Mobil senada langit malam itu meluncur di jalanan kota Jakarta menuju sekolah tempat Wooyoung tempuh pendidikan. Tadi pagi, syukurnya, pemuda itu mau ia hantarkan ke sekolah sebagai permintaan maafnya karena telah lancang lakukan hal yang tak seharusnya menjadi ranahnya. Jadi sekarang, kala telpon dari Wooyoung ia dapatkan, ia dengan segera tancap gas untuk jemput sang majikan.
Sekitar tiga menit ia menunggu di depan gerbang sekolah, kala akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga. Pemuda itu masuk ke dalam mobil dengan tergesa, kalakian tutup pintu dengan bantingan cukup kencang.
Ah, sikap kasar dan tak sabaran ini sepertinya memang sifat alami Jung Wooyoung. Namun hari ini, entah kenapa, sikap itu juga bercampur dengan rasa kesal. Terlebih kala akhirnya, San sadari pipi sebelah kiri pemuda itu terdapat lebam juga goresan kecil di dekat rahangnya, buat ia buru-buru menengok dan dekatkan badan.
“Pipinya kenapa? Kok lebam?”
Yang ditanya mendecak, kiranya tak suka San ikut campuri urusannya. “Buruan jalanin mobilnya!”
Namun, pemuda tinggi belum menyerah, ia kini angkat tangannya guna sentuh pipi pemuda kecil agar ia bisa leluasa lihat biru dan kemerahan yang menghias pipi kirinya.
“Kamu abis dipukulin?”
“Ribet lu, bangsat!” Tangan yang lebih tua ditepis kasar disertai decakan kesal. “Gak usah ikut campur urusan gue!”
Diteriaki demikian, buat San beri jarak yang sempat menipis di antara keduanya, tak ingin buat sang majikan merasa tak nyaman. Ia cukup lama diam, pandangi bagaimana pemuda di sampingnya pertahankan gurat raut kesal dengan telapak tangan yang berusaha tutupi sebagian pipi kirinya.
“Buruan jalan, nungguin apa lagi lu?!”
Akhirnya, setelah sekali lagi dapat teguran, San dengan segera lajukan mobil itu keluar dari pekarangan sekolah. Pandangannya sempat mengedar, berusaha lihat sekitar, berharap temukan seseorang yang mencurigakan—yang mungkin saja sebabkan kekacauan yang terjadi pada Wooyoung hari ini. Namun, nihil, ia tak temukan apa-apa.
Belum setengah jalan mereka tempuh, kala San hentikan mesin beroda itu di depan supermarket yang cukup dekat dengan sekolah. Dirinya tak tahan, melihat lebam dan lecet di wajah Wooyoung buat ia tak bisa fokus pada jalanan.
“Kenapa berhenti? Mau ke mana lu?” Tanya itu Wooyoung muntahkan, kala San tiba-tiba buka pintu mobil usai tarik rem tangan. Ia kebingungan.
“Beli P3K. Kamu tunggu bentar di mobil.”
“Kagak ya, gue gak nyuruh lu beli P3K! Masuk lagi, sini! Buruan, gue mau pulang!”
San tak indahkan, usai katakan, “tunggu bentar, gak akan lama,” pada pemuda kecil yang sudah tampilkan raut kesal, ia lantas segera keluar, tutup pintu, lalu berlari masuk ke dalam supermarket di depan.
Sial, Wooyoung benci jika San bertindak sesuka hatinya.
Namun, yang dilakukannya tetap diam dan menunggu. Sesekali mengumpat, muntahkan celoteh yang dituju untuk sang pengawal.
Hingga akhirnya pemuda tinggi itu datang bersama kotak putih dan satu botol air mineral. Masuk ke dalam mobil, lalu duduk di kursi pengemudi usai tutup kembali pintu. Dipangkunya kotak P3K itu, kala tangannya dengan gesit buka tutup botol air mineral. Dibukanya juga kotak di pangkuan, keluarkan satu kapas dari dalam sana, kalakian dituangkannya sedikit air di atas sana.
Ia menengadah setelah cukup lama tundukkan kepala, beri tatap pada Wooyoung yang diam-diam perhatikan tiap geriknya sedari tadi. “Coba sini pipinya, biar saya bersihin dulu lukanya sebelum dikasih obat merah.”
Pemuda itu sempat menolak awalnya dengan bilang bahwa ia bisa lakukan sendiri, nanti, di rumah. Namun, San terus-terusan memaksa dengan bilang dirinya bisa bantu sekarang juga, lantas yang dilakukan pemuda kecil hanya menurut walaupun dengan mimik wajah tak suka.
San tempelkan kapas dengan air mineral yang basahi permukaannya, guna bersihkan luka dan lecet di rahang pemuda kecil. Usainya, setelah luka itu sudah dirasa bersih, kalakian ia teteskan obat merah pada kapas yang baru. Lagi, ditempelkannya pada luka dan lecet di sana, dengan hati-hati tentunya, tahu itu akan terasa sakit setelahnya.
“Pelan-pelan, kek!”
Fokusnya belum juga buyar usai protes itu berkali-kali diperdengarkan guna beri peringatan padanya. Ia ambil kapas baru, tetesi obat merah untuk lebam yang berada di tulang pipi kiri. Lagi-lagi protes itu terdengar, namun San tak terlalu pedulikan.
“Abis berantem, ya? Apa dipukulin?”
“Bukan urusan lu.”
San terkekeh, “saya ini bodyguard-mu, loh. Kalau ada apa-apa harusnya bilang ke saya, biar saya bantu.”
“Lu pikir gue lemah? Gue apa-apa bisa sendiri.”
“Tapi Papa mu mau saya lindungin kamu.”
Decakan itu terdengar lagi, sudah yang ke berapa kalinya, San tak hitung sama sekali.
“Itu kan kemauan Papa, bukan gue.”
Keduanya sama-sama diam sekarang. Kerja tangan San yang obati luka di pipi Wooyoung kini sudah selesai. Dimasukkannya kembali kapas yang kotor ke dalam kotak putih di atas pangkuan, lantas ia simpan kotak itu ke dalam dashboard mobil usai letakkan sisa air mineral pada cup holder di samping kursi pengemudi.
Wooyoung lama terdiam usai San selesaikan kegiatan obati pipi kirinya. Ia sandarkan sikunya ke pintu mobil untuk dijadikan tumpuan dengan lengan yang tutupi sebagian wajahnya. Pandangannya lurus tatap apa saja dari jendela, hindari tatapan San yang berusaha pastikan Wooyoung sudah benar-benar baik-baik saja sekarang.
“Makasih,” katanya, masih dengan mata yang mengarah ke luar jendela. Sikap angkuhnya bahkan tak bisa hilang meskipun mulutnya tengah ungkapkan kata langka yang keluar dari sana.
“Sama-sama. Lain kali, langsung bilang aja kalau kamu butuh sesuatu ataupun perlu bantuan, saya dua puluh empat jam siap kapan aja.”
Usai beri gumaman atas kalimat San barusan, yang lebih tua lantas kembali lajukan mobil keluar dari parkiran supermarket. Kembali lanjutkan perjalanan menuju rumah dengan fokus yang sudah lebih baik sekarang.
0 notes
Text

001.
Sepatunya mengetuk lantai parket kayu berkali-kali, bentuk melodi kacau di dalam ruangan yang diisi tiga nyawa saling berhadapan. Satu nyawa yang duduk dengan angkuh di kursi kerja di balik meja mengkilap yang berisi tumpukan berkas di atasnya; beri tatap tajam padanya yang berdiri malas di hadapan si pria paruh baya. Nyawa satu lagi berdiri tegap disamping singgasana si pria, silangkan tangan ke belakang guna hormati nyawa paling tua di antara mereka bertiga.
Tiga menit ia berdiri di sana, beradu pandang dengan sosok di hadapannya. Matanya sesekali curi pandang pada sosok lainnya. Ia tebak umurnya tak jauh berbeda dengan dirinya, dilihat dari perawakannya yang terlihat masih sangat muda. Kala derak kursi yang didorong ke belakang pecahkan lamunan juga ketukan sepatunya, lantas dirinya alihkan pandangan ke lantai. Sedikit tegakkan tubuh, sebab ia tahu topik yang akan banjiri ruangan ini bukanlah topik basa-basi.
“Sudah ada sebelas orang yang mengundurkan diri menjadi bodyguard pribadimu, cuma karena sikap kurang ajar kamu ke mereka. I've never taught you how to behave, have I? Haven't you ever thought about how you've been acting all this time?”
Tatapan kosongnya ia arahkan pada satu nyawa yang baru saja muntahkan kalimatnya dengan kaki yang menyilang di atas kaki lainnya. Arogan sekali, pikirnya. Tak pernah sadar bahwa tatapan yang ia berikan juga sama angkuhnya.
“You think you've taught me anything? I grew up in a nanny's hands, not in yours.”
“Watch your words, Jung Wooyoung.”
Ingin ia muntahkan kata sekali lagi, namun akhirnya hanya decihan sinis itu yang keluar dari bilah bibirnya.
“Saya gak mau dengar laporan kalau kamu bersikap kurang ajar lagi ke bodyguard-mu yang baru. Kamu bukan anak raja, jangan bersikap semena-mena. Improve your attitude and never embarrass me as your dad!”
Anggukan kepala enggan bercampur rasa malas itu ia sertakan, hanya untuk sudahi ocehan sang Papa yang tak pernah sekalipun selipkan kata pujian untuknya dalam tiap kalimatnya. Satu kata pun bahkan tak pernah.
“Dia bodyguard baru mu.”
Lantas netranya ikuti arah pandang sang Papa, tatap pemuda berwajah tegas di samping kursi kerja di depan sana. Pandangan mereka bertemu, bertubruk satu sama lain. Ia beri seringaian kala pemuda itu tarik ujung bibir guna beri sapa padanya, memasang wajah ramah, namun yang ia lakukan malah sebaliknya. Tatapan lancangnya pandangi pemuda itu dari atas sampai bawah, sertakan seringaian yang masih melekat pada bibirnya.
“Salam kenal, Jung Wooyoung.”
Suara itu terdengar lembut, setidaknya lebih lembut dari suara derit kursi kerja sang Papa yang didorong kala pria itu beranjak keluar dari mejanya. Tatapan sang anak dan Papanya itu cukup lama bersabung dalam atmosfer tegang, dibiarkannya angkuh dalam kelereng jernih itu terobos manik jelaga miliknya, sebelum akhirnya sang Papa keluar ruangan usai muntahkan kalimat terakhirnya.
“Saya gak pulang sampai minggu depan.”
Ia rotasikan bola matanya disertai decakan. Lelah sekali. Hadapi Papanya dengan sikap angkuh dan arogan bukanlah hal yang mudah. Bebasnya belum pernah ia cicipi, dikekang dan dikurung di dalam sangkar bak burung hasil tangkapan. Namun, pria itu jarang sekali pulang ke rumah, dan dirinya, setidaknya, punya cukup waktu untuk rehatkan rungu dari ocehan juga celoteh sang Papa.
Matanya beralih tatap figur yang kini sudah beranjak menuju pintu, menunggu dirinya untuk ikut keluar dari ruang kerja sang Papa guna kembali ke rumah.
Lantas keduanya beranjak dari sana, keluar dari kantor milik sang Papa yang cabangnya sudah menyebar di beberapa kota. Naiki mobil dengan warna senada langit malam kala mencapai parkiran, kalakian mesin beroda itu dilajukan, membelah jalanan ibu kota yang tak pernah sepi.
Jung Wooyoung; pemuda berumur delapan belas yang baru rayakan ulang tahunnya bulan kemarin. Baginya, hidupnya tak lebih dari simulasi yang dibuat oleh sang Papa. Ia tumbuh dengan berselimut rasa sesal atas kematian sang Ibunda. Otaknya dicuci, ditanamkan rasa bersalah, sebab telah renggut nyawa wanita demi lahirnya ia ke dunia.
Sang Papa tanggung banyak rasa dendam atas kelahirannya. Kehilangan istri tercinta bukanlah hal yang mudah diterima oleh akal sehatnya. Lantas untuk limpahkan segala rasa sedih dan putus asanya, ia anggap sang anak satu-satunya sebagai produk gagal yang tak pantas ditunjukkan kepada dunia.
Ia tumbuh tanpa peluk identitas orang tua. Teman-teman sekolahnya tak pernah tahu dari kalangan mana ia berasal. Siapa sebenarnya orang tua dari anak yang kelakuannya begitu angkuh dan kurang ajar. Yang mereka tahu hanyalah rumor bahwa ia dari kalangan kelas atas, bukan dari keluarga sembarangan. Lantas, alasan itu pula yang menjadi penyebab dirinya tak miliki banyak teman. Mereka takut Wooyoung berasal dari keluarga mafia, yakuza, atau semacamnya. Memang tak masuk akal, namun, ia senang mendengar rumor itu tersebar. Setidaknya ia punya alasan untuk tidak bergaul dengan para penjilat di luaran sana.
“Papamu bilang saya bisa tinggal di rumah, tapi kalo kamu gak nyaman, saya sewa apartemen aja di sekitar sana.”
Ah, ia hampir lupakan nyawa lain yang sekarang tengah fokus pada kursi pengemudi di sampingnya. Wooyoung sejenak lempar tatapan pada pemuda itu, sebelum akhirnya pandangi jalanan di depan sana.
Pemuda di sampingnya adalah pengawal kedua belas yang disewa oleh sang Papa. Dimulai dari ia menginjak bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah, hidupnya selalu berdampingan dengan macam-macam pengawal. Rata-rata dari mereka, bekerja tak sampai satu tahun, sebab tak tahan akan sikap dan kelakuan sang majikan. Ia tak pernah keberatan, toh ini semua kemauan sang Papa. Ia tak pernah meminta disewakan seorang bodyguard selama delapan belas tahun dirinya hidup di dunia. Entah apa alasan pria itu, Wooyoung tak pernah tahu dan tak ingin juga cari tahu.
“Gak usah sewa apartemen, tinggal aja di rumah,” ia berkata, sejenak sandarkan punggungnya, selagi tangannya ia lipat di depan dada. “Palingan sebulan juga lu udah minta resign.”
Pemuda yang miliki rahang tegas itu beri gurat raut terkejut atas kalimatnya barusan, kiranya tak sangka kalimat demikian keluar dari bilah bibirnya.
“Kenapa mikirnya gitu?”
“Karena bodyguard yang kemaren kayak gitu semua. Pada gak tahan, katanya.”
Yang disampingnya beri tatap sejenak, sebelum kembali fokuskan pandangan pada jalanan di depan. “Karena sikapmu?”
Wooyoung angkat bahu dengan raut malasnya, “kayaknya. Lu—siapa nama lu?”
“Choi San.”
“Choi San? Kayaknya lu bodyguard termuda yang di-hired sama Papa. Lu baru lulus SMA kemaren lusa, ya?”
“Kebetulan saya udah lulus S1, sih.”
Ia terdiam. Cukup tak masuk akal baginya, sebab perawakan dan wajah Choi San terlihat masih sangat muda, seperti pemuda berumur sembilan belas tahun yang baru lulus sekolah kemarin lusa. Atau setidaknya, seperti pemuda yang baru injak dunia perkuliahan.
“Kalo kamu raguin kemampuan saya, saya gak dibayar cuma-cuma, kok. Saya bisa tinju dan taekwondo.”
“Such an arrogant.”
Senyum simpul itu diperlihatkan, terlihat sama sekali tak tersinggung atas kalimat Wooyoung barusan. Entah sosok itu ingin jaga sikap di hari pertama kerjanya, atau memang ia punya sejuta kesabaran yang mengalir di dalam tubuhnya.
“Mohon kerjasamanya, ya, Wooyoung. You can call me anytime if you need something.”
Lantas obrolan itu berakhir di sana. Wooyoung tak beri tanggapan apa-apa, hanya pandangi Choi San dengan tatapan malasnya. Semua mantan pengawalnya juga ucapkan kalimat demikian di hari pertama mereka, dan Wooyoung penasaran di hari keberapa pemuda di sampingnya itu akan nyatakan undur diri dari pekerjaannya sekarang.
0 notes
Text

Hey, you've done your best.
Sore itu, akhirnya, Salazar habiskan sisa harinya di kediaman Wave ditemani cookies dan susu hangat yang disiapkan oleh si pemilik rumah. Mengobrol selagi diri sandarkan punggung di sofa, menonton televisi yang tengah siarkan animasi. Lembayung senja diluar lengkap temani dua nyawa yang duduk bersisian, selagi masing-masing tangan genggam cookies yang sudah hampir tandas setengahnya di piring.
Salazar baru rasakan lagi perasaan ini sekarang setelah bertahun-tahun ia berpisah dengan Wave Joelian. Perasaan seolah tengah berada di rumah paling nyaman yang diisi hal-hal baik di dalamnya. Perasaan tenang seolah luruh segala masalahnya selagi punggungnya bersandar di sofa. Perasaan hangat kala sabung mata mereka bertahan untuk waktu yang cukup lama dari biasanya. Perasaan yang buat Salazar mengerti bahwa masih ada hal-hal kecil ini yang menjadi alasannya bertahan di dunianya yang hampir dipenuhi awan kelabu.
Kita, cookies, susu, dan acara televisi sore itu.
Hal kecil yang buat segala emosinya luruh, lantas digantikan oleh perasaan hangat dan juga tenang. Rumahnya bahkan tak pernah sehangat ini.
“Nanti bikin lagi, ya.”
Wave tolehkan kepala, beri tatap pada pemuda yang baru saja muntahkan kata usai masukkan seluruh cookies ke dalam mulutnya. “Bikin apa?” Tanyanya.
“Cookies. Nanti bikin lagi, tapi harus bareng aku.”
“Emang lu bisa bikin kue-kuean?”
“Jangan ngeremehin gitu, dong. Gini-gini juga aku suka bantuin Mama di dapur.”
Kekehan Wave lantas timbulkan senyum di wajah Salazar. Ia ingin sekali membuat kue kering bersama Wave. Pandangi pemuda kecil selagi fokus uleni adonan dengan wajah seriusnya; Salazar yakini adalah pemandangan yang akan sangat ia sukai.
Acara animasi di televisi masih terputar. Hembusan angin sore yang masuk dari celah-celah jendela sapa kulit mereka. Salazar dan sisa-sisa remahan di bibirnya, tiba-tiba hempaskan tubuh ke sofa dengan jadikan paha Wave sebagai bantalnya. Pemuda kecil jelas terkejut, mengerjap berkali-kali kala dapati wajah Salazar yang tersenyum tanpa dosa di bawah sana.
“Lu—bangun, gak!”
Pemuda tinggi nyatanya tak acuh sama sekali. Alih-alih kembali tegakkan tubuh kala dapat protes dari sang empu, pemuda itu malah pejamkan mata.
“Just a moment, please. I need it.”
Dan Wave tak bisa apa-apa kalau sudah begini. Ia dan gerak kikuknya yang datang tiba-tiba buat suasana di ruang tengah itu menjadi canggung seketika. Bukan salahnya lagipula, namun anehnya, ia merasa suasana ini tak akan bisa ia tanggung untuk waktu yang lama.
Ia lantas tundukkan kepala, pandangi wajah damai Salazar yang masih terpejam di atas pahanya. Ia baru ingat lagi kala ia pandangi wajah itu lamat-lamat; lebam kemerahan yang agaknya bekas sapaan kasar dari telapak tangan seseorang.
Diusapnya bekas kemerahan di pipi kanan pemuda tinggi, buat sang empu kerutkan alis kala dinginnya jemari Wave sapa pipi hangatnya. “Gak apa-apa,” katanya, tak ingin buat Wave terlalu cemaskan dirinya.
“Where did you get this?”
Mata pemuda tinggi kembali terbuka, beri tatap pada manik jelaga milik pemuda yang kini tengah tundukkan kepala guna pandangi wajahnya. “Didn't I tell you?”
“Gak ada yang namanya keserempet tembok, Sal. Gak mungkin lu lagi diem, tiba-tiba tuh tembok gerak nyerempet pipi lu. Nyari alasan yang masuk akal dikit.”
Salazar rasanya lagi-lagi ingin tertawa dengar celotehan kecil yang Wave tujukan untuk dirinya. Namun, ia sadar, Wave ingin topik ini dibahas dengan serius tanpa diselipi candaan sebagai jawaban. Lantas usai senyum tipis ia perlihatkan, pelan-pelan pemuda itu kembali muntahkan kalimatnya yang cukup panjang kali ini.
“I got this from Papa. Dia gak puas sama nilai dan peringkatku. Katanya, aku bisa aja masuk tiga besar kalau lebih rajin belajarnya. Katanya, kalau aku gini-gini terus gak akan bisa maju. It's all nothing, right? Everything I have achieved, it's all nothing, right?”
Wave belum sempat jawab tiap untaian bunyi bahasa yang Salazar ucapkan, sebab pemuda tinggi kembali lanjutkan kalimatnya lebih dulu.
“Kayaknya gak ada kata puas di kamus Papa. Kayaknya aku cuma investasinya doang. Kalo nanti akhirnya aku gak bisa kasih dia keuntungan, it's not impossible for him to think about selling me to a rental.”
“Hey, gak boleh ngomong gitu! You've done your best, tau. Kalau mereka belum bisa apreasiasi dan bangga sama apa yang lu raih sekarang, seenggaknya lu masih punya gue. I'm so proud of you, Salazar.”
Sabung mata yang lagi-lagi jebak mereka dalam sunyi sesaat usai kalimat Wave mengudara, hantarkan sengatan aneh pada tubuh Salazar. Wave dan senyum manisnya, pandangi dirinya dengan binar bening pada kelereng jernihnya; perpaduan yang amat menenangkan.
“I wish I can be proud of myself.”
“If you can't do it yet, let someone else do it for you.”
“Who's that someone else?”
Wave sejenak diam, pandangi bagaimana gurat raut penasaran di bawah sana menunggu untuk jawabannya. “Me. Sama kayak dulu, I will celebrate everything you get with your efforts, bahkan sesimpel lu dapat nilai seratus.”
Senyum itu merekah, mengembang bak bolu panas yang baru saja keluar dari oven. Wave sampai harus alihkan pandangan, sebab ditatap sebegitu dalamnya disertai senyum lembut milik pemuda tinggi buat dirinya diserang berjuta rasa yang tak bisa ia jelaskan lewat rentet kata.
“I will do the same to you,” kata pemuda tinggi, buat kelereng jernih milik pemuda kecil lagi-lagi terjebak pada tatap lembutnya.
“You must. Itu namanya timbal balik.”
“Sama kayak cinta antara dua pihak, ya. Kalau cuma satu yang jatuh cinta, berarti gak ada timbal balik di sana.”
Tawa Wave pecah, dengar Salazar selipkan kata cinta di obrolan mereka buat dirinya tak bisa tahan diri untuk tak tertawa. “Lu selain buaya darat, ternyata juga dangdut, ya, orangnya.”
“Apanya? Kita hidup berdampingan sama yang namanya cinta, tau, Wave. Don't laugh when I mention about love!”
Wave anggukan kepala berkali-kali dengan sisa tawanya, berusaha hentikan tawa juga senyum jahilnya. Ia hanya merasa lucu kala ia sadar bahwa sosok di bawah sana belum juga berubah, masih sama seperti dirinya yang dulu. Salazar yang lagaknya begitu paham tentang cinta dan sejenis kata untuk representasikan kasih sayang lainnya. Bahkan hingga dirinya menginjak usia remaja, Wave rasa ilmunya tentang hal semacam itu semakin bertambah.
“Lu pasti udah berpengalaman soal cinta-cintaan, ya? Salazar buaya kecil yang udah tumbuh gede ini gak mungkin gak ada pengalaman pacaran.”
“Pacaran? Jaman sekarang gak ada pacar-pacaran, langsung nikah dong kayak kita.”
Wave terbatuk, bukan main kagetnya kala untaian bunyi bahasa itu meluncur dengan santainya dari bilah bibir Salazar. “Maksud lu apaan, anjir?!”
Kekehan kecil itu dibuahi jitakkan keras di kepala, buat sang empu rapatkan bibir, tak ingin buat pemuda kecil mengamuk atas kalimatnya.
“Kita emang pernah nikah, Wave, kalimatku gak salah. Kamu lupa? Kita pernah ci—”
Dibekapnya mulut Salazar secepat mungkin sebelum kalimat ambigu lainnya serang kewarasannya. Wave jelas ingat, tak pernah lupa akan kejadian di masa lalu tentang mereka, si bocah ingusan, yang entah pikiran dari mana tiba-tiba tiru tindakan orang dewasa yang disebut menikah.
Memang sisi gila mereka.
“Gak usah bahas dua bocil gila itu.”
Yang di bawah sana lempar tatapan tajam sebab mulutnya masih dibekap telapak tangan pemuda kecil, tak diizinkan bicara sebab kalimatnya akan melantur kemana-mana.
Bahkan kala tangan Salazar terangkat untuk raih poni milik Wave yang menjuntai ke bawah, pemuda kecil belum juga lepaskan tangannya. Dibiarkan begitu saja sampai sisa remahan cookies di bibir pemuda tinggi sepertinya sudah bersih menempel ke telapak tangannya. Dan Wave pun tampaknya tak peduli, kala jemari itu sisir poninya yang mulai memanjang hari demi hari. Membeku dalam posisi itu sampai derak pintu buyarkan lamunan, bubarkan dua orang yang baru saja tenggelam ke dalam lautan jernih dalam kelereng masing-masing.
Kembali pandangi televisi, kala sapaan dari sang Mama yang baru saja pulang menjadi akhir dari sedikit momen yang direkam jejak jingga di luar jendela.
0 notes
Text
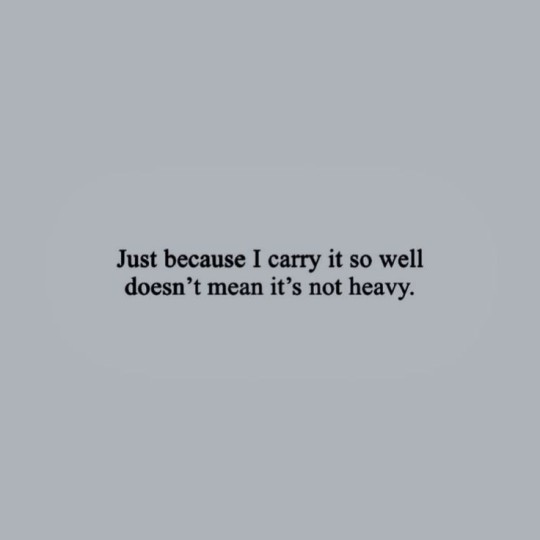
Is everything still not enough?
Kiranya, semua yang sudah ia lalui akan dihadiahi apresiasi manis dengan tepukan-tepukan kecil di kepala. Kiranya, segala cara yang sudah ia usahakan untuk raih nilai tinggi dan peringkat kelas akan dihadiahi pujian disertai segala macam kata-kata baik di dalamnya. Kiranya, rasa puas dengan senyum hangat akan dipamerkan kala ia umumkan isi rapornya yang sedikit banyaknya berisi angka sembilan puluh ke atas. Namun, nyatanya, besar harap dan ekspektasi yang ia angankan bahkan jauh dari perkiraan.
Papanya mengamuk. Di ruang keluarga yang atmosfernya hampir menghangat, Papanya teriakan sumpah serapah sebab sang anak belum bisa penuhi ekspektasi yang ia harapkan selama ini.
Salazar tak mengerti. Tak pernah bisa mengerti. Satu minggu ia lewati hari-hari tanpa ponsel dan alat komunikasi sama sekali. Bergelut dengan tumpukan buku, kejar segala materi yang ia lewatkan setengah tahun itu. Bahkan usainya, selama masa classmeeting, ia masih khawatirkan segala resiko dan konsekuensi yang akan ia terima jikalau seandainya, nilainya jauh dari ekspektasi sang Papa. Namun, semuanya tak seburuk itu sampai sang Papa keraskan suara untuk bantah apa yang sudah ia dapatkan atas segala usahanya.
Nilai rata-ratanya bagus, bahkan lebih baik dari tahun-tahun sekolahnya selama di Australia dulu. Ia raih peringkat kelima di kelas, berhasil raih lima besar yang kalau kata Wave; tak mudah untuk diraih murid pindahan dari luar negeri seperti Salazar.
Maka dengan sisa-sisa keberaniannya, ia pamerkan rapor miliknya di depan sang Mama Papa di ruang keluarga sore itu. Dan dari sanalah segala caci maki serta sumpah serapah itu bermula, digaungkan di ruang keluarga yang jika diingat-ingat kembali, tak pernah menjadi hangat sama sekali.
“Bangga sama nilaimu, ya? Cuma segini usaha kamu buat semester ini? You think that's enough, Salazar? Kamu seharusnya bisa masuk tiga besar kalau kamu lebih rajin belajarnya! Seharusnya Papa sita hape kamu dari dua minggu sebelum ujian!”
Lagi, teriakan itu digaungkan selagi jari telunjuknya tunjuk rapor yang beberapa saat lalu dihempas di atas meja sofa. Dua nyawa lain di sana tak bisa berbuat apa-apa selain diam dan dengarkan segala rentet kata yang dimuntahkan dengan segala penekanan pada tiap katanya.
Salazar tundukkan kepala, tegaskan rahangnya untuk halau segala emosi yang membuncah, selagi rungu tangkap semua kalimat sang Papa.
Ia muak.
Sedang Mamanya hanya bisa pandangi bagaimana sang suami lagi-lagi berusaha sakiti perasaan juga mental sang anak satu-satunya. Ia tak bisa berbuat apa-apa, ia tak punya kuasa untuk itu semua.
“Jangan jadi pribadi yang mudah puas, kamu gak akan bisa maju kalau kayak gitu. Semua nilai dan peringkat ini, kamu pikir cukup buat mendaftar di kampus terkenal dalam negeri?”
Tatap tajam serta menuntut itu menghunus tepat pada manik jelaga miliknya. Ia gelengkan kepala, enggan untuk buka suara, walau nyatanya ia ingin sekali bantah segala argumen sang Papa.
“Kalau tetap bodoh kayak gini, gimana bisa kamu lanjutin perusahaan Papa? Mau jadi apa perusahaan itu kalau kamu sendiri aja gak pernah mau maju?”
Cengkraman jari-jarinya menguat sertakan gelenyar tak nyaman di dalam dadanya. Ia hampir capai limit kesabarannya, namun pikirnya, sang Papa belum juga mengerti.
“Perusahaan gak akan maju—”
“Can you stop talking about that damn company?!”
Ia lepas kendali. Emosinya berhasil kuasa diri.
“Papa pikir aku peduli? I don't give a fuck about your company!”
PLAK!
Pipinya memanas. Tamparan yang dilayangkan begitu kerasnya ternyata berhasil sadarkan ia dan segala iblis emosi di dalam dirinya. Ia bak hilang kesadaran kala mulutnya muntahkan untaian kalimat serapah yang ditunjukkan untuk sang Papa.
Papanya berdiri, cengkram kerah seragam milik sang putra, dipaksanya untuk berdiri. “Bilang sekali lagi! Bilang sekali lagi di depan muka Papa!”
Salazar gemetar, nyatanya ia tak pernah kuat jika harus terlibat adu mulut bersama figur yang berdiri angkuh di hadapannya. Ia tak pernah berharap menjadi kurang ajar lalu rusak hubungan yang memang sedari awal tak pernah bisa akur selayaknya keluarga orang-orang. Namun, sisi lain dirinya seolah tak terima atas sikap semena-mena yang selama ini ia dapatkan dari kepala keluarga di rumah mereka.
“Aku capek, Pa. Papa pikir selama ini aku gak ada usaha? Ever since we went to Australia, you never cared about me or even the smallest things about me. All you cared about is my grades, family's reputation, and that stupid company!”
Helaan napas berat juga kasar terdengar dari Salazar. Kiranya lelaki itu masih berusaha untuk sabar, tak ingin buat sang Mama khawatir di ujung sofa di sana.
“Do you think it all makes sense? Kalau Papa mau semuanya sempurna, jangan berharap sama anak yang bahkan belum injak usia dewasa. Just go and build yourself a robot that can fulfill all your unrealistic expectations, 'cause I will never be!”
Untaian bunyi bahasa yang digaungkan dengan penuh penekanan itu ternyata berhasil pancing amarah Papanya. Tangan pria itu terangkat, sudah bersiap untuk layangkan pukulan pada tubuh Salazar, namun harus tertahan di udara kala teriakan sang Mama terdengar kencang di ruang keluarga.
“Don't ever think about hurting our child!”
Salazar terkekeh, beri seringaian pada sang Papa yang wajahnya sudah merah padam. “Go on. After all, I should have gotten it, right? Cuma karena rumah kita di sini gak ada basement, bukan berarti Papa gak bisa pukulin aku kayak dulu-dulu. You can do it here, in front of Mama.”
Kalimatnya sarkastik. Entah apa tujuannya muntahkan rentet kalimat seperti itu, ia juga tak mengerti. Dan akhirnya, yang ia dapati hanyalah tangis sang Mama yang terdengar sangat menyakitkan.
Wanita itu baru tahu semuanya. Semuanya. Semua siksa serta kekerasan yang selama ini sang suami berikan sebagai hukuman atas sikap sembrono sang anak selama di sekolah. Namun, yang paling menyakitkan adalah; bahkan sampai detik ini, ia masih belum juga mampu lakukan apa-apa selain tumpahkan segala tangisnya.
Di sana, sang Papa kembali beri tatap tajam pada Salazar setelah pemuda itu berhasil buat sang Mama menangis atas fakta yang ia muntahkan tanpa pikir panjang.
“Gak tau diuntung kamu! Mau sampai kapan kamu kurang ajar sama orang tua?!”
“Sampai Papa hargain semua usaha aku selama ini! Sampai Papa sadar kalau aku cuma remaja biasa dan belum bisa pikul semua ekspektasi tinggi Papa!”
Usai muntahkan kalimat terakhirnya, pemuda itu lantas beranjak dari ruang keluarga. Tinggalkan sang Papa dengan sisa amarahnya, serta sang Mama yang belum juga usai dengan tangisnya.
Tak ia pedulikan teriakan Papanya yang menyuruhnya untuk kembali menghadap dirinya. Ia lelah. Beradu mulut dengan pria yang tak pernah bisa hargai usaha anaknya bukanlah hal yang mampu untuk Salazar hadapi lebih lama.
Ia butuh tenang untuk setidaknya usir iblis emosi di dalam dirinya.
0 notes
Text

Have you been fine all this time?
Para nyawa mulai berhamburan keluar dari masing-masing ruangan usai kerjakan lembar-lembaran soal di hari terakhir ujian. Helaan napas lelah sekaligus lega lolos dari bilah bibir Wave kala akhirnya, setelah habiskan puluhan menit bergulat dengan soal penjas yang sebenarnya tak sesulit yang ia kira; ia bisa pulang dan bersantai di rumah.
Buru-buru pemuda itu bereskan apa-apa yang berantakan di atas meja, menyambar tas miliknya, lantas keluar ruangan dengan segera. Tinggalkan beberapa bebannya di sana. Setidaknya ia sudah berhasil lewati ujian satu minggu ini, urusan nilai biarlah menjadi urusan beberapa hari ke depan.
“Wave?”
Baru ia keluarkan ponselnya dari dalam tas, kala suara lembut namun juga tegas itu sapa dirinya setelah satu minggu tinggalkan asing pada rungunya. Salazar, lelaki itu berdiri di samping pintu, hentikan gerak serta langkah kaki Wave yang hendak keluar tapaki lorong kelas.
“Seminggu ini gimana? Aman?”
Untaian bunyi bahasa yang dimuntahkan dengan lembutnya itu buat Wave terbuai awalnya, hingga akhirnya ia sadar, seharusnya ia kesal pada sosok yang tengah buntuti dirinya sekarang. Aman, katanya?
Ia ketikkan beberapa pesan dalam ruang obrolan yang hanya diisi oleh tiga orang dalam aplikasi ponselnya. Ingin terlihat sibuk selagi tungkainya melangkah dengan terburu-buru, abaikan tiap tanya yang Salazar muntahkan padanya.
“Wave? Buru-buru amat, mau ke mana?”
Di anak tangga pertama, Salazar potong jalur Wave yang melangkah lebih dulu, halangi pemuda kecil dengan berdiri di anak tangga selanjutnya. Gerakan bola mata yang malas juga decakan sebal itu ia sertakan, berharap Salazar mengerti bagaimana suasana hatinya sekarang.
“Aku daritadi ngomong sama kamu, loh. Gak mau dijawab dulu pertanyaan basa-basinya?”
“Males basa-basi.”
Dan pemuda tinggi lantas segera mengerti. Suasana hati pemuda kecil tengah jelek sekarang, atau mungkin ada yang tak beres di antara keduanya hingga buat yang kecil beri jawaban jutek tak seperti biasanya.
“Hari ini ikut aku, aku traktir es krim.”
Alis yang menukik serta tatapan sinis lantas langsung Wave perlihatkan sebagai reaksi. Entahlah, dirinya tak sebegini kesalnya kemarin-kemarin, lalu kala dilihatnya wajah Salazar dengan senyum tanpa dosa serta tiap tanya basa-basinya; buat Wave sebal, entah kenapa.
Di lewatinya Salazar, lanjutkan langkahnya turuni anak tangga menuju lantai utama. “Lu kemaren-kemaren sombong banget tuh kayak orang gak kenal, ketemu gue juga langsung melengos. Terus sekarang kenapa tiba-tiba mau traktir es krim?”
Di belakangnya, Salazar bungkam. Ia tak ada niatan sama sekali bersikap demikian pada Wave satu minggu terakhir ini. Hanya saja, keadaan serta kepalanya berpikir untuk tidak taruh banyak perhatian pada hal lain selain fokus pada ujian dan nasib janji yang sudah Papanya gaungkan.
“Satu minggu ini emang aku ngehindarin semua orang, gak mau banyak interaksi dulu supaya fokus ujian.”
Ia kembali muntahkan kata setelah berhasil sejajarkan langkah di samping pemuda kecil yang kini beri tatap pada netra miliknya.
“Melengos ke gue kemaren itu juga sengaja?”
“Sorry. I thought it was better for my mind.”
“Maksudnya?”
“Aku gak mau kepikiran kamu, terus malah gak fokus belajar. Aku seminggu ini ngehindarin kamu karena takut gak kuat pengen ketemu, then end up ruin my study time.”
Kini Wave yang dibuat bungkam. Ia tak ingin percaya, namun semakin dalam kelereng jernih itu terobos manik jelaga miliknya, semakin yakin pula Wave bahwa semua yang Salazar lakukan bukan tanpa alasan. Ia seharusnya paham, ia seharusnya mengerti.
“Wave, sorry. I won't do it again. Yesterday was the last one, I promise.”
Dan akhirnya pemuda kecil itu luluh juga. Dari awal memang ia tak berniat marah lalu turut hindari Salazar seperti apa yang pemuda itu lakukan padanya. Ia hanya tak suka Salazar tiba-tiba hindari dirinya tanpa sebab, tanpa kata.
“You have promised me.”
“I have promised you.”
Senyum manis itu lantas perlahan-lahan mulai terbit, bak matahari yang akhirnya tampakkan diri usai usir mendung yang seharian ini tutupi bumi.
Sampai di parkiran, Salazar raih helmnya, dipasangkannya selagi bibir ucapkan rentet kata pada pemuda yang juga lakukan hal yang sama.
“Kita langsung ke rumah kamu, ya, nanti aku sekalian titip motor di sana. Ke tempat es-krimnya kita jalan kaki aja.”
Wave menoleh usai tatap pantulan wajahnya di kaca spion, untuk pastikan helmnya sudah terpasang dengan benar. “Gak apa-apa langsung main? Orang tua lu marah gak nanti?” Tanyanya, sedikit takut wacana mereka setelah ini malah akan timbulkan masalah.
“Gak apa-apa, aman, kok. Ujiannya juga udah selesai.”
Setelah Wave beri anggukan, keduanya lantas mulai tunggangi mesin beroda milik masing-masing. Kalakian, keluar dari parkiran, lantas belah jalanan siang itu dengan Wave yang memimpin jalan.
Padahal niat awalnya, Salazar ingin jemput Wave tadi pagi agar nantinya mereka bisa tunggangi satu motor bersama. Agar bisa dengan mudah mereka mengobrol selagi Salazar kendarai mesin beroda itu tanpa perlu takut kendaraan lain akan terganggu. Namun, nyatanya ia bangun kesiangan dan harus buru-buru sampai ke sekolah sebelum pagar dikunci, lalu kacaukan segala yang sudah ia siapkan dari jauh-jauh hari.
Namun, begini saja tak apa.
Butuh waktu lima belas menit untuk keduanya sampai di kediaman keluarga Wave. Parkiran masing-masing motor di dalam garasi yang tak begitu luas, lalu kembali ke pekarangan usai lepaskan pelindung kepala.
Wave yakin hari ini Mamanya akan kembali pulang malam, seperti biasanya. Jadi, sebelum ia kelupaan, lelaki itu merogoh saku untuk cari kunci rumah, lalu masuk ke dalam dengan terburu-buru. “Bentar, gue angkat jemuran dulu.”
Di depan pintu, Salazar berdiri perhatikan Wave yang berlari gesit naiki tangga guna angkat jemuran yang dijejerkan pada braket besi di balkon lantai dua. Beberapa saat kemudian, ribut suara langkah kaki terdengar, lantas pemuda kecil kembali muncul bersama satu keranjang pakaian yang cukup besar, buat kakinya turuni tangga dengan meraba-raba, sebab pandangannya tertutup keranjang rotan di dalam pelukan.
Salazar baru akan lepaskan sepatu guna masuk untuk bantu pemuda kecil, namun pemuda itu sudah lebih dulu tolak tawarannya dengan bilang, “gak apa-apa. Bisa, kok, bisa.”
Dan pemuda tinggi akhirnya tetap berdiri di sana sampai pemuda kecil kembali keluar, dikuncinya kembali pintu, lantas ia pimpin jalan menuju tempat yang menjadi tujuan mereka; toko es krim dekat taman komplek.
Namun, belum sampai lima langkah tungkai mereka melangkah, pemuda tinggi maju ke depan lantas buat pemuda kecil tertinggal di belakang.
“Biar aku yang pimpin jalan. Tempatnya masih sama, kan?”
“Sama. Banner-nya doang yang beda.”
“Okay, follow me.”

“Sudah lama nih Nak Wave gak main ke sini, sekolah gimana, Nak Wave?”
Sapa hangat sekaligus tanya tata krama itu hadir dari pria tua dengan rambut yang sudah hampir sepenuhnya memutih. Selagi tangan ulurkan dua es-krim dengan rasa berbeda, senyum ramahnya pun ikut serta sebagai pelengkap untuk pelanggan setianya yang sudah absen dari lama.
Wave kemudian lakukan hal yang sama, balas dengan tarikan ujung bibir selagi kedua tangannya terima uluran dua es-krim dari pria di balik konter.
“Iya, Abah, lagi sibuk belajar kemaren. Ini baru aja beres ujian.”
“Oh, iya, sudah masuk ujian ya minggu ini.”
“Iya, Abah.”
Lantas usai lempar senyum dan ucapkan terimakasih, keduanya kembali telusuri jalanan menuju taman komplek yang sepi siang ini. Mungkin karena sekarang waktunya anak-anak kecil tidur siang, jadi taman bermain itu terbengkalai sampai sore nanti.
Wave berbalik saat hampir capai pertengahan jalan, hampir lupakan es-krim di tangan serta Salazar yang diam pandangi ia di belakang. Diulurkannya satu es-krim rasa semangka yang Salazar pesan, lantas segera disambut oleh yang lebih tinggi.
“Kamu gak mau cobain dulu es-krimnya?” Tanyanya, kembali ulurkan es krim yang baru saja ia sambut dari tangan Wave. “Nanti gantian aku cobain es-krim durian punya kamu.”
Dan tanpa paksaan, Wave cicipi es-krim rasa semangka milik Salazar. Rasanya masih sama, jelas, ia sudah beli es-krim dengan varian yang sama berulang kali. Namun, kala Salazar beri tawaran untuk cicipi es-krim miliknya, entah kenapa Wave tak menolak sama sekali. Lantas kemudian, Salazar lakukan hal yang sama. Sedikit menunduk untuk cicipi es-krim rasa durian milik Wave.
“Rasanya kayak durian.”
“Ya, 'kan, emang durian!”
“Ternyata duriannya kerasa banget di lidah, kirain bakal dominan rasa susu. Tapi enak, kok.”
Komentar dari Salazar hanya Wave beri anggukan, sama sekali tak setuju, sebab pikirnya rasa durian di dalam es krim itu sudah pas dan tak berlebihan. Salazar saja yang tak suka dengan rasa durian.
“Abis ini enaknya ngapain, ya?”
Tanya itu dimuntahkan kala kaki berhasil tapaki taman. Pemuda kecil beringsut naiki jungkat-jungkit di pojok taman bersama es-krimnya yang sisa setengah, sebelum akhirnya untaian bunyi bahasa ia udarakan guna beri jawab atas pertanyaan pemuda tinggi barusan.
“Main sama gue. Lu udah berapa lama gak main ginian? Perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, jaring laba-laba, udah berapa lama gak main itu semua?”
“Terakhir main semuanya bareng kamu, sebelum aku pindah waktu itu,” katanya, selagi kaki susul tempat di mana Wave tengah berada sekarang. Ia duduk di sisi satunya, di sisi kanan jungkat-jungkit yang kini sejajar setelah ia dudukkan diri.
Cukup lama mereka bertahan dengan posisi seimbang, habisi es-krim masing-masing di tangan, sebelum akhirnya Wave lebih dulu gunakan bobot tubuhnya guna buat jungkat-jungkit itu terangkat di sisi yang tengah Salazar duduki sekarang. Senyum jahilnya ia pamerkan, puas sekali melihat wajah panik Salazar kala tubuhnya tersentak ke atas.
“Your life must be boring.”
Jungkat-jungkit itu perlahan mulai bekerja dengan seimbang, turun-naik teratur atas kerja sama keduanya. Senyum tipis Salazar muncul usai dengar rentet kata Wave barusan, tak mengelak sama sekali.
“It's boring because there's no you.”
“I've had a big impact on your life, haven't I?"
Tawa ringan milik pemuda tinggi diperdengarkan, “oh, it's annoying when you say it directly, but yeah, you are not wrong, though.”
Pemuda kecil lantas ikut tertawa, tak sangka Salazar akan tanggapi dengan serius kalimatnya barusan. Entah kenapa ia suka sekali menggoda Salazar akhir-akhir ini. Entah ini termasuk inner child-nya atau berlebihan jika ia katakan demikian, namun saat goda pemuda tinggi buat ia kembali menjadi sisi kecilnya yang sempat mati.
“Salazar?”
Keduanya sontak tolehkan kepala kala suara lain menginterupsi obrolan kecil mereka. Menghentikan laju jungkat-jungkit yang tengah diduduki, lantas Salazar kembali berdiri, langkahkan kaki keluar dari sana untuk kemudian dekati sosok pemuda tinggi yang datang menghampiri.
“Roki?”
“Oh, wow, masih inget gue ternyata. Kirain udah lupa.”
Di sisi kiri jungkat-jungkit yang kini jatuh pada sisi yang tengah ia duduki, Wave pandangi dua orang yang tengah berdiri dengan tatap dingin sebagai tembok pemisah yang coba Salazar bangun tinggi-tinggi.
Salazar masih ingat dengan jelas bagaimana sosok Roki di kehidupannya dulu. Sosok pemimpin geng anak SD yang masih labil dan nakal. Mereka tak berteman baik, namun tak pula bangun hubungan yang buruk selama mereka berada di sekolah yang sama enam tahun silam. Namun, mengingat bagaimana cara Roki bersikap tak adil pada Wave dulu, buat Salazar harus bentangkan jarak aman agar tak pemuda itu lewati batas wajarnya.
“Udah lama balik ke sini? Australia gimana?”
“Udah mau lima bulan. Australia? Nothing special, though.”
“Lu sekarang lanjut sekolah di mana?”
“Satu sekolah sama Wave.”
Saat dengar nama Wave disebutkan, Roki sontak tolehkan kepala, beri tatap pada pemuda kecil yang masih setia duduk di atas jungkat-jungkit di sana. Ia beri senyuman ramah, sebelum akhirnya kembali muntahkan kata.
“Awet banget pertemanan kalian. Wave, you must've missed him every day, right?”
Wave tetap bungkam, enggan jawab tanya yang Roki udarakan dengan seringaian yang sangat menjengkelkan. Dan Salazar jelas sadar, Wave sama sekali tak nyaman dengan kedatangan Roki yang ganggu waktu bermain mereka. Hendak ia ucapkan kata sopan untuk usir tamu tak diundang di hadapannya, namun yang bersangkutan sudah lebih dulu pamit undur diri sebab ponselnya yang tiba-tiba berdering nyaring.
“Gue duluan, ya, sorry ganggu waktu kalian berdua.”
Lantas punggung itu menjauh menuju kedai minuman di dekat pertigaan. Tinggalkan mereka berdua, tinggalkan suasana canggung yang sebelumnya tak pernah ada. Wave berdiri dari sana, beringsut naiki jaring laba-laba hingga bagian paling atas. Ia duduk di sana dengan mata yang menyipit akibat silau, sebelum akhirnya disusul oleh Salazar.
“Dia gimana selama ini?”
“Hah?”
Salazar cari posisi yang nyaman di samping Wave, duduk di bagian paling atas jaring laba-laba, bersabung mata cukup lama dengan jarak yang cukup dekat. Salazar bahkan bisa rasakan napas berat dan panas milik Wave yang dihembuskan dengan sedikit terengah-engah.
“Roki, gimana dia selama ini? Aku tau dia gak cukup baik sama kamu selama kita SD dulu. Gimana dia sekarang? Gak pernah jahat ke kamu lagi, 'kan?”
Cukup lama Wave tenggelam pada kelereng jernih penuh rasa khawatir milik Salazar, bak tersihir atas binar yang sialnya baru ia sadari beri banyak sinar kala manik jelaga itu tatap dirinya. Sebelum akhirnya ia beri gelengan, masih dengan sabung mata yang belum juga usai.
“Have you been fine all this time?” Tanya Salazar lagi, sekadar untuk memastikan.
“Are you worried about me?”
“Of course, I am!”
Wave terkekeh, beri sentilan kecil pada dahi Salazar, lantas buat sang empu tampilkan gurat raut kesal. “You think too much about me.”
0 notes
Text

Semua sikap itu muncul lagi.
Baru Wave tapaki jalanan menuju gedung kelas usai parkirkan motornya, kala nyawa lain datang lantas halangi jalannya. Senyum cerah bagai matahari pagi bersama lekukan alami lesung pipi beri sapaan hangat untuk ia yang sudah munculkan gurat raut masam di pagi hari.
Kedatangan tiba-tiba Salazar yang patahkan langkah Wave lantas datangkan decakan sebal, pun raut masam itu semakin dominasi wajah manis pemuda kecil.
“Mataharinya belum muncul, nih, masam banget jadinya pagi-pagi,” godaan itu Salazar muntahkan guna goda Wave yang kini benar-benar hentikan langkah kaki. “Kenapa pagi-pagi udah masam mukanya?”
“Males, gak dibikinin Mama sarapan.”
Wave dan gurat raut masamnya justru buat Salazar merasa lucu. Jarang sekali lelaki itu tunjukkan raut wajah seperti itu, atau sebenarnya Salazar saja yang sudah lama tidak melihat wajah ekspresif milik Wave.
Senyum pemuda tinggi terbit, sebelum tangannya raih sesuatu di saku celana, kalakian dikeluarkan, dibuka bungkusnya, lantas disodorkannya tepat di depan bibir pemuda kecil.
“Aaa...c'mon, pesawat mau masuk.”
Lantas dengan segera Wave terima sodoran permen rasa stroberi-krim pemberian Salazar, buat senyumnya mulai terbit gantikan raut masam beberapa saat lalu.
Kenapa sikap lelaki itu manis sekali pagi ini?
“Suka?”
Anggukan kecil itu dibalas senyum yang jauh lebih hangat, seolah tak ada kesempatan baginya untuk tidak pamerkan senyum barang sedetik pun jika di hadapan pemuda kecil.
Dan Wave justru kebingungan atas semua sikap manis Salazar, kiranya sikap dingin yang lelaki itu tunjukkan di hari pertama mereka bertemu kembali beberapa bulan lalu ialah sikap permanen yang tak akan bisa menghangat oleh apapun. Namun, Wave kemudian ingat satu hal kini; Salazar dan semua ingatannya telah kembali.
Lalu, apa yang salah? Toh, sedari dulu lelaki itu sudah pandai bicara dan tak luput dari sikap manis yang ia punya. Wave saja yang belum terbiasa.
Kini mereka bawa masing-masing tungkai untuk kembali tapaki koridor menuju gedung kelas di lantai dua. Berjalan bersisian dengan celoteh kecil Salazar guna usir canggung serta perbaiki suasana hati Wave yang sedikit buruk pagi ini.
“Gue bawa bekal, nanti kita makan bareng, ya?”
“Lu bawa bekal apa?”
“Sandwich. Kamu suka sandwich?”
Dan kembali lagi, Salazar dan bahasa rancunya. Wave terkadang bingung, sebenarnya sama sekali bukan masalah, namun bahasa rancu yang lelaki itu gunakan selalu buat ia kebingungan.
Wave tatap pemuda tinggi di sampingnya usai keluarkan permen dari dalam mulutnya. “Lu labil terus, ya, Sal.”
“Hah? Maksudnya?” Gurat raut bingung itu diperlihatkan, tak paham sisi mana dirinya yang disebut labil oleh pemuda kecil.
“Lu labil. Kemaren gue-lu, sekarang aku-kamu. Now you call yourself 'gue', then you call me 'kamu'. Besok-besok pasti berubah lagi. Labil.”
Dapat protes dari yang lebih kecil buat Salazar tertawa, entah apa yang lucu, tapi dengar Wave dan gerutu kecilnya buat Salazar tak tahan. Selalu lucu.
“Kamu sukanya yang mana?”
“Terserah,” katanya, kalakian masukkan kembali permen di tangan ke dalam mulutnya.
“We used to use 'aku-kamu', thought. So what's wrong with using our old little habits?”
Wave beri tatap pada Salazar di sebelah, tak disangka Salazar ingat semua detail kecil tentang mereka. Sebenarnya tak masalah, namun rasanya aneh jika ia ikut biasakan diri gunakan kebiasaan kecil mereka yang dulu.
“Then, go ahead. I don't mind.”
“Kamu juga harus gitu, biar balance.”
Bruk!
Bunyi sesuatu yang jatuh dari arah belakang, lantas interupsi obrolan kecil mereka. Keduanya hentikan langkah, berbalik ke belakang, kalakian temukan Violin yang tengah berjongkok, pungut bukunya yang jatuh.
Wave sontak maju, bantu pungut buku terakhir yang tergeletak di lantai, lantas diberikannya pada gadis dengan surai sepundak.
“Thank you, Wave. Duluan, ya!”
Senyum cerah dan lambaian tangan itu Violin tujukan kepada Wave, sebelum akhirnya ia lanjutkan jalan lebih dulu, abaikan Salazar yang beri tatap dengan binar rasa bersalah.
“Kok dia cuma nyapa gue? Lu sama Olin lagi berantem?”
Pertanyaan dari pemuda kecil lantas distraksi pandangan Salazar untuk kembali fokuskan diri pada jalanan di depan.
“Gak lagi berantem, kok.”
“Pacar lu ngambek?”
Mata Salazar membola dengan kedua alis yang terangkat ke atas usai dengar untaian bunyi bahasa yang dimuntahkan dengan begitu santainya. Ah, ia hampir lupa dengan yang satu ini.
“Awas tangga,” katanya beri peringatan, alih-alih jawab pertanyaan Wave barusan.
Dan celoteh kecil itu berhenti sampai di sana. Salazar masih enggan jawab pertanyaan barusan, pun Wave segan untuk bertanya ulang. Kiranya Salazar tak nyaman dengan topik terakhir mereka, jadi lebih baik ia diam sekarang.
Hingga tungkai mereka capai kelas dan daratkan diri pada tempat duduk masing-masing, hening itu belum juga pecah lantas mengakar di antara keduanya. Tinggalkan rasa sesal pada diri Wave karena sudah lancang muntahkan tanya yang kiranya buat Salazar tak nyaman.
0 notes
Text
“Halo?”
“Iya, halo.”
“Ini bener Wave, kan? Wave Joelian, kan?”
“Iya, beneran. Kenapa, dah, Sal?”
“Oh, beneran. Gak apa-apa, sih, gue parno aja takut yang ngangkat setan.”
“Bjir, maksud lu?”
“Bentar, jangan marah dulu. Gue parno takutnya daritadi cuma halu, takut pas nelpon yang ngangkat ternyata bukan elu...”
Wave tertawa, merasa lucu dengar kalimat Salazar barusan.
“Kenapa ketawa?”
“Lucu. Lu penakut, ya?”
“Gak, tadi cuma parnoan aja.”
“Sama aja.”
“Beda.”
“Sama!”
“Iya, sama.”
Di seberang telepon, Salazar tersenyum, mengalah sebab ia tahu debatan kecil itu tak akan berhenti sebelum dirinya yang mengalah lebih dulu. Lima detik hanya diisi dengan deru napas masing-masing, lantas kemudian Salazar kembali udarakan pertanyaan, tak izinkan sunyi ambil alih.
“Wave, masih suka chupa-chups?”
“Masih.”
“Paling suka varian apa?”
“Stroberi-krim sama lemon-limau.”
“Gak berubah ya berarti. Dulu kamu juga sukanya varian itu, kan?”
Wave sejenak diam, merasa aneh, sebab Salazar yang masih ingat varian permen kesukaannya. Wave bahkan baru sadar bahwa dari dulu hingga sekarang, ia masih suka permen dengan varian stroberi-krim dan lemon-limau. Dan satu hal lagi, ada apa dengan cara bicara Salazar?
“Wave?”
“Hm?”
“Ayo cerita, jangan diem aja. Gue kehabisan topik...”
Lagi-lagi tawa itu diperdengarkan, namun kali ini lebih terdengar seperti kekehan.
“Mau cerita apa? Mau gue dongengin apa gimana?”
“Apa aja. Cerita soal lu juga gak apa-apa. Gue pengen tau apa aja yang udah gue lewatin selama kita pisah dulu.”
Dan Wave tiba-tiba ragu. Ada banyak hal yang belum pernah ia ungkap kepada Salazar tentang dirinya yang dulu. Ada sedikit banyaknya hal yang belum Salazar tahu. Namun, untuk ungkapkan semuanya sekarang, Wave rasa dirinya belum benar-benar siap akan hal itu.
“Boring. Hidup gue gitu-gitu aja dari dulu. Tapi lu harus tau ini. Masih inget warnet tempat kita main dulu?”
“Iya, masih. Yang penjaganya katanya duda anak satu itu, kan?”
“Iya, bener. Lu tau gak, beliau nikah lagi sama janda muda kaya raya!”
“Serius?”
“Iya, serius. Semenjak itu warnetnya tutup, terus beliau buka toko elektronik.”
“Terus kamu jadinya pindah ke warnet lain?”
“Enggak, sih. Abis lu pindah gue udah gak main ke warnet lagi.”
“Terus mainnya ke mana?”
“Gak pernah main lagi, gue sibuk bimbel.”
Kembali sunyi. Salazar belum juga lempar tanggapan usai kalimat terakhir dari Wave. Namun, sepertinya energi Wave malam itu sedang full, jadi sekali lagi ia udarakan kalimatnya, belum ingin obrolan via telepon itu berakhir.
“Toko es-krim yang deket taman komplek itu sekarang makin rame, tau. Kemaren gue ke sana, rame banget, ada anak-anak TK. Kayaknya gak jauh dari sana ada TK baru, jadinya anak-anak TK mainnya pada ke sana.”
“Hmm...? Toko es-krim rasa semangka, ya?”
Suara Salazar kini terdengar sedikit lebih lembut, namun parau.
“Iya, dulu kita suka beli yang rasa semangka. Banyak varian baru sekarang, ada rasa durian sama banana juga.”
“Umm...durian? Aku gak suka durian...”
“Padahal enak, loh. Rasanya gak kayak durian banget, baunya juga gak yang nyengat banget gitu.”
“Um? Enggak?”
“Iya, enggak.”
“Umm...”
“Sal, ngantuk? Tidur aja kalo udah ngantuk.”
“Jangan, dong...”
“Hah? Jangan apa?”
“Jangan dimatiin. Nanti aja, jangan dimatiin...”
“Iya, gak dimatiin. Lu kalo mau tidur gak apa-apa, gak gue matiin teleponnya.”
“Hu’um...”
Setelahnya, hanya deru napas yang bisa Wave dengar dari panggilan mereka. Kiranya, yang di sebrang sana sedang konsentrasi jemput alam bawah sadarnya, lantas Wave-pun ikut diam. Berbaring di atas kasurnya dengan ponsel yang diletakkan di samping kepala, menunggu sesaat hingga kantuk hampiri dirinya.
“Sal? Udah tidur?”
Tak ada jawaban, dan Wave bisa simpulkan bahwa yang di seberang sudah benar-benar terlelap sekarang.
“Gue matiin teleponnya, ya? Good night.”
Setelahnya, Wave ikut pejamkan matanya usai matikan panggilan dan ucapkan selamat malam pada Salazar yang sudah terlelap di seberang sana.
0 notes
Text

Strange.
Dari awal Salazar menjemputnya tadi pagi, hingga jam istirahat siang ini, lelaki yang lebih tinggi tak kunjung berhenti beri tatapan aneh. Entah hanya Wave yang terlalu percaya diri atau memang benar kelereng jernih itu tak pernah lepas menguncinya bahkan saat pelajaran tengah berlangsung di dalam kelas. Ia bahkan bisa rasakan tatapan itu menembus leher belakangnya.
Namun, sepertinya Wave tak hanya sedang keegeran, saat tengah belajar beberapa jam lalu, dua kali Salazar dapat teguran dari guru yang mengajar sebab lelaki itu tak taruh fokus pada papan tulis di depan. Dan bahkan saat mereka sampai di meja kantin usai dapatkan dua mangkuk pangsit udang di konter makanan, manik jelaga milik Salazar belum juga usai pandangi Wave di hadapannya.
“Tumben pesannya pangsit udang.”
Bunyi bahasa yang keluar dari bilah bibir Wave akhirnya pecah sunyi di meja makan tempat mereka duduk sekarang. Lantas buat yang di depan menengadah usai suapkan satu pangsit udang ke dalam mulut.
“Pengen coba makanan kesukaan kam—lu.”
Wave sejenak diam, balas tatapan Salazar yang lagi-lagi kunci maniknya begitu dalam. Sebelum akhirnya buang pandangan, kemudian beri anggukan kepala untuk respon kalimatnya barusan. “Pangsitnya hari ini agak kurang asin.”
“Iya? Biasanya gak gini, ya, rasanya?”
“Iya, hari ini agak hambar.”
Salazar beberapa kali beri anggukan, baru sadar rasa pangsit yang tengah mereka santap sedikit kurang sedap sebab kurang garam. “Mau ganti menu, gak?” Katanya.
“Hah? Gak usah, lah, gak apa-apa masih enak kok ini.”
Akhirnya Salazar diam setelah sejenak tarik sudut bibirnya. Kembali lanjutkan makan dengan damai, lupakan rasa kurang asin dari pangsit yang ia makan. Namun, lagi-lagi matanya fokuskan Wave sebagai objeknya, rekam tiap gerik yang tengah lelaki itu lakukan.
Wave jelas sadar, mata itu seolah tengah telanjangi dirinya, buat ia salah tingkah dan tiap geriknya terasa salah.
Menelisik beberapa hari yang lalu, ia masih dibuat khawatir sebab dapati Salazar pingsan di taman kecil dekat rumahnya. Ia dan Sadam akhirnya bawa lelaki itu ke rumah sakit, dan di sana Salazar dirawat selama tiga hari. Wave tak bohong kala rasa khawatir itu serang dirinya, ingin jenguk lelaki itu keesokan harinya namun batal, takut akan orang tua Salazar yang ia tahu tak lagi senang akan kehadirannya. Dan hingga hari ketiga Salazar menginap di rumah sakit, Wave dapati lelaki itu ketuk pintu rumahnya, datang dengan setelan piyama rumah sakit dan punggung tangan yang berdarah.
Wave rasa kala itu Salazar tengah gila, ucapkan ribuan kata maaf kepadanya, lantas peluk dirinya serta tangis yang ditumpahkan bersama rasa bersalah. Katanya, akhirnya, ia dapatkan kembali ingatan miliknya yang membeku selama beberapa bulan lamanya. Katanya, ia akhirnya ingat kembali dengan sosok Wave dan mungkin itulah yang membawa lelaki itu kabur dari rumah sakit hanya untuk temui dirinya.
Wave belum pernah lihat sisi gila dari Salazar yang bertahun-tahun ia kenal. Jadi saat lelaki itu lakukan hal yang diluar batas wajar, Wave akhirnya sadar bahwa ia hanya tahu Salazar yang berumur sepuluh.
Dan di depannya sekarang, bukan lagi Salazar yang ia kenal. Bukan lagi Salazar yang selalu bertindak wajar demi hindari hal-hal buruk yang akan datang di masa depan.
“Don't look at me with those eyes.”
“Hm? What eyes?”
Wave jengah, ditatap seharian ini oleh Salazar rasanya melelahkan. Wave mungkin berlebihan, namun cara Salazar menatapnya dengan senyum tipis bak seringaian, buat kewarasannya menghilang.
“Keep staring at me like that, you'll go home alone!”
Pangkal alis yang lebih tinggi terangkat, pasang raut memelas dengar tutur kata Wave barusan.
“Why thought? Staring at you is illegal?”
“Not like that. I mean, it's strange...”
Kekehan ringan itu mengudara, terdengar jelas bahkan ditengah bisingnya kantin siang ini. Wave tak tahu apa yang lucu dari kalimatnya barusan, tapi Salazar terkekeh bak tengah tonton lawakan sore.
“Gue biasanya emang gini.”
“Enggak, lu biasanya gak gini. Lu biasanya gak mau liat gue.”
Sisa kekehan serta tarikan sudut bibir itu kemudian hilang. Wajah Salazar kembali datar, namun tatapnya masih kunci manik Wave di depan.
“Waktu itu gue masih bego. Sekarang udah gak, udah inget lagi sama lu soalnya.”
Dan senyum itu kembali merekah, lebih lebar dari yang sebelumnya, hingga buat kedua mata itu menyipit sertakan lengkungannya.
Dan Wave beku, kiranya terpanah senyum manis milik lelaki di hadapannya.
0 notes
Text

The first time they met.
Yolin tak tahu bagaimana awalnya, tak pula sadar saat motor miliknya yang dikendarai oleh sang sepupu berhenti di jalanan kosong dekat jembatan. Tujuan awal mereka ialah pergi ke salah satu mall di jantung kota, namun malah berakhir di kerumunan murid-murid yang tampaknya sebaya.
Ia ikut turun dari motor miliknya kala Tio—sang sepupu—dengan buru-buru matikan mesin, kalakian beranjak menuju kerumunan anak-anak yang baru Yolin sadari kenakan seragam yang sama seperti milik sang sepupu.
“Tio, mau ke mana? Kenapa berhenti di sini?!”
Yolin dengan cepat menghindar kala Tio lemparkan rantai besi berukuran cukup besar yang baru saja sepupunya keluarkan dari dalam tas miliknya. “Jangan banyak tanya, ambil rantainya! Ikutin gue!”
“Apaan, bangsat! Lu mau tawuran?!”
Segerombolan anak-anak yang kenakan seragam sekolah berbeda tiba-tiba datang menyerbu dari arah depan, tanpa sempat Yolin dengar jawaban dari Tio, tanpa sempat ia cerna situasi yang hendak ia hadapi ke depannya.
Sialan, ia dijebak oleh sepupunya sendiri.
Dalam hitungan detik segerombolan anak-anak itu sudah memisahkan diri, mengepung ia dan belasan teman-teman Tio di bawah jembatan jalan kosong itu. Puluhan kerikil dilempar sembarang arah, tak peduli mengenai siapa saja, lawan ataupun teman sendiri.
Kesadaran yang sempat melayang kembali jatuh ke dalam tubuh kala kerikil kecil mengenai pelipis sebelah kiri Yolin, buat ia buru-buru bergerak dari sana, mencari tempat untuk sembunyi.
Kepanikannya bahkan buat ia menjadi bodoh sampai tak sadar bahwa ia bisa langsung pergi dari sana dengan motor miliknya. Namun yang dilakukannya hanya berdiri di bahu jalan dengan rantai besi dalam genggaman tangan yang bergetar.
Kali pertama dihadapkan dengan situasi seperti sekarang membuat cara kerja otaknya tiba-tiba berantakan.
“WOI, SINI LU, BAJINGAN!”
Dieratkannya genggaman pada rantai besi di tangan, bersiap untuk segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi kala didengarnya teriakan dari salah satu lawan. Ia tak begitu buruk dalam teknik bela diri, ia pernah berkelahi lebih dari satu kali, jadi ia rasa dirinya masih bisa hadapi ini.
Yolin bersiap ambil langkah hadapai satu anak yang hendak hampiri dirinya, kala tangan yang datang dari belakang tiba-tiba seret dirinya dengan bekap mulutnya bak penculikan anak kebanyakan.
Ia sempat berontak, semakin panik kala rantai besi di tangan jatuh ke jalan. Namun kalakian, tangan yang bekap mulutnya dilepas dan Yolin akhirnya bisa lihat seorang anak lelaki yang tingginya hampir sama dengan dirinya dorong tubuhnya ke tembok kala mereka berhasil injakan kaki di gang sempit tak jauh dari lokasi tawuran.
“Lu bukan anak eagle, kan? Jangan ke bawah jembatan!”
Yolin bahkan belum sempat cerna semuanya. Kenapa anak-anak ini tawuran di jalan, kenapa tiba-tiba ia dibawa kemari. Bahkan ia juga tak mengerti kenapa lelaki ini selamatkan dirinya padahal dari seragam yang ia kenakan, Yolin yakin ia adalah kawanan yang menjadi musuh Tio dan teman-temannya.
Sial, otaknya terlalu bodoh untuk mencerna semua kejadian hari ini.
Bahkan saat lelaki itu kembali berlari menuju jembatan, Yolin tetap tak bisa muntahkan sepatah kata dari tiap isi kepala. Yang bisa ia ingat hanyalah wajah dan untaian bunyi bahasa yang diucap cepat namun cukup tegas.
Akan ia ingat.
Cukup lama berkecamuk dengan segala isi kepala yang mulai runyam, akhirnya Yolin putuskan untuk pulang. Ikut tawuran dengan seragam sekolah yang masih menempel di badan sama saja dengan cari mati. Ia tak habis pikir dengan isi kepala anak-anak kurang kerjaan itu.
Namun sial, ia harus kembali ke sana untuk dapatkan motor miliknya yang ia yakini sudah mendapat banyak kecupan dari kerikil-kerikil yang orang-orang itu lempar.
Hari ini benar-benar menjengkelkan.
0 notes
Text

I'm home.
Wave lantas beranjak dari tempatnya berdiri sekarang kala suara bel menggema di dalam rumah, sejenak abaikan tumpukan baju bersih, dan berlari kecil menuju pintu hingga tak sadar bawa beberapa hanger baju di tangan.
Kiranya mungkin sang Ibunda akhirnya kembali setelah seminggu berada di kampung halaman. Lantas kala dibukanya pintu, ia ambil ancang-ancang untuk peluk seseorang di depan sana, namun tunggu—
“Salazar?!”
Wave mundur satu langkah ke belakang kala didapatinya lelaki bertubuh tinggi, alih-alih Mamanya. Rentangan tangan yang dimaksudkan untuk beri pelukan selamat datang kepada Mamanya ia tarik kembali. Hanger di dalam genggamannya sampai berhamburan, jatuh ke lantai sebab tangannya tiba-tiba lemas, entah bagaimana.
“Salaz, why are you here?”
Wave sorotkan pandangan pada figur berwajah pucat yang berdiri diam di ambang pintu dengan setelan piyama rumah sakit lengkap dengan salah satu punggung tangan yang berdarah—kiranya bekas infus yang dilepas paksa. Yang lebih tinggi tak suarakan apa-apa, hanya pandangi yang lebih kecil dengan sorot sendu, namun dalam. Taruh banyak tanda tanya yang memang sudah menumpuk di dalam kepala.
Ada yang salah dengan Salazar.
“Sal, kenapa datang ke sini?”
Kendati jawab pertanyaan yang dilempar dengan penuh kebingungan, Salazar tundukkan kepala dalam-dalam. Entah apa maksud dari semua tindakannya sekarang, Wave benar-benar tak paham.
“Salazar—”
“Maaf..”
Wave bungkam, kata maaf yang tiba-tiba diudarakan dengan suara parau buat ia semakin dihantam kebingungan. Ia memang sulit memahami isi kepala Salazar, namun hari ini jauh lebih sulit untuk ia pahami. Ia lagi-lagi pandangi bagaimana kepala itu terangkat, kembali menengadah setelah cukup lama tertunduk dalam.
Sial, mata itu. Wave benci melihat sendu itu menyerobot bersama asing yang menembus relung lalu tinggalkan nyeri di dalam sana. Wave benci bagaimana mata itu tumpahkan kilapan air mata tanpa suara.
“Maaf. Maaf, Wave...”
“Kenapa minta maaf?”
“Maaf...”
Sungguh, ingin berapa kali Salazar ucapkan kata maaf dengan suara parau miliknya. Ingin berapa banyak tetes air mata yang mengalir di pipinya bersama tatap menyakitkan. Wave tak bisa mengerti apa yang ingin Salazar sampaikan dengan kata maaf yang diucap berulang kali.
“Sal, are you okay? Lu kabur dari rumah sakit?”
Wave kikis sedikit jarak antara keduanya, berusaha mendekat hanya untuk pastikan bahwa lelaki di depannya baik-baik saja. Ia mungkin tak mengerti situasi sekarang, namun melihat tangis Salazar yang tak kunjung redam, buat semua perasaan cemas hampiri dirinya.
“Kangen... Gue kangen lu, Wave...”
Ah, akhirnya lelaki itu kembali buka suara. Namun tatap itu tak sepenuhnya berubah, masih sama sendunya bahkan lebih dari yang sebelumnya. Wave hendak raih lengan Salazar kala dua lengan yang lebih besar tarik dirinya, lantas dipeluk erat bersama tangis yang dua kali lipat lebih keras.
Salazar benamkan wajahnya pada pundak Wave yang bergetar. Didekap tiba-tiba dengan tangis yang terdengar menyakitkan, Wave tak tahu harus bertindak bagaimana.
“I'm home, Wave... I finally remembered you.”
Hembusan angin menerpa wajah Wave bersamaan dengan tubuhnya yang tiba-tiba membeku. Pelukan itu terasa lebih berat kala akhirnya Wave cerna dengan baik tiap rentet kata yang diterima oleh rungunya.
Matanya memanas, dihantam ombak perasaan buat Wave kehilangan seluruh fokusnya. Sialan, ia bahkan belum siap mendengar kalimat itu sekarang. Salazar, lelaki itu kenapa tiba-tiba datang dengan kejutan yang tak pernah ia terka sebelumnya.
Wave akhirnya balas pelukan itu, dekap erat tubuh Salazar seolah tak ada kesempatan lagi baginya di esok hari. Bahunya semakin bergetar, seiring tangisnya yang tiba-tiba datang.
Ia mengerti sekarang. Ia mengerti kenapa tatap itu berbeda hari ini, ia mengerti kenapa parau suara itu tak pernah asing di rungunya, ia mengerti kenapa pelukan ini terasa begitu menghangatkan.
Salazar-nya pulang.
Wave mungkin pernah dibuat kecewa atas sandiwara yang Salazar cipta, namun untuk sekarang, ia coba singkirkan logika hanya untuk puaskan egonya yang sedari awal harapkan narasi demikian.
0 notes
Text

Stop denial.
Wave percepat langkahnya kala ia berhasil injakan kaki di lantai tiga gedung kelas. Ada satu hal yang harus ia urus hingga ia harus tunda jam makan siangnya. Jadi saat dilihatnya tujuannya sudah di depan mata, lantas lelaki itu segera mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kelas dua belas IPA satu.
Kelas Simon, itu adalah tujuannya sekarang. Namun, ia memilih berhenti di ambang pintu kala dilihatnya figur yang ingin ia temui masih sibuk dengan setumpuk buku di atas meja. Beberapa anak kelas itu juga masih sibuk menulis di meja masing-masing, buat Wave sungkan untuk masuk lalu mengganggu. Dan ia memilih menunggu di sana, di depan pintu kelas, hingga akhirnya Simon keluar kelas usai bereskan tumpukan buku miliknya.
Lelaki itu hentikan langkah kala dilihatnya Wave berdiri di ambang pintu, sedikit terkejut sebab sudah lama sekali sejak terakhir kali Wave hampiri ia ke kelas saat mereka masih berteman dekat, dulu.
“Loh, Wave, ngapain di sini? Mau nyamperin gue?”
Dan anggukan kecil atas pertanyaannya barusan berhasil cetak senyum tipis milik Simon. “Kenapa mau nyamperin gue?”
“Mau bahas sesuatu.”
Jawaban dingin dengan wajah datar itu sudah cukup buat Simon mengerti bahwa ada hal serius yang ingin Wave sampaikan padanya. Lantas selanjutnya, Simon ajak Wave menepi ke tangga menuju atap, berdiri di dekat sana untuk hindari telinga lain yang tak seharusnya dengar apa yang akan mereka bicarakan.
“Here we are. Mau bahas apa?”
Wave sejenak balas tatapan Simon yang terlihat lebih tenang hari ini, namun tak cukup mampu usir gusar yang kuasai isi kepalanya dari kemarin lusa. Lantas usai ambil napas untuk sekadar tenangkan diri agar tak rancu bicaranya nanti, Wave akhirnya lempar kata.
“Kenapa lu gak buang kertas yang lu temuin waktu itu? Kenapa malah dikasih ke Salaz?”
Kalimat terang-terangan tanpa basa-basi itu ternyata sama sekali tak buat Simon terkejut ataupun kebingungan. Lelaki itu tahu ke arah mana pembicaraan ini, ia tahu apa yang Wave maksudkan soal kertas yang ia temukan.
“Gue cuma ngerasa Salaz pantas buat baca kertas itu.”
Alis yang menukik tajam dan rahang yang mulai mengeras itu akhirnya buat yang lebih tua sadar bahwa tindakannya buat Wave tak senang.
“Sebelumnya gue mau minta maaf karena udah lancang baca kertas itu padahal lu nyuruh gue buat buang kertasnya. Maaf karena gue udah kasih kertas itu ke Salaz. Dan maaf juga karena gak ngerti situasi lu sama Salaz sekarang.”
“Lu emang gak ngerti.”
“Maaf...”
Wave berdecak, pusing tiap kali hadapi kakak kelasnya itu. “Mau lu sebenarnya apa sih, Kak?”
Simon hela napas panjang, dihembuskannya perlahan, lantas kembali fokuskan pandangan pada Wave di depannya.
“Gue cuma mau bantu biar lu bisa temenan lagi sama Salaz, because I know you've been waiting for him all this time.”
“After all the bad things you said about Salaz? Setelah jelek-jelekin Salaz malem itu, terus sekarang lu bilang mau bantu gue buat temenan lagi sama dia? Lu sadar gak sih, Kak, kalo lu tuh labil?”
Simon sejenak diam, tundukkan kepala usai usap wajahnya dengan kasar. Ah, ini memang salahnya. Salahnya yang tak punya pendirian, salahnya yang tak pernah berpikir dua kali sebelum bicara dan bertindak.
“I know, omongan gue emang jahat soal Salaz, tapi gue gak ada niatan buat jelek-jelekin Salaz, Wave.”
“Dan lu sadar gak, kalo lu tuh udah ikut campur urusan gue sama Salaz?”
Simon anggukan kepala, untuk yang satu ini, ia jelas sadar sedari awal. “Gue sadar kok, Wave. Gue udah terlanjur tau semuanya, udah terlanjur denger semua hal tentang lu dan Salaz, so instead of just sitting there, I'd better help you.”
“I'm not asking you to help me.”
“Stop denial, Wave!”
Satu bentakan dari Simon barusan berhasil buat Wave bungkam. Tatapan tajamnya berubah gusar, dan sialnya Simon baru ingat bahwa lelaki itu paling tak suka dibentak. Kalakian, Simon maju selangkah, kikis sedikit jarak antara ia dan Wave.
“Wave...gue tau lu selama ini selalu berharap bisa temenan lagi sama Salaz, gue tau lu seneng waktu Salaz akhirnya balik ke Indonesia setelah enam tahun dia pergi tanpa kabar. Lu udah ceritain semuanya ke gue, dan gak mungkin gue diem aja setelah tau kalo ternyata Salaz amnesia dan sama sekali gak inget sama lu.”
Wave diam, berusaha dengarkan tiap bunyi bahasa yang keluar dari bilah bibir Simon. Mencoba untuk tepis perasaan kesalnya, berusaha beri sedikit pengertian pada lelaki itu, setidaknya sampai ia dengar pernyataan yang masuk akal atas tiap tindakannya selama ini.
“Gue emang sempet kesel sama Salaz. Gue kesel karena dia gak pernah kasih kabar ke lu padahal lu di sini selalu nungguin kabar dari dia. And until I found out that he had amnesia. Gue sempet pengen marah, pengen nonjok Salaz karena lagi-lagi bikin lu sedih. But I realize that until now you are still waiting for him, bahkan setelah kalian udah ketemu lagi.”
“Lu masih berharap sampe sekarang, Wave, gak usah denial. Jujur soal perasaan lu. Gue tau lu masih berharap Salaz bisa inget sama lu, biar kalian bisa temenan lagi kayak dulu. Gue tau lu juga gak sungguh-sungguh waktu bilang kalo lu benci Salaz. Gue tau, Wave.”
Wave lemparkan pandangannya ke sembarang arah, hanya untuk hindari tatapan Simon yang entah kenapa terasa sangat mengintimidasi. Tiap rentet kata yang lelaki itu lempar buat matanya memanas sertakan rasa nyeri di bagian dada. Ia ditampar fakta, dan rasanya sangat menjengkelkan.
“Gue tau pertemanan kita gak sedeket dulu. But, Wave, I want you to know that until now I still consider you like my own little brother. Gue gak suka liat lu sedih terus.”
Wave tundukkan kepala, teguk ludah dengan susah payah usai dengar kalimat Simon barusan. Wave tak tahu harus dengan kalimat apa ia tanggapi tiap bunyi bahasa itu. Ia terlanjur kesal, terlanjur dibuat jengkel oleh Simon yang selalu bertindak tanpa seizinnya. Namun, ia juga tahu, hal yang telah lelaki itu lakukan tak sepenuhnya salah. Wave tahu niat lelaki itu tak sejahat itu walaupun mungkin ia salah dalam menaruh tindakan dan tiap kata.
Wave akhirnya kembali dongakkan kepala, beranikan diri untuk balas tatapan yang lebih tua. Sebelum akhirnya ucap beberapa kata setelah cukup lama bungkam.
“Setelah ini lu gak perlu ikut campur urusan gue sama Salaz. Gue tau niat lu baik, tapi gue gak suka, Kak.”
Simon tarik sudut bibir untuk bentuk senyuman manis miliknya, kemudian beri anggukan kepala setelahnya. “Maaf, ya.”
Wave akhirnya anggukan kepala, ingin masalah ini selesai dan berharap tak akan ada lagi keributan antara ia dan Simon.
0 notes